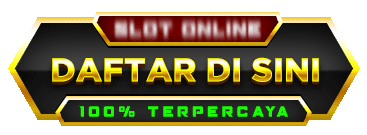Ketika minggu lalu saya berkunjung ke toko buku, saya melihat ada dua buah buku Iwan Simatupang di rak buku baru, yaitu : Tegak Lurus dengan Langit (kumpulan cerpen) dan kumpulan esainya (saya lupa judulnya). Saya lalu ingat, rasanya saya pernah membeli satu (dengan harga obral sangat murah) novel karya Iwan Simatupang di sebuah pameran buku di Jakarta beberapa waktu silam. Sesampainya di rumah, saya cari novel tersebut. Ketemulah Kering di antara koleksi buku-buku saya.
Sebelumnya, saya tidak ingat apakah saya pernah membaca karya Iwan Simatupang, seorang sastrawan kita kelahiran Sibolga, Sumatera Utara (satu kampung gak ya dengan Sitor?) pada 18 Januari 1928 dan meninggal dunia empat puluh dua tahun kemudian (masih sangat muda ya?). Tepatnya 4 Agustus 1970. Ia telah banyak menulis cerita pendek dan novel, di antaranya : Merahnya Merah dan Ziarah. Konon, ia adalah seorang eksistensialis yang karyanya sulit dipahami.
Saya tidak tahu apakah ia benar seorang eksistensialis, tetapi yang jelas Kering telah membuat kening saya berkerut cukup banyak dalam upaya memahaminya. Eksistensialisme sendiri adalah salah satu cabang ilmu filsafat abad ke-20 yang menolak pemikiran metafisika tradisional dari Kant dan Hegel, demikian yang saya kutip dari Ensiklopedi Indonesia. Dikatakan pula bahwa ajaran pokok eksistensialisme adalah : "Kita dan benda-benda umumnya ada dan hanya urusan yang serba tak masuk akal (absurd) yang kita sebut hidup"
Saya tak terlalu paham maksudnya, tetapi baiklah biarkan saya bicara tentang Kering saja.
Novel ini terbit pertama kali tahun 1972, saat mana Orde Baru tengah menancapkan kuku-kuku kekuasaannya dengan berbagai program untuk "kesejahteraan rakyat". Salah satu program pemerintah itu adalah transmigrasi, memindahkan penduduk di Pulau Jawa ke pulau-pulau luar Jawa dengan slogan megah "demi masa depan yang lebih baik". Penduduk yang dipindahkan itu, baik secara paksa ataupun suka rela, dalam novel ini umumnya adalah orang-orang "pelarian". Ada yang lari dari tanggungjawab setelah menghamili pacarnya, ada kriminal yang kabur setelah menggelapkan uang perusahaan dan ada seorang mahasiswa yang bosan dengan ruang kuliah serta buku-buku tebal di perpustakaan. Mahasiswa inilah tokoh utama cerita yang disebut oleh penulisnya sebagai "Tokoh Kita". Iwan tak memberi tokoh-tokoh ceritanya nama yang lazim terdapat pada novel. Ia hanya memberi mereka sebutan seperti : "Tokoh Kita", "Si Gemuk Pendek" atau "Si Kacamata".
Dikisahkan bahwa Tokoh Kita ini adalah seorang mahasiswa sangat cerdas yang sering mendebat dosen-dosen yang menurutnya kurang memuaskan dalam mengajar, sehingga para dosen kewalahan dibuatnya. Alih-alih bangga padanya, mereka malah bersikap memusuhi. Mereka lega saat akhirnya Tokoh Kita memutuskan berhenti kuliah dan memilih ikut transmigrasi.
Sebetulnya : Dia tak memilih untuk jadi transmigran. Dia menjadi transmigran karena pikiran itulah saat itu kebetulan menyembul dalam dirinya. Bila yang kebetulan nyembul ketika itu adalah kehendak untuk jadi astronot misalnya, terang tak bakal di perkampungan transmigran sunyi tandus ini dia sekarang. Tapi, sebutlah di Cape Kennedy (hal.37)
Maka, dimulailah kehidupan baru Tokoh Kita di daerah transmigrasi : membuka hutan, mencangkuli tanah, menanam bibit-bibit, menanti hujan datang...
Hujan? Dia tertawa. Masih ingatkah ia, apa bagaimana hujan? Apa bagaimana rasanya basah? Dingin? Dia menggelepar. Serasa tak kuasa lagi dia mengkhayalkannya kembali. Hujan adalah pengertian sejarah purbakala baginya (hal.52)
Ya, ternyata hanya kemarau panjanglah yang setia mengunjungi mereka : Kering. Ladang-ladang telah jadi dataran tanah retak..Matahari lohor tak kenal ampun. Teriknya melecut langit. Embun segumpal tak ada. Udara bergetar (hal.1)
Keadaan yang demikian akhirnya membuat para transmigran itu menyerah, lantas satu demi satu mereka pergi meninggalkan ladang-ladang kering tersebut. Hanya Tokoh Kita seorang tetap tinggal bertahan menghadapi terpaan kemarau yang membakar bumi, mencoba untuk tidak menyerah kepada panas, kepada haus, dan rasa lapar :
Silakan kau datang, hai lapar! Bumi kecil ini bakal tembus juga aku gali. Ingin tembus di mana aku ya? Texas? Ah, tidak! Bau minyak. California? Tidak. Terlalu banyak nilon dan neon. Terlalu banyak kenes dan uang pada jutawan-jutawan model baru seperti Frank Sinatra dan Sammy Davis Jr. Mexico barangkali?
Dan ia terus menggali tanah itu dengan harapan bertemu mata air, sambil menahankan lapar sebab persediaan makanan telah ludes, sampai akhirnya tak tahan lagi. Ia ditemukan pingsan oleh petugas transmigrasi di pondoknya yang terbakar lalu dibawa ke kota.
Di kota inilah Tokoh Kita mengajak pembaca "berlari" menyusuri kehidupan, bertemu orang-orang dan mengalami berbagai peristiwa yang terkadang menurut saya agak kelewat dramatis, misalnya :
Kakek-kakek menari-nari, terkekeh-kekeh. Nenek-nenek main jungkir balik. Pria-pria memeluk wanita yang bukan istrinya. Wanita-wanita membiarkan dirinya dicium pria yang bukan suaminya. Juru rawat menjulurkan lidahnya pada dokter-dokter. Pemegang-pemegang buku mencubiti perut direktur-direktur. Mahasiswa memelonco mahaguru..(hal 169).
Atau ini : Ketika gerimis pertama turun, dunia serasa kiamat. Mereka seperti kemasukan setan. Ada yang melompat tinggi sekali. Dengan sendirinya jatuhnyapun deras sekali. Otaknya berhamburan. Ada yang berteriak keras sekali. Sejak itu hilang suaranya. Selama-lamanya. Ada yang, setelah merobek baju dan celananya lebih dulu, merobek mukanya sendiri. Sejak itu dia buta. Sejak itu, dia berjari 10 kurang 1, 10 kurang 2, atau kurang lagi (hal.169)
Tetapi Iwanpun tak lupa berkelakar, meski humor-humornya terasa sinis dan penuh sindiran : Kota beroleh senam baru. Yaitu : menatap lama-lama, tinggi-tinggi, ke langit. Banyak penduduk yang karenanya mengeluh diserang kejang leher. Balsem gosok--dalam dan luar negeri, tulen dan palsu, entah benar-benar balsem gosok, entah tidak--laris. Jutawan-jutawan balsem baru timbul (hal. 165).
Melalui Tokoh Kita ini juga, Iwan melontarkan kritik-kritiknya kepada pemerintah (Orde Baru) beserta aparatnya, khususnya mengenai penyelenggaraan transmigrasi yang akhirnya terkesan hanya sekedar "memindahkan masalah", bukan menyelesaikannya. Kritiknya juga ditujukan pada orang-orang / kehidupan kota yang semakin bendawi dan sering menghalalkan segala cara demi kehidupan duniawi. Dalam Kering ini, Iwan seperti seseorang yang tengah menumpahkan kemarahannya pada keadaan sekitar yang mungkin dinilainya telah banyak menyimpang. Kegelisahan seorang sastrawan.
Maka, lalu akhir cerita ini menjadi tidak terlalu penting lagi buat saya, sebab saya telah cukup merasa "asyik" sekaligus "pusing" dengan keseluruhan pemikiran penulisnya yang tumpah ruah di sepanjang halaman-halaman buku. Kendati, barangkali sedikit sekali yang bisa benar-benar saya pahami.