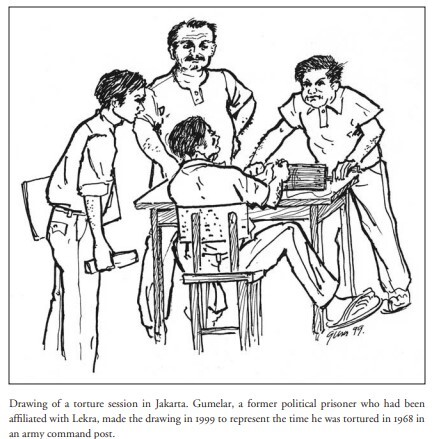Sebelum mulai membaca ini, saya punya satu pertanyaan besar soal pembantaian 1965-1966 sebagai sebuah diskursus akademik: adakah riset/investigasi/penelitian terbaru selama 5 tahun terakhir? Kita butuh temuan atau argumentasi baru yang lebih kuat untuk mempertahankan isu ini di tengah rezim impunitas.
Menurutku, kajian terakhir dan sulit terbantahkan masih dipegang oleh Jess Melvin lewat "Mekanika Pembunuhan Massal 1965-1966". Temuannya berupa arsip resmi militer yang terencana di Aceh. John Roosa mengakuinya sebagai "terobosan dalam historiografi pembunuhan massal".
Berawal dari mendatangi lokasi kuburan massal di sejumlah provinsi, kajian terbaru Roosa ini justru banyak menemukan banyak perspektif baru di ranah ekonomi dan budaya. Saat meriset puluhan literatur soal genosida, Roosa mengaku tak banyak menemukan sejarawan atau peneliti yang menganalisis praktik-praktik pembunuhan massal dibarengi dengan politik pembersihan komunisme di dunia. Ada semacam upaya pemisahan menjadi dua diskursus berbeda oleh para sejarawan.
Padahal, kata Roosa, "sejak Revolusi Rusia 1917 hingga keruntuhan Uni Soviet pada 1991, hampir semua, kalau tidak semua, kampanye berdarah melawan komunisme di seluruh dunia sekaligus merupakan kampanye melawan kelompok buruh terorganisir".
Jika melihat pembantaian lewat perspektif dinamika kapitalisme, kita akan menemukan pola kemiskinan struktural antar generasi. Roosa menemukan pola itu saat banyak korban 1965-1966 di Sumatera Selatan adalah serikat buruh perkebunan yang melek secara politik dan bisa mengorganisir diri untuk menuntut upah dan hidup layak. Politik eufemisme bahasa "buruh" menjadi "karyawan" yang dilakukan Orde Baru bertahun-tahun setelahnya membuat keadaan makin runyam: serikat buruh kehilangan kenangan masa lalu dan sulit membayangkan rencana masa depan. Buruh miskin akan tetap jadi buruh miskin.
Ia juga riset ke sejumlah lokasi ke Jawa Tengah, termasuk Surakarta yang merupakan episentrum gerakan politik radikal penentang kolonialisme terkuat di awal abad 20. Menurut Takashi Shiraishi, Surakarta termasuk dalam periode "zaman bergerak" yang politis dan terorganisir secara masif menentang penjajahan. Sayangnya, pembantaian yang dilakukan Soeharto, kata Roosa, "menguburkan pengalaman politik egaliter puluhan tahun ini dengan menghidupkan kembali budaya aristokrasi turun-temurun Surakarta dari masa kolonial".
Ada pola yang berbeda dalam pembantaian di tiap provinsi. Di Sumatera Selatan dan Jawa Barat, misalnya, tidak semasif di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Konteks pimpinan militer dan bagaimana ormas lokal diorganisir untuk ikut membunuh menjadi faktor penentu. Misalnya di Bali, yang praktik pembantaian berlangsung 'agak telat' karena dimitigasi oleh pimpinan militer setempat yang notabene merupakan loyalis Sukarno. Ada jeda sekitar dua bulan, sampai akhirnya sang pimpinan militer diganti oleh Soeharto dan pembantaian tak terhindarkan.
"Bali menjadi provinsi tempat pembunuhan terjadi secara sangat luas, dengan jumlah kematian per kapita yang mungkin tertinggi di seluruh negeri," kata Roosa.
Walau ia sendiri tak mengesampingkan bahwa jumlah kematian di Jawa Timur bisa jadi yang terbesar di antara semua provinsi, yang angka korbannya mencapai 150.000 jiwa.
Terima kasih banyak untuk Roosa karena berkat buku ini saya harus membaca lebih jauh lagi soal kasus pembantaian di Cluring, Banyuwangi, dan kisah bekas petinggi PKI di Banyuwangi untuk riset personal saya soal kampung halaman.
Buku yang mengesankan!