Ronny Agustinus's Blog
October 26, 2017
Fiksi Amerika Latin pasca Boom
Makalah untuk diskusi meja bundar "Saling Silang Cerita Dua Daratan", Komunitas Salihara, 28 Oktober 2017.
Published on October 26, 2017 19:14
March 7, 2017
"Duabelas Perempuan di Tahun Keduabelas", oleh Subcomandante Marcos
Terjemahan ini pertama kali dimuat di Subcomandante Marcos, Bayang Tak Berwajah: Dokumen Perlawanan Tentara Pembebasan Nasional Zapatista, terjmh. dan kompilasi Ronny Agustinus (Yogyakarta: Insist Press, 2003), hlm. 255-261.

Selang tahun keduabelas EZLN, puluhan kilometer, dan jarak maha jauh dari Peking, 12 orang perempuan berkumpul tanggal 8 Maret dengan wajah-wajah terhapus…
1. Kemarin…Seraut wajah terbalut hitam masih menyisakan mata dan beberapa helai rambut yang terjuntai dari kepala. Dalam tatapan itu terbersitlah seorang yang mencari. Karaben M-1 digenggam di depan, dalam kuda-kuda yang dinamakan “penyerangan”, dan sepucuk pistol tersarung di pinggang. Di sisi kiri dada perempuan itu, tempat harapan dan keyakinan bersemayam, tersematlah pangkat Mayor Infantri pasukan tentara pemberontak, yang pada subuh 1 Januari 1994 menamai diri mereka Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Di bawah komandonya, berdiri sepasukan pemberontak yang menduduki San Cristóbal de las Casas, bekas ibukota negara bagian Chiapas, Meksiko Tenggara. Alun-alun San Cristóbal senyap. Hanya lelaki dan perempuan pribumi yang dikomandoinyalah yang jadi saksi saat Mayor itu, seorang perempuan pemberontak suku Tzotzil, merebut bendera nasional dan memberikannya kepada komandan-komandan pergerakan, mereka yang disebut “Komite Klandestin Revolusioner Adat”. Di radio, sang Mayor berucap: “Bendera telah kami selamatkan. 10-23 ganti.” 1 Januari 1994, pukul 02.00 waktu tenggara, atau pukul 01.00 tahun baru di belahan dunia lainnya, dan ia telah menunggu 10 tahun lamanya untuk bisa mengucapkan kalimat tersebut. Ia tiba di pegunungan rimba raya Lacandon bulan Desember 1984. Belum genap 20 tahun usianya, namun sekujur tubuhnya telah membawa bekas-bekas riwayat penindasan penduduk adat. Bulan Desember 1984, perempuan coklat ini berkata “Cukup sudah!”, namun ia mengucapkannya begitu lirih sampai cuma ia seorang yang mendengar. Bulan Januari 1994, perempuan ini beserta sekian ribu penduduk adat bukan cuma mengucapkan, namun meneriakkan lantang-lantang “Cukup sudah!”, sampai seluruh dunia mendengar mereka…Di luar San Cristóbal, sekelompok pemberontak lainnya yang dikomandoi seorang pria –satu-satunya yang berkulit terang dan berhidung besar di antara penduduk pribumi yang menyerbu kota—baru saja rampung mengambil alih markas besar kepolisian. Dari penjara yang tersembunyi itu dibebaskanlah orang-orang pribumi yang menghabiskan malam tahun baru di bui akibat kejahatan terberat di wilayah tenggara Chiapas: jadi orang miskin. Eugenio Asparuk, suku Tzetzal, adalah nama Kapten pemberontak yang bersama-sama si hidung besar mengawasi penggeledahan dan penyitaan markas besar tersebut. Saat pesan sang Mayor tiba, Kapten pemberontak Pedro, suku Chol, telah selesai mengambil alih markas besar Polantas Federal dan mengamankan jalan raya yang menghubungkan San Cristóbal dengan Tuxtla Gutierrez. Kapten pemberontak Ubilio, suku Tzeltal, telah menguasai jalan masuk sisi utara kota berikut simbol uluran tangan pemerintah pada masyarakat adat, Institut Adat Nasional. Kapten pemberontak Guillermo, suku Chol, mengambil posisi di titik tertinggi kota. Dari situ ia memberi aba-aba dengan tatapannya. Rasa kaget yang tercekat mengintip dari balik jendela rumah-rumah dan gedung-gedung. Kapten pemberontak Gilberto dan Noe, masing-masing suku Tzotzil dan Tzeltal, tapi sama-sama pembangkang, mengakhiri pendudukan markas besar kepolisian hukum negara bagian lantas membakarnya sebelum berbaris mengamankan sisi kota yang mengarah menuju barak-barak Zona Militer ke-31 di Rancho Nuevo.Pukul 02.00 waktu tenggara, 1 Januari 1994, lima petinggi pemberontak, lelaki-lelaki pribumi, mendengar di radio suara pimpinan mereka, seorang perempuan pribumi pemberontak yang berucap, “Bendera telah kami selamatkan. 10-23 ganti.” Mereka mengulanginya pada pasukan mereka, semua lelaki perempuan pribumi pemberontak, lantas menerjemahkan ucapan berikut “Kita telah mulai…”Di istana kotapraja, sang Mayor mengorganisir posisi pertahanan guna melindungi orang-orang yang kini memerintah kota—kota yang sekarang ada dalam kekuasaan pemberontak pribumi. Seorang perempuan bersenjatalah yang melindungi mereka.Di antara para komandan pemberontak ada seorang perempuan imut, bahkan lebih imut ketimbang mereka yang di sekitarnya. Seraut wajah terbalut hitam masih menyisakan mata dan beberapa helai rambut yang terjuntai dari kepala. Dalam tatapan itu terbersitlah seorang yang mencari. Senapan laras pendek kaliber 12 tergantung di punggungnya. Mengenakan gaun tradisional perempuan San Andrés, Ramona turun gunung bersama seratus lebih perempuan lainnya, menuju San Cristóbal di malam terakhir tahun 1993 itu. Bersama Susana dan lelaki-lelaki adat lainnya ia adalah bagian dari komando perang Indian yang pada tahun 1994 melahirkan Komite Klandestin Revolusioner Adat - Komando Jenderal EZLN. Nantinya, Comandanta Ramona dengan imut tubuhnya dan kecerdasannya akan mengejutkan pers internasional saat ia muncul di sela Dialog Perdamaian pertama yang diselenggarakan di Katedral. Ia keluarkan dari tas ranselnya, bendera nasional yang direbut sang Mayor tanggal 1 Januari itu. Ramona tak tahu kapan, begitu pula kita, tapi dalam tubuhnya berdiam penyakit yang menggerogoti dirinya dalam gigitan-gigitan lebar, yang meredupkan suara dan tatapan matanya. Ramona dan sang Mayor, perempuan satu-satunya dalam delegasi Zapatista yang tampil di hadapan dunia, untuk pertama kalinya mencanangkan: “Demi segala niat dan tujuan kami telah mati, kami tak berarti apa-apa.” Dengan ini mereka belum memperhitungkan segala jenis pelecehan dan keterbelakangan. Sang Mayor menerjemahkan untuk Ramona pertanyaan para wartawan. Ramona mengangguk dan mengerti, seakan-akan jawaban yang diminta darinya telah ada di sana, dalam tubuh imut yang menertawakan bahasa Spanyol dan perilaku wanita kota. Ramona tertawa seakan tidak tahu dirinya sedang sekarat. Andaipun tahu, ia tetap tertawa. Sebelum ini ia tidak eksis bagi siapapun, sekarang ia eksis, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang perempuan adat, sebagai seorang perempuan pemberontak. Sekarang Ramona hidup, perempuan dari ras yang harus mati terlebih dulu untuk bisa hidup…Sang Mayor mengawasi cahaya memenuhi jalan-jalan San Cristóbal. Para prajuritnya mengorganisir pertahanan kota tua Jovel dan perlindungan bagi para penduduknya yang sedang lelap tertidur, orang-orang pribumi dan mestizo, yang sama-sama terkejut. Sang Mayor, perempuan pribumi pemberontak ini telah menduduki kota mereka. Ratusan penduduk pribumi bersenjata mengepung kota tua. Seorang perempuan bersenjatalah yang memimpin mereka…Sekian menit kemudian para pemberontak menduduki Las Margaritas, sekian jam setelahnya pasukan pemerintah yang mempertahankan Ocosingo, Altamirano, dan Chanal menyerah. Huixtan dan Oxchuc direbut oleh sekelompok prajurit yang menuju ke arah penjara utama San Cristóbal. Tujuh kota sekarang ada dalam genggaman kelompok pemberontak yang tunduk pada 7 kata sang Mayor:Perang demi kata-kata sekarang telah dimulai…Di tempat berbeda, para perempuan lainnya yang sama-sama pribumi dan sama-sama pembangkang, telah menyusun ulang potongan sejarah yang diberikan pada mereka. Potongan yang sampai tanggal 1 Januari 1994 itu selalu dibopong dalam kebisuan. Tak juga nama ataupun rupa mereka punya:IRMA. Kapten Infantri Pemberontak. Irma, perempuan suku Chol, membawahi sepasukan gerilya yang merebut alun-alun Ocosingo tanggal 1 Januari 1994 itu. Dari salah satu sisi taman kota, bersama tentara-tentara yang dikomandoinya, ia menyerang garnisun yang terletak dalam istana kotapraja sampai mereka menyerah. Lantas Irma menggerai kepang rambutnya. Rambut itu terjatuh ke pinggang seakan berkata “inilah aku, yang baru dan merdeka”. Rambut Kapten Irma bersinar, dan terus bersinar walau malam telah menyelimuti Ocosingo yang ada dalam genggaman kaum pemberontak…LAURA. Kapten Infantri Pemberontak. Suku Tzotzil. Gigih dalam perang dan gigih dalam belajar-mengajar. Laura menjadi kapten dalam unit yang beranggotakan lelaki semua. Bukan cuma itu, merekapun semuanya anggota baru. Dengan sabar, sesabar gunung yang melihatnya tumbuh dewasa, Laura mengajar dan memberi perintah. Kalau lelaki-lelaki yang dibawahinya itu ragu, ia memberi contoh dengan mengerjakannya sendiri. Tak ada yang menggotong beban dan berjalan kaki sebanyak dia. Setelah penyerbuan Ocosingo, ia memerintahkan unitnya mundur. Begitu teratur dan beres. Wanita berkulit terang ini jarang bicara, tapi ia menggenggam di tangannya sepucuk karaben yang direbutnya dari seorang polisi yang memandang seorang wanita dusun tak lebih dari sosok untuk dihina atau diperkosa. Setelah menyerah, polisi itu kabur dalam celana kolornya, persis mereka lainnya yang sampai hari itu percaya bahwa wanita cuma berguna di dapur atau untuk dihamili…ELISA. Kapten Infantri Pemberontak. Ibarat piala perang, ia membawa dalam tubuhnya pecahan-pecahan mortir yang tertanam selamanya di situ. Ia sedang mengatur pasukannya tatkala barisan pemberontak terputus dan sebuah bola api menggulung pasar Ocosingo dengan darah. Kapten Benito terluka dan kehilangan matanya. Sebelum pingsan, ia sempat memberi penjelasan dan aba-aba: “Aku kena, Kapten Elisa ambil alih”. Kapten Elisa sendiri telah terluka saat ia berhasil membawa segerombolan prajurit keluar dari pasar itu. Kalau Kapten Elisa, perempuan suku Tzeltal itu memberi perintah, suaranya cuma menggumam lirih… tapi tiap orang patuh…SILVIA. Kapten Infantri Pemberontak. Ia terperangkap 10 hari di Ocosingo yang telah jadi sarang tikus sejak tanggal 2 Januari itu. Menyamar sebagai warga negara biasa, ia berlari tergesa-gesa sepanjang kota yang penuh berisi tentara federal, tank, dan meriam. Di satu pos penjagaan militer ia diberhentikan. Tapi segera saja mereka membolehkannya lewat. “Tak mungkin wanita semuda dan selembut itu anggota pemberontak”, kata tentara-tentara itu saat melihatnya pergi. Sesudah bergabung kembali bersama unitnya di pegunungan, perempuan suku Chol ini tampak murung. Dengan hati-hati, aku tanya kenapa gelak tawanya berkurang. “Di Ocosingo situ,” jawabnya dengan kepala tertunduk, “di Ocosingo kutinggalkan ranselku berisi semua kaset lagu yang telah kukoleksi, kini kita tak punya apa-apa.” Senyap, kepedihannya tergolek di tangannya. Aku tak berkata apa-apa, kusampaikan belasungkawaku dan kulihat dalam perang tiap-tap orang kehilangan apa yang paling ia cintai…MARIBEL. Kapten Infantri Pemberontak. Ia mengambil alih stasiun radio Las Margaritas saat unitnya menyerbu kotapraja itu tanggal 1 Januari 1994. Sembilan tahun penuh ia hidup di pegunungan untuk bisa duduk di depan mikrofon dan mengucapkan: “Kami ini hasil dari 500 tahun perjuangan; pertama kami berjuang melawan perbudakan…” Transmisinya tak berjalan baik karena alasan-alasan teknis, dan Maribel pindah posisi untuk melindungi sisi belakang unitnya yang bergerak menuju Comitan. Berhari-hari sesudahnya ia bertugas sebagai penjaga tawanan perang, Jenderal Absalon Castellanos Dominguez. Maribel suku Tzeltal dan umurnya belum genap 15 tahun saat ia tiba di pegunungan Meksiko Tenggara. “Masa terberat dalam 9 tahun itu adalah saat aku harus mendaki bukit pertama yang dijuluki ‘bukit akhirat’, sesudah itu semuanya gampang,” kata perwira pemberontak ini. Tatkala Jenderal Castellanos Dominguez dikembalikan ke pemerintah, Kapten Maribel adalah pemberontak pertama yang melakukan kontak dengan pemerintah. Komisaris Manuel Camacho Solis mengulurkan tangan padanya dan bertanya berapa umurnya. “502,” jawab Maribel, yang menghitung tahun keseluruhan sejak pemberontakan dimulai…ISIDORA. Infantri Pemberontak. Isidora pergi ke Ocosingo sebagai tamtama di hari pertama bulan Januari itu. Dan sebagai tamtama Isidora meninggalkan Ocosingo yang bermandi api, setelah berjam-jam lamanya berjuang menyelamatkan unitnya, sekitar 40 orang lelaki yang terluka. Dia juga menyimpan pecahan-pecahan mortir di lengan dan kakinya. Saat Isidora tiba di unit perawatan untuk menyerahkan mereka yang terluka, ia meminta sedikit air dan bangkit berdiri lagi. “Mau ke mana kau?” tanya mereka sambil mencoba mengobati luka-luka yang merobek-melukisi wajahnya serta memerahkan seragamnya. “Menjemput yang lain,” jawab Isidora sambil mengokang lagi. Mereka mencoba menghentikannya tapi tak mampu. Tamtama Isidora bersikukuh ia harus kembali ke Ocosingo menyelamatkan compañeros lainnya dari nada-nada kematian yang dialunkan oleh mortir dan granat. Mereka sampai harus memenjarakannya untuk menghentikannya. “Paling tidak saat aku dihukum aku tidak turun pangkat,” kata Isidora sembari menunggu dalam kamar yang baginya tampak seperti kurungan. Berbulan-bulan kemudian, saat mereka menganugerahinya bintang jasa yang menaikkannya jadi perwira infantri, Isidora, seorang Tzeltal dan Zapatista, menatap bintang itu terlebih dahulu lalu menatap komandannya, dan bertanya seakan-akan ia sedang dihina “Kenapa?”… Tapi ia tidak menunggu jawabannya…AMALIA. Letnan satu di unit rumah sakit. Amalia punya gelak tawa tercepat di seluruh wilayah Tenggara Meksiko. Saat ia menjumpai Kapten Benito tergeletak tak sadar bergenang darah, ia menyeretnya ke tempat yang lebih aman. Ia menggendongnya di punggung dan membawanya keluar dari lingkaran kematian yang mengitari pasar. Tatkala seseorang mengusulkan untuk menyerah, Amalia, taklid akan darah Chol yang mengalir di nadinya, naik pitam dan mulai membantah. Tiap orang menyimak, sekalipun di atas mereka ledakan-ledakan begitu bengis dan peluru-peluru berdesingan. Tak seorang pun menyerah…ELENA. Letnan di unit rumah sakit. Saat bergabung dengan EZLN ia buta huruf. Di sana ia belajar membaca, menulis, serta apa yang disebut obat-obatan. Dari mengobati diare dan menyuntikkan vaksin, ia kini menangani mereka yang terluka di rumah sakit kecil yang sekaligus jadi rumah, gudang, dan farmasi. Dengan jerih payah ia mengeluarkan cuilan-cuilan mortir yang dibawa orang-orang Zapatista di tubuh mereka. “Ada yang bisa aku buang, ada yang tidak,” kata Elena, suku Chol pemberontak, seolah-olah ia sedang membicarakan kenangan dan bukan potongan-potongan logam…Di San Cristóbal, pagi hari 1 Januari 1994 itu, ia bercakap dengan si hidung putih besar: “Seseorang baru saja ke mari bertanya-tanya tapi aku tak paham bahasanya, barangkali Inggris. Entah fotografer atau bukan tapi ia bawa kamera.”“Aku segera ke sana,” kata si hidung besar sambil merapikan topeng skinya.Ke dalam kendaraan dibawa pulalah senjata-senjata yang direbut dari markas polisi dan ia meluncur menuju pusat kota. Mereka mengeluarkan senjata-senjata itu dan membagikannya kepada penduduk-penduduk adat yang berjaga di seputar istana kotapraja. Orang asing itu turis yang bertanya apakah ia bisa meninggalkan kota. “Tidak,” jawab si topeng ski yang kelebihan hidung itu, “lebih baik kau kembali ke hotelmu. Kami tak tahu apa yang bakal terjadi.” Turis itu pergi setelah meminta izin merekam dengan kamera videonya. Seraya pagi datang, datang pulalah orang-orang yang ingin tahu, wartawan-wartawan dan pertanyaan-pertanyaan. Si hidung besar menjawab dan menjelaskannya pada penduduk setempat, turis, dan wartawan. Mayor ada di belakangnya. Si topeng ski menjawab dan bercanda. Perempuan bersenjata itu mengawasi di baliknya.Seorang wartawan, dari balik kamera televisi bertanya: “Dan siapa Anda?” “Siapa aku,” jawab si topeng ski ragu-ragu seakan sedang melawan kantuk setelah malam berkepanjangan. “Ya,” desak si jurnalis, “siapakah Anda ini, ‘Komandan Macan’ atau “Komandan Singa’?” “Bukan,” jawab si topeng ski sambil mengucek matanya yang kini penuh berisi kejemuan. “Jadi, siapa nama Anda?” tanya si wartawan sambil menyorongkan kamera dan mikrofonnya. Si topeng ski berhidung besar itu menjawab “Marcos. Subcomandante Marcos”… Di atas kepala kapal-kapal Pontius Pilatus mulai berdengung…Sejak itulah, kisah tertibnya aksi militer dalam pendudukan San Cristóbal mulai meremang. Terhapuslah fakta bahwa seorang perempuan, seorang perempuan dusun pemberontaklah yang mengkomandoi seluruh operasi. Peran serta semua perempuan dalam aksi-aksi lain tanggal 1 Januari itu, serta sepanjang 10 tahun jalan berliku lahirnya EZLN, jadi dinomorduakan. Wajah-wajah di balik topeng-topeng ski jadi makin anonim saat semua cahaya mengarah ke Marcos. Sang Mayor diam saja, ia terus menjagai sisi belakang si hidung besar yang namanya sekarang tersohor ke seluruh dunia. Tak seorang pun bertanya siapa namanya…Subuh 2 Januari 1994, masih perempuan yang sama itu jugalah yang memimpin penarikan mundur dari San Cristóbal untuk berbalik ke pegunungan. Ia kembali ke San Cristóbal 50 hari setelahnya sebagai bagian dari rombongan pengawal yang menjaga keamanan delegasi CCRI-CG dari EZLN dalam Dialog di Katedral. Beberapa jurnalis perempuan mewawancarainya dan menanyakan namanya. “Ana Maria, Mayor Pemberontak Ana Maria,” jawabnya dengan tatapan matanya yang gelap. Ia tinggalkan Katedral dan menghilang sepanjang sisa tahun 1994 itu. Seperti compañera-compañera lainnya, ia mesti menunggu, ia mesti diam…Tiba bulan Desember 1994, 10 tahun sejak ia menjadi tentara, Ana Maria menerima tugas menyiapkan penerobosan blokade militer yang dipasang pemerintah di sekeliling rimba raya Lacandon. Subuh 19 Desember, EZLN mengambil posisi di 38 kotapraja. Ana Maria mengkomandoi aksi di kotapraja-kotapraja Altos di Chiapas. Duabelas perwira perempuan bersamanya dalam aksi itu: Monica, Isabela, Yuri, Patricia, Juana, Ofelia, Celina, Maria, Gabriela, Alicia, Zenaida, dan Maria Luisa. Ana Maria sendiri menangani kotapraja Bochil.Setelah penyebaran pasukan Zapatista, perwira-perwira tinggi tentara federal memerintahkan diam seribu bahasa atas bobolnya blokade, dan media massa menuliskannya sebagai aksi “propagandis” EZLN belaka. Harga diri kaum federal sangat terluka: Zapatista sanggup lolos dari blokade dan yang lebih menghina lagi, seorang perempuanlah yang mengkomandoi unit yang menduduki pelbagai wilayah kotapraja. Jelas hal ini tidak bisa diterima dan sejumlah besar uang harus dikucurkan agar kejadian ini tertutupi selamanya.Karena aksi-aksi tak sengaja para compañerosbersenjatanya, serta aksi-aksi sengaja pemerintah, peran Ana Maria dan kaum perempuan Zaptista memudar dan jadi tak terlihat…
2. Hari IniAku hampir rampung menuliskan ini saat seseorang lainnya tiba…Doña Juanita. Setelah wafatnya Pak Tua Antonio, doña Juanita membiarkan ritme hidupnya melambat selambat saat ia menjerang kopi. Meski kuat secara fisik, doña Juanita mengabarkan bahwa ia akan mati. “Jangan konyol, nek,” kataku, segan menatap matanya. “Kau ini…,” jawabnya, “kalau untuk hidup kita mesti mati, maka tak satupun bisa menghalangiku mati, apalagi bocah kurang ajar sepertimu,” berkata dan mengumpatlah doña Juanita, istri Pak Tua Antonio, seorang perempuan pemberontak seumur hidupnya, dan seperti terlihat, seorang pemberontak bahkan dalam menjawab panggilan mautnya…Dari simpang lain blokade terlihatlah…Ia. Ia tak punya pangkat militer, seragam, ataupun senjata. Ia seorang Zapatista meski hanya ia seorang yang tahu. Ia tak punya wajah ataupun nama, seperti layaknya Zapatista. Ia berjuang demi demokrasi, kebebasan, dan keadilan, sama seperti Zapatista. Ia bagian dari apa yang dinamakan EZLN “masyarakat sipil”. Ia orang tanpa partai, orang yang tak jadi milik “masyarakat politik” yang tersusun atas aturan-aturan dan pimpinan-pimpinan partai politik. Ia sebagian dari kerumitan itu, tapi bagian sesungguhnya dari suatu masyarakat yang, hari demi hari, mengucapkan sendiri “Sudah, cukup!”Pertama ia kaget mendengar ucapannya sendiri, tapi kemudian, berazaskan kekuatan yang timbul dari mengulang-ulangnya, dan terlebih-lebih, menghidupinya, ia tak lagi gentar akan mereka, tak lagi gentar akan dirinya sendiri. Ia kini seorang Zapatista. Ia telah menggabungkan nasibnya dengan nasib orang-orang Zapatista dalam igauan baru yang begitu menakutkan partai-partai politik dan kaum intelektual Kekuasaan: Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Ia telah berjuang melawan tiap orang, melawan suaminya, kekasihnya, pacarnya, anak-anaknya, temannya, saudara lelakinya, ayahnya, kakeknya. “Kau sinting,” begitulah penilaian yang lazim. Ia tinggalkan banyak hal di belakangnya. Apa yang ia tinggalkan jauh lebih besar ketimbang apa yang ditinggalkan para pemberontak lain yang memang sudah tak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Segala sesuatunya, dunianya, menghendaki ia melupakan “orang-orang Zapatista gila itu”, dan kompromi memintanya duduk dalam ketidakacuhan nyaman yang hidup dan kuatir hanya tentang dirinya sendiri. Ia tinggalkan semuanya. Ia tak mengucapkan apa-apa. Suatu pagi buta ia meruncingkan sisi tumpul harapannya dan mulai berusaha menyamai 1 Januari milik saudari-saudari Zapatistanya berulang-ulang dalam satu hari, setidaknya 364 kali dalam setahun, yang tak ada hubungannya dengan sebuah tanggal satu Januari saja. Ia tersenyum karena ia pernah mengagumi Zapatista dan kini tidak lagi. Ia mengakhiri kekagumannya saat ia tahu bahwa mereka hanyalah pantulan pemberontakannya sendiri, harapannya sendiri.Ia menemukan dirinya terlahir tanggal 1 Januari 1994. Sejak itulah ia merasa hidupnya, yang selalu dikatakan sebagai mimpi dan utopi, ternyata bisa diwujudkan.Ia mulai merajut dalam diam dan tanpa bayaran, berdampingan dengan lelaki dan perempuan lainnya, impian ruwet yang oleh beberapa orang disebut harapan: segala sesuatu untuk semua orang, tak ada yang untuk diri kami sendiri.Ia bertemu tanggal 8 Maret dengan wajah yang terhapus dan nama yang sembunyi. Dengannya datang pula ribuan perempuan. Banyak dan kian banyak. Lusinan, ratusan, ribuan, dan jutaan perempuan seluruh dunia yang ingat ada banyak soal yang harus digarap dan masih banyak lagi yang harus diperjuangkan. Tampaknya apa yang disebut ‘martabat’ itu bisa menular dan kaum perempuanlah yang rentan terjangkiti penyakit meresahkan ini…Tanggal 8 Maret adalah saat yang tepat untuk mengenang dan memberikan tempat yang semestinya bagi orang-orang Zapatista pemberontak itu, bagi kaum Zapatista, bagi para perempuan bersenjata maupun tak bersenjata. Bagi para pembangkang dan para perempuan Meksiko yang gelisah ditekuk-tekuk sebagai bawahan. Sejarah, tanpa mereka, tak lebih dari sekadar fabel yang dikarang secara buruk…
2. Hari EsokBila ada hari esok, maka ia akan disusun bersama kaum perempuan, dan terlebih lagi, oleh kaum perempuan…
Dari pegunungan Meksiko TenggaraSubcomandante Insurgente Marcos Meksiko, Maret 1996

Selang tahun keduabelas EZLN, puluhan kilometer, dan jarak maha jauh dari Peking, 12 orang perempuan berkumpul tanggal 8 Maret dengan wajah-wajah terhapus…
1. Kemarin…Seraut wajah terbalut hitam masih menyisakan mata dan beberapa helai rambut yang terjuntai dari kepala. Dalam tatapan itu terbersitlah seorang yang mencari. Karaben M-1 digenggam di depan, dalam kuda-kuda yang dinamakan “penyerangan”, dan sepucuk pistol tersarung di pinggang. Di sisi kiri dada perempuan itu, tempat harapan dan keyakinan bersemayam, tersematlah pangkat Mayor Infantri pasukan tentara pemberontak, yang pada subuh 1 Januari 1994 menamai diri mereka Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Di bawah komandonya, berdiri sepasukan pemberontak yang menduduki San Cristóbal de las Casas, bekas ibukota negara bagian Chiapas, Meksiko Tenggara. Alun-alun San Cristóbal senyap. Hanya lelaki dan perempuan pribumi yang dikomandoinyalah yang jadi saksi saat Mayor itu, seorang perempuan pemberontak suku Tzotzil, merebut bendera nasional dan memberikannya kepada komandan-komandan pergerakan, mereka yang disebut “Komite Klandestin Revolusioner Adat”. Di radio, sang Mayor berucap: “Bendera telah kami selamatkan. 10-23 ganti.” 1 Januari 1994, pukul 02.00 waktu tenggara, atau pukul 01.00 tahun baru di belahan dunia lainnya, dan ia telah menunggu 10 tahun lamanya untuk bisa mengucapkan kalimat tersebut. Ia tiba di pegunungan rimba raya Lacandon bulan Desember 1984. Belum genap 20 tahun usianya, namun sekujur tubuhnya telah membawa bekas-bekas riwayat penindasan penduduk adat. Bulan Desember 1984, perempuan coklat ini berkata “Cukup sudah!”, namun ia mengucapkannya begitu lirih sampai cuma ia seorang yang mendengar. Bulan Januari 1994, perempuan ini beserta sekian ribu penduduk adat bukan cuma mengucapkan, namun meneriakkan lantang-lantang “Cukup sudah!”, sampai seluruh dunia mendengar mereka…Di luar San Cristóbal, sekelompok pemberontak lainnya yang dikomandoi seorang pria –satu-satunya yang berkulit terang dan berhidung besar di antara penduduk pribumi yang menyerbu kota—baru saja rampung mengambil alih markas besar kepolisian. Dari penjara yang tersembunyi itu dibebaskanlah orang-orang pribumi yang menghabiskan malam tahun baru di bui akibat kejahatan terberat di wilayah tenggara Chiapas: jadi orang miskin. Eugenio Asparuk, suku Tzetzal, adalah nama Kapten pemberontak yang bersama-sama si hidung besar mengawasi penggeledahan dan penyitaan markas besar tersebut. Saat pesan sang Mayor tiba, Kapten pemberontak Pedro, suku Chol, telah selesai mengambil alih markas besar Polantas Federal dan mengamankan jalan raya yang menghubungkan San Cristóbal dengan Tuxtla Gutierrez. Kapten pemberontak Ubilio, suku Tzeltal, telah menguasai jalan masuk sisi utara kota berikut simbol uluran tangan pemerintah pada masyarakat adat, Institut Adat Nasional. Kapten pemberontak Guillermo, suku Chol, mengambil posisi di titik tertinggi kota. Dari situ ia memberi aba-aba dengan tatapannya. Rasa kaget yang tercekat mengintip dari balik jendela rumah-rumah dan gedung-gedung. Kapten pemberontak Gilberto dan Noe, masing-masing suku Tzotzil dan Tzeltal, tapi sama-sama pembangkang, mengakhiri pendudukan markas besar kepolisian hukum negara bagian lantas membakarnya sebelum berbaris mengamankan sisi kota yang mengarah menuju barak-barak Zona Militer ke-31 di Rancho Nuevo.Pukul 02.00 waktu tenggara, 1 Januari 1994, lima petinggi pemberontak, lelaki-lelaki pribumi, mendengar di radio suara pimpinan mereka, seorang perempuan pribumi pemberontak yang berucap, “Bendera telah kami selamatkan. 10-23 ganti.” Mereka mengulanginya pada pasukan mereka, semua lelaki perempuan pribumi pemberontak, lantas menerjemahkan ucapan berikut “Kita telah mulai…”Di istana kotapraja, sang Mayor mengorganisir posisi pertahanan guna melindungi orang-orang yang kini memerintah kota—kota yang sekarang ada dalam kekuasaan pemberontak pribumi. Seorang perempuan bersenjatalah yang melindungi mereka.Di antara para komandan pemberontak ada seorang perempuan imut, bahkan lebih imut ketimbang mereka yang di sekitarnya. Seraut wajah terbalut hitam masih menyisakan mata dan beberapa helai rambut yang terjuntai dari kepala. Dalam tatapan itu terbersitlah seorang yang mencari. Senapan laras pendek kaliber 12 tergantung di punggungnya. Mengenakan gaun tradisional perempuan San Andrés, Ramona turun gunung bersama seratus lebih perempuan lainnya, menuju San Cristóbal di malam terakhir tahun 1993 itu. Bersama Susana dan lelaki-lelaki adat lainnya ia adalah bagian dari komando perang Indian yang pada tahun 1994 melahirkan Komite Klandestin Revolusioner Adat - Komando Jenderal EZLN. Nantinya, Comandanta Ramona dengan imut tubuhnya dan kecerdasannya akan mengejutkan pers internasional saat ia muncul di sela Dialog Perdamaian pertama yang diselenggarakan di Katedral. Ia keluarkan dari tas ranselnya, bendera nasional yang direbut sang Mayor tanggal 1 Januari itu. Ramona tak tahu kapan, begitu pula kita, tapi dalam tubuhnya berdiam penyakit yang menggerogoti dirinya dalam gigitan-gigitan lebar, yang meredupkan suara dan tatapan matanya. Ramona dan sang Mayor, perempuan satu-satunya dalam delegasi Zapatista yang tampil di hadapan dunia, untuk pertama kalinya mencanangkan: “Demi segala niat dan tujuan kami telah mati, kami tak berarti apa-apa.” Dengan ini mereka belum memperhitungkan segala jenis pelecehan dan keterbelakangan. Sang Mayor menerjemahkan untuk Ramona pertanyaan para wartawan. Ramona mengangguk dan mengerti, seakan-akan jawaban yang diminta darinya telah ada di sana, dalam tubuh imut yang menertawakan bahasa Spanyol dan perilaku wanita kota. Ramona tertawa seakan tidak tahu dirinya sedang sekarat. Andaipun tahu, ia tetap tertawa. Sebelum ini ia tidak eksis bagi siapapun, sekarang ia eksis, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang perempuan adat, sebagai seorang perempuan pemberontak. Sekarang Ramona hidup, perempuan dari ras yang harus mati terlebih dulu untuk bisa hidup…Sang Mayor mengawasi cahaya memenuhi jalan-jalan San Cristóbal. Para prajuritnya mengorganisir pertahanan kota tua Jovel dan perlindungan bagi para penduduknya yang sedang lelap tertidur, orang-orang pribumi dan mestizo, yang sama-sama terkejut. Sang Mayor, perempuan pribumi pemberontak ini telah menduduki kota mereka. Ratusan penduduk pribumi bersenjata mengepung kota tua. Seorang perempuan bersenjatalah yang memimpin mereka…Sekian menit kemudian para pemberontak menduduki Las Margaritas, sekian jam setelahnya pasukan pemerintah yang mempertahankan Ocosingo, Altamirano, dan Chanal menyerah. Huixtan dan Oxchuc direbut oleh sekelompok prajurit yang menuju ke arah penjara utama San Cristóbal. Tujuh kota sekarang ada dalam genggaman kelompok pemberontak yang tunduk pada 7 kata sang Mayor:Perang demi kata-kata sekarang telah dimulai…Di tempat berbeda, para perempuan lainnya yang sama-sama pribumi dan sama-sama pembangkang, telah menyusun ulang potongan sejarah yang diberikan pada mereka. Potongan yang sampai tanggal 1 Januari 1994 itu selalu dibopong dalam kebisuan. Tak juga nama ataupun rupa mereka punya:IRMA. Kapten Infantri Pemberontak. Irma, perempuan suku Chol, membawahi sepasukan gerilya yang merebut alun-alun Ocosingo tanggal 1 Januari 1994 itu. Dari salah satu sisi taman kota, bersama tentara-tentara yang dikomandoinya, ia menyerang garnisun yang terletak dalam istana kotapraja sampai mereka menyerah. Lantas Irma menggerai kepang rambutnya. Rambut itu terjatuh ke pinggang seakan berkata “inilah aku, yang baru dan merdeka”. Rambut Kapten Irma bersinar, dan terus bersinar walau malam telah menyelimuti Ocosingo yang ada dalam genggaman kaum pemberontak…LAURA. Kapten Infantri Pemberontak. Suku Tzotzil. Gigih dalam perang dan gigih dalam belajar-mengajar. Laura menjadi kapten dalam unit yang beranggotakan lelaki semua. Bukan cuma itu, merekapun semuanya anggota baru. Dengan sabar, sesabar gunung yang melihatnya tumbuh dewasa, Laura mengajar dan memberi perintah. Kalau lelaki-lelaki yang dibawahinya itu ragu, ia memberi contoh dengan mengerjakannya sendiri. Tak ada yang menggotong beban dan berjalan kaki sebanyak dia. Setelah penyerbuan Ocosingo, ia memerintahkan unitnya mundur. Begitu teratur dan beres. Wanita berkulit terang ini jarang bicara, tapi ia menggenggam di tangannya sepucuk karaben yang direbutnya dari seorang polisi yang memandang seorang wanita dusun tak lebih dari sosok untuk dihina atau diperkosa. Setelah menyerah, polisi itu kabur dalam celana kolornya, persis mereka lainnya yang sampai hari itu percaya bahwa wanita cuma berguna di dapur atau untuk dihamili…ELISA. Kapten Infantri Pemberontak. Ibarat piala perang, ia membawa dalam tubuhnya pecahan-pecahan mortir yang tertanam selamanya di situ. Ia sedang mengatur pasukannya tatkala barisan pemberontak terputus dan sebuah bola api menggulung pasar Ocosingo dengan darah. Kapten Benito terluka dan kehilangan matanya. Sebelum pingsan, ia sempat memberi penjelasan dan aba-aba: “Aku kena, Kapten Elisa ambil alih”. Kapten Elisa sendiri telah terluka saat ia berhasil membawa segerombolan prajurit keluar dari pasar itu. Kalau Kapten Elisa, perempuan suku Tzeltal itu memberi perintah, suaranya cuma menggumam lirih… tapi tiap orang patuh…SILVIA. Kapten Infantri Pemberontak. Ia terperangkap 10 hari di Ocosingo yang telah jadi sarang tikus sejak tanggal 2 Januari itu. Menyamar sebagai warga negara biasa, ia berlari tergesa-gesa sepanjang kota yang penuh berisi tentara federal, tank, dan meriam. Di satu pos penjagaan militer ia diberhentikan. Tapi segera saja mereka membolehkannya lewat. “Tak mungkin wanita semuda dan selembut itu anggota pemberontak”, kata tentara-tentara itu saat melihatnya pergi. Sesudah bergabung kembali bersama unitnya di pegunungan, perempuan suku Chol ini tampak murung. Dengan hati-hati, aku tanya kenapa gelak tawanya berkurang. “Di Ocosingo situ,” jawabnya dengan kepala tertunduk, “di Ocosingo kutinggalkan ranselku berisi semua kaset lagu yang telah kukoleksi, kini kita tak punya apa-apa.” Senyap, kepedihannya tergolek di tangannya. Aku tak berkata apa-apa, kusampaikan belasungkawaku dan kulihat dalam perang tiap-tap orang kehilangan apa yang paling ia cintai…MARIBEL. Kapten Infantri Pemberontak. Ia mengambil alih stasiun radio Las Margaritas saat unitnya menyerbu kotapraja itu tanggal 1 Januari 1994. Sembilan tahun penuh ia hidup di pegunungan untuk bisa duduk di depan mikrofon dan mengucapkan: “Kami ini hasil dari 500 tahun perjuangan; pertama kami berjuang melawan perbudakan…” Transmisinya tak berjalan baik karena alasan-alasan teknis, dan Maribel pindah posisi untuk melindungi sisi belakang unitnya yang bergerak menuju Comitan. Berhari-hari sesudahnya ia bertugas sebagai penjaga tawanan perang, Jenderal Absalon Castellanos Dominguez. Maribel suku Tzeltal dan umurnya belum genap 15 tahun saat ia tiba di pegunungan Meksiko Tenggara. “Masa terberat dalam 9 tahun itu adalah saat aku harus mendaki bukit pertama yang dijuluki ‘bukit akhirat’, sesudah itu semuanya gampang,” kata perwira pemberontak ini. Tatkala Jenderal Castellanos Dominguez dikembalikan ke pemerintah, Kapten Maribel adalah pemberontak pertama yang melakukan kontak dengan pemerintah. Komisaris Manuel Camacho Solis mengulurkan tangan padanya dan bertanya berapa umurnya. “502,” jawab Maribel, yang menghitung tahun keseluruhan sejak pemberontakan dimulai…ISIDORA. Infantri Pemberontak. Isidora pergi ke Ocosingo sebagai tamtama di hari pertama bulan Januari itu. Dan sebagai tamtama Isidora meninggalkan Ocosingo yang bermandi api, setelah berjam-jam lamanya berjuang menyelamatkan unitnya, sekitar 40 orang lelaki yang terluka. Dia juga menyimpan pecahan-pecahan mortir di lengan dan kakinya. Saat Isidora tiba di unit perawatan untuk menyerahkan mereka yang terluka, ia meminta sedikit air dan bangkit berdiri lagi. “Mau ke mana kau?” tanya mereka sambil mencoba mengobati luka-luka yang merobek-melukisi wajahnya serta memerahkan seragamnya. “Menjemput yang lain,” jawab Isidora sambil mengokang lagi. Mereka mencoba menghentikannya tapi tak mampu. Tamtama Isidora bersikukuh ia harus kembali ke Ocosingo menyelamatkan compañeros lainnya dari nada-nada kematian yang dialunkan oleh mortir dan granat. Mereka sampai harus memenjarakannya untuk menghentikannya. “Paling tidak saat aku dihukum aku tidak turun pangkat,” kata Isidora sembari menunggu dalam kamar yang baginya tampak seperti kurungan. Berbulan-bulan kemudian, saat mereka menganugerahinya bintang jasa yang menaikkannya jadi perwira infantri, Isidora, seorang Tzeltal dan Zapatista, menatap bintang itu terlebih dahulu lalu menatap komandannya, dan bertanya seakan-akan ia sedang dihina “Kenapa?”… Tapi ia tidak menunggu jawabannya…AMALIA. Letnan satu di unit rumah sakit. Amalia punya gelak tawa tercepat di seluruh wilayah Tenggara Meksiko. Saat ia menjumpai Kapten Benito tergeletak tak sadar bergenang darah, ia menyeretnya ke tempat yang lebih aman. Ia menggendongnya di punggung dan membawanya keluar dari lingkaran kematian yang mengitari pasar. Tatkala seseorang mengusulkan untuk menyerah, Amalia, taklid akan darah Chol yang mengalir di nadinya, naik pitam dan mulai membantah. Tiap orang menyimak, sekalipun di atas mereka ledakan-ledakan begitu bengis dan peluru-peluru berdesingan. Tak seorang pun menyerah…ELENA. Letnan di unit rumah sakit. Saat bergabung dengan EZLN ia buta huruf. Di sana ia belajar membaca, menulis, serta apa yang disebut obat-obatan. Dari mengobati diare dan menyuntikkan vaksin, ia kini menangani mereka yang terluka di rumah sakit kecil yang sekaligus jadi rumah, gudang, dan farmasi. Dengan jerih payah ia mengeluarkan cuilan-cuilan mortir yang dibawa orang-orang Zapatista di tubuh mereka. “Ada yang bisa aku buang, ada yang tidak,” kata Elena, suku Chol pemberontak, seolah-olah ia sedang membicarakan kenangan dan bukan potongan-potongan logam…Di San Cristóbal, pagi hari 1 Januari 1994 itu, ia bercakap dengan si hidung putih besar: “Seseorang baru saja ke mari bertanya-tanya tapi aku tak paham bahasanya, barangkali Inggris. Entah fotografer atau bukan tapi ia bawa kamera.”“Aku segera ke sana,” kata si hidung besar sambil merapikan topeng skinya.Ke dalam kendaraan dibawa pulalah senjata-senjata yang direbut dari markas polisi dan ia meluncur menuju pusat kota. Mereka mengeluarkan senjata-senjata itu dan membagikannya kepada penduduk-penduduk adat yang berjaga di seputar istana kotapraja. Orang asing itu turis yang bertanya apakah ia bisa meninggalkan kota. “Tidak,” jawab si topeng ski yang kelebihan hidung itu, “lebih baik kau kembali ke hotelmu. Kami tak tahu apa yang bakal terjadi.” Turis itu pergi setelah meminta izin merekam dengan kamera videonya. Seraya pagi datang, datang pulalah orang-orang yang ingin tahu, wartawan-wartawan dan pertanyaan-pertanyaan. Si hidung besar menjawab dan menjelaskannya pada penduduk setempat, turis, dan wartawan. Mayor ada di belakangnya. Si topeng ski menjawab dan bercanda. Perempuan bersenjata itu mengawasi di baliknya.Seorang wartawan, dari balik kamera televisi bertanya: “Dan siapa Anda?” “Siapa aku,” jawab si topeng ski ragu-ragu seakan sedang melawan kantuk setelah malam berkepanjangan. “Ya,” desak si jurnalis, “siapakah Anda ini, ‘Komandan Macan’ atau “Komandan Singa’?” “Bukan,” jawab si topeng ski sambil mengucek matanya yang kini penuh berisi kejemuan. “Jadi, siapa nama Anda?” tanya si wartawan sambil menyorongkan kamera dan mikrofonnya. Si topeng ski berhidung besar itu menjawab “Marcos. Subcomandante Marcos”… Di atas kepala kapal-kapal Pontius Pilatus mulai berdengung…Sejak itulah, kisah tertibnya aksi militer dalam pendudukan San Cristóbal mulai meremang. Terhapuslah fakta bahwa seorang perempuan, seorang perempuan dusun pemberontaklah yang mengkomandoi seluruh operasi. Peran serta semua perempuan dalam aksi-aksi lain tanggal 1 Januari itu, serta sepanjang 10 tahun jalan berliku lahirnya EZLN, jadi dinomorduakan. Wajah-wajah di balik topeng-topeng ski jadi makin anonim saat semua cahaya mengarah ke Marcos. Sang Mayor diam saja, ia terus menjagai sisi belakang si hidung besar yang namanya sekarang tersohor ke seluruh dunia. Tak seorang pun bertanya siapa namanya…Subuh 2 Januari 1994, masih perempuan yang sama itu jugalah yang memimpin penarikan mundur dari San Cristóbal untuk berbalik ke pegunungan. Ia kembali ke San Cristóbal 50 hari setelahnya sebagai bagian dari rombongan pengawal yang menjaga keamanan delegasi CCRI-CG dari EZLN dalam Dialog di Katedral. Beberapa jurnalis perempuan mewawancarainya dan menanyakan namanya. “Ana Maria, Mayor Pemberontak Ana Maria,” jawabnya dengan tatapan matanya yang gelap. Ia tinggalkan Katedral dan menghilang sepanjang sisa tahun 1994 itu. Seperti compañera-compañera lainnya, ia mesti menunggu, ia mesti diam…Tiba bulan Desember 1994, 10 tahun sejak ia menjadi tentara, Ana Maria menerima tugas menyiapkan penerobosan blokade militer yang dipasang pemerintah di sekeliling rimba raya Lacandon. Subuh 19 Desember, EZLN mengambil posisi di 38 kotapraja. Ana Maria mengkomandoi aksi di kotapraja-kotapraja Altos di Chiapas. Duabelas perwira perempuan bersamanya dalam aksi itu: Monica, Isabela, Yuri, Patricia, Juana, Ofelia, Celina, Maria, Gabriela, Alicia, Zenaida, dan Maria Luisa. Ana Maria sendiri menangani kotapraja Bochil.Setelah penyebaran pasukan Zapatista, perwira-perwira tinggi tentara federal memerintahkan diam seribu bahasa atas bobolnya blokade, dan media massa menuliskannya sebagai aksi “propagandis” EZLN belaka. Harga diri kaum federal sangat terluka: Zapatista sanggup lolos dari blokade dan yang lebih menghina lagi, seorang perempuanlah yang mengkomandoi unit yang menduduki pelbagai wilayah kotapraja. Jelas hal ini tidak bisa diterima dan sejumlah besar uang harus dikucurkan agar kejadian ini tertutupi selamanya.Karena aksi-aksi tak sengaja para compañerosbersenjatanya, serta aksi-aksi sengaja pemerintah, peran Ana Maria dan kaum perempuan Zaptista memudar dan jadi tak terlihat…
2. Hari IniAku hampir rampung menuliskan ini saat seseorang lainnya tiba…Doña Juanita. Setelah wafatnya Pak Tua Antonio, doña Juanita membiarkan ritme hidupnya melambat selambat saat ia menjerang kopi. Meski kuat secara fisik, doña Juanita mengabarkan bahwa ia akan mati. “Jangan konyol, nek,” kataku, segan menatap matanya. “Kau ini…,” jawabnya, “kalau untuk hidup kita mesti mati, maka tak satupun bisa menghalangiku mati, apalagi bocah kurang ajar sepertimu,” berkata dan mengumpatlah doña Juanita, istri Pak Tua Antonio, seorang perempuan pemberontak seumur hidupnya, dan seperti terlihat, seorang pemberontak bahkan dalam menjawab panggilan mautnya…Dari simpang lain blokade terlihatlah…Ia. Ia tak punya pangkat militer, seragam, ataupun senjata. Ia seorang Zapatista meski hanya ia seorang yang tahu. Ia tak punya wajah ataupun nama, seperti layaknya Zapatista. Ia berjuang demi demokrasi, kebebasan, dan keadilan, sama seperti Zapatista. Ia bagian dari apa yang dinamakan EZLN “masyarakat sipil”. Ia orang tanpa partai, orang yang tak jadi milik “masyarakat politik” yang tersusun atas aturan-aturan dan pimpinan-pimpinan partai politik. Ia sebagian dari kerumitan itu, tapi bagian sesungguhnya dari suatu masyarakat yang, hari demi hari, mengucapkan sendiri “Sudah, cukup!”Pertama ia kaget mendengar ucapannya sendiri, tapi kemudian, berazaskan kekuatan yang timbul dari mengulang-ulangnya, dan terlebih-lebih, menghidupinya, ia tak lagi gentar akan mereka, tak lagi gentar akan dirinya sendiri. Ia kini seorang Zapatista. Ia telah menggabungkan nasibnya dengan nasib orang-orang Zapatista dalam igauan baru yang begitu menakutkan partai-partai politik dan kaum intelektual Kekuasaan: Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Ia telah berjuang melawan tiap orang, melawan suaminya, kekasihnya, pacarnya, anak-anaknya, temannya, saudara lelakinya, ayahnya, kakeknya. “Kau sinting,” begitulah penilaian yang lazim. Ia tinggalkan banyak hal di belakangnya. Apa yang ia tinggalkan jauh lebih besar ketimbang apa yang ditinggalkan para pemberontak lain yang memang sudah tak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Segala sesuatunya, dunianya, menghendaki ia melupakan “orang-orang Zapatista gila itu”, dan kompromi memintanya duduk dalam ketidakacuhan nyaman yang hidup dan kuatir hanya tentang dirinya sendiri. Ia tinggalkan semuanya. Ia tak mengucapkan apa-apa. Suatu pagi buta ia meruncingkan sisi tumpul harapannya dan mulai berusaha menyamai 1 Januari milik saudari-saudari Zapatistanya berulang-ulang dalam satu hari, setidaknya 364 kali dalam setahun, yang tak ada hubungannya dengan sebuah tanggal satu Januari saja. Ia tersenyum karena ia pernah mengagumi Zapatista dan kini tidak lagi. Ia mengakhiri kekagumannya saat ia tahu bahwa mereka hanyalah pantulan pemberontakannya sendiri, harapannya sendiri.Ia menemukan dirinya terlahir tanggal 1 Januari 1994. Sejak itulah ia merasa hidupnya, yang selalu dikatakan sebagai mimpi dan utopi, ternyata bisa diwujudkan.Ia mulai merajut dalam diam dan tanpa bayaran, berdampingan dengan lelaki dan perempuan lainnya, impian ruwet yang oleh beberapa orang disebut harapan: segala sesuatu untuk semua orang, tak ada yang untuk diri kami sendiri.Ia bertemu tanggal 8 Maret dengan wajah yang terhapus dan nama yang sembunyi. Dengannya datang pula ribuan perempuan. Banyak dan kian banyak. Lusinan, ratusan, ribuan, dan jutaan perempuan seluruh dunia yang ingat ada banyak soal yang harus digarap dan masih banyak lagi yang harus diperjuangkan. Tampaknya apa yang disebut ‘martabat’ itu bisa menular dan kaum perempuanlah yang rentan terjangkiti penyakit meresahkan ini…Tanggal 8 Maret adalah saat yang tepat untuk mengenang dan memberikan tempat yang semestinya bagi orang-orang Zapatista pemberontak itu, bagi kaum Zapatista, bagi para perempuan bersenjata maupun tak bersenjata. Bagi para pembangkang dan para perempuan Meksiko yang gelisah ditekuk-tekuk sebagai bawahan. Sejarah, tanpa mereka, tak lebih dari sekadar fabel yang dikarang secara buruk…
2. Hari EsokBila ada hari esok, maka ia akan disusun bersama kaum perempuan, dan terlebih lagi, oleh kaum perempuan…
Dari pegunungan Meksiko TenggaraSubcomandante Insurgente Marcos Meksiko, Maret 1996
Published on March 07, 2017 19:31
November 6, 2016
Karya-karya Fiksi tentang Pablo Neruda
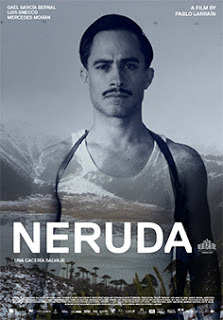 Dengan mulai diputarnya di festival-festival internasional film Neruda (2016), karya anyar sutradara Cile Pablo Larrain yang berkisah tentang Inspektur Polisi Óscar Peluchonnea (diperankan oleh Gael García Bernal) yang ditugaskan memburu penyair komunis Pablo Neruda, saya mencoba mengingat-ingat lagi karya-karya fiksi apa sajakah yang pernah dibuat tentang penyair besar satu ini.
Dengan mulai diputarnya di festival-festival internasional film Neruda (2016), karya anyar sutradara Cile Pablo Larrain yang berkisah tentang Inspektur Polisi Óscar Peluchonnea (diperankan oleh Gael García Bernal) yang ditugaskan memburu penyair komunis Pablo Neruda, saya mencoba mengingat-ingat lagi karya-karya fiksi apa sajakah yang pernah dibuat tentang penyair besar satu ini.Yang paling populer di Indonesia tentu saja adalah novel Ardiente paciencia karya Antonio Skármeta, yang bercerita tentang tukang pos pengantar surat Neruda yang berusaha belajar berpuisi dari sang maestro. Novel ini diadaptasi menjadi film berbahasa Italia yang sangat terkenal oleh sutradara Inggris Michael Radford berjudul Il Postino (1994). Terjemahan Indonesia novel Skármeta itu diterbitkan oleh penerbit Akubaca lebih dari satu dekade lalu dengan memakai judul versi filmnya.
Melihat ulasan-ulasan positif para kritikus beberapa hari belakangan yang menyanjung Neruda sebagai film yang melabrak batas-batas genre biopic, sepertinya Neruda-nya Larrain bakal melebihi kepopuleran Il Postino. Sebagai catatan, perlu disebut di sini bahwa pada 2014 lalu telah ada film berjudul Neruda karya sutradara Cile Manuel Basoalto yang juga merupakan biopic sang penyair, tetapi film ini jeblok secara kualitas maupun komersial. Selain itu, pada 2017 mendatang dokumenter Pablo Neruda: The People’s Poet semoga juga sudah dirilis sesuai jadwalnya. Dokumenter ini disutradarai dan diproduksi oleh Mark Eisner, salah satu penerjemah, penulis biografi, dan pakar Neruda paling terkemuka di dunia.
Neruda juga menjadi tokoh sentral novel detektif karya Roberto Ampuero berjudul El caso Neruda (2008), yang terjemahan Inggrisnya terbit sebagai The Neruda Case (2012). Berlatar era 1970an yang penuh gejolak politik di Cile, novel ini adalah novel keenam Ampuero dalam serial detektif Cayetano Brulé, meski mengisahkan kasus paling pertama yang ditanganinya: Neruda menugaskan si detektif mencari dokter Kuba yang pernah ditemui penyair itu pada tahun 1940an. Untuk menggambarkan sosok Neruda, Ampuero –yang selain novelis juga menjabat duta besar Cile untuk Meksiko—menggali ingatan masa kecilnya sendiri yang pada 1960an memang tinggal bertetangga dengan Neruda. Ia ingat misalnya saat sedang berjalan-jalan di hari Minggu bersama ayahnya, mereka lihat Neruda di bangku belakang mobil yang disopiri oleh seorang perempuan, sementara di bangku depan ada seorang lelaki lain mengenakan kacamata berbingkai hitam tebal. “Jangan pernah lupakan bapak-bapak itu, nak,” pesan ayahnya. “Yang satu, suatu hari nanti akan menerima Hadiah Nobel, dan yang satunya akan menjadi Presiden Cile.” Lelaki di bangku depan itu memang adalah Salvador Allende.

Lalu ada buku anak-anak/remaja karangan penulis Hispanik AS Pam Muñoz Ryan berjudul The Dreamer (2010). Buku yang sangat imajinatif ini berkisah tentang Neruda kecil (Neftali Reyes) yang terpukau pada kata-kata dan bunyi-bunyian dari dunia sekitarnya: tetes hujan, kapak ayahnya menghantami batang pohon, sepatu botnya menginjak lumpur dll. Masih untuk buku anak-anak, Neruda juga dikenalkan sejak dini bagi para pembaca bahasa Spanyol dan Inggris lewat dua buku ini: Conoce a Pablo Neruda (2012) karya Georgina Lázaro León dengan ilustrasi Valeria Cis, dan Pablo Neruda: Poet of the People (2011) karya Monica Brown dengan ilustrasi Julie Paschkis.
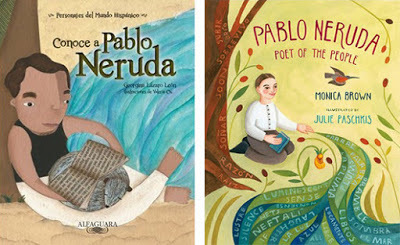
Apa sih sesungguhnya yang bikin Neruda sepopuler itu sebagai penyair? Di antara analisa-analisa serius tentang kualitas puisinya, novelis eksil Cile Ariel Dorfman punya jawaban paling asyik: “Satu alasan mengapa Neruda selalu populer di kalangan anak muda adalah karena ia doyan sekali seks. Di tiap generasi, para lelaki, termasuk aku, pernah mengutip Neruda buat menggaet cewek.” Ya, seperti si tukang pos di novel Skármeta, atau perhatikan bagaimana puisi “Soneta XVII” Neruda dibacakan di film Patch Adams (1998) oleh Robin Williams untuk kepentingan yang sama: merayu perempuan.
Nah untuk soal satu ini, ada sisi gelap kehidupan Neruda yang mungkin jarang diketahui orang. Ketika ditugaskan sebagai diplomat di Batavia, Neruda menikahi seorang perempuan Belanda kelahiran Jawa, María Antonieta Hagenaar, dan punya seorang putri bernama Malva Marina. Malva menderita hidrosefalus (pembesaran kepala), dan Neruda menelantarkan anak dan istrinya begitu saja, sampai Malva meninggal di Belanda pada usia 9 tahun. Neruda tak pernah menyebut-nyebut sama sekali anak istrinya ini dalam semua karyanya termasuk memoarnya.
Dua penulis Belanda telah mengarang novel tentang kasus ini. Pauline Slot menulis En het vergeten zo lang / Dan Lupa Itu Lama (2010), yang pernah diterjemahkan sedikit oleh Joss Wibisono di tautan ini, sementara Hagar Peeters menulis novel Malva (2015) yang banyak dipuji kritikus sebagai karya yang cemerlang. Secara khusus, sutradara teater perempuan Cile Flavia Radrigán juga pernah mementaskan karyanya yang mengecam keras kelakuan Neruda ini berjudul Un ser perfectamente ridículo / Seseorang yang Sempurna Konyolnya (2004). Bila ingin mengetahui lebih lanjut tentang anak Neruda yang tak diakuinya ini, ada satu buku non-fiksi yang bisa dibaca berjudul El enigma de Malva Marina: la hija de Pablo Neruda (2013) karya Bernardo Reyes, keponakan Neruda sendiri.

Published on November 06, 2016 05:16
August 10, 2016
Sampah dan Orang Sisa-sisa
Pengantar kuratorial sesi Amerika Latin oleh Ronny Agustinus, dalam ARKIPEL Jakarta International Documentary Film Festival 2016. Wacana antroposen menjadi semakin populer dalam ilmu-ilmu sosial dan ekologi belakangan ini. Meski titik waktu resminya sebagai sebuah kala geologi masih perlu dipastikan, tak terbantahkan bahwa kita memang hidup di era antroposen, ketika ulah manusia—dan bukan alam—yang paling berperan dalam mengubah iklim serta paras bumi. Dan sepanjang sekitar 200 tahun terakhir, wujud antroposen tak syak lagi adalah masyarakat kapitalis industri. Dengan segenap pola produksi dan konsumsinya, kapitalisme industri di mana-mana akan berujung pada residu pamungkasnya: sampah—residu akhir yang justru membuat wacana antroposen menjadi mendesak untuk dibicarakan pada awalnya. Dan itulah yang akan menjadi tema kurasi program Amerika Latin dalam ARKIPEL social/kapital 2016 ini: sampah sebagai akhir dan juga awal pergulatan social/kapital, sampah dalam arti fisikal maupun sosial, dan bagaimana keduanya bertalian erat.Sampah adalah persoalan besar kota-kota Amerika Latin, dan bukan kebetulan bila sebagian filem pertama yang mengawali gebrakan Sinema Baru Amerika Latin pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an mengangkat persoalan sampah. Sebagai bagian dari usaha untuk menunjukkan realitas Amerika Latin apa adanya (dalam kerangka besar gerakan-gerakan pembebasan), lahirlah dokumenter-dokumenter macam Cantegriles (1958) dan Tire dié (1958/1960). Filem 8 menit Cantegriles karya Alberto Miller (Uruguay) tedeng aling-aling menyandingkan gambaran wilayah perumahan mewah Cantegril Country Club di Punta del Este, Uruguay, dengan wilayah kumuh di seputar tempat pembuangan sampah (yang oleh kalangan kaya dengan olok-olok disebut “cantegriles”-nya kaum miskin). Sementara Tire dié direkam di Santa Fe, Argentina, oleh sutradara Fernando Birri beserta para mahasiswanya dari Sekolah Dokumenter Santa Fe selama tiga tahun—proyek yang mereka namai “filem survei” dengan versi akhir sepanjang 33 menit.Di ujung yang lain, saya memilih dokumenter pendek 12 menit Ilha das Flores (1989) karya Jorge Furtado dari Brasil. Dengan montase kreatif atas materi-materi foto dan footage, buat saya inilah filem paling jitu dan menohok dalam membahas sampah sebagai residu sisa-sisa sistem produksi dan konsumsi kapitalisme global, serta “orang sisa-sisa” yang harus ada sebagai bagian inheren dari sistem. Furtado tak menyajikan impian-impian indah bahwa ada jalan keluar yang manis dari ini. Menyandingkan keduanya saya harap memberikan perenungan dan kontras tersendiri untuk program Amerika Latin tahun ini. Maka bila paragraf terakhir pengantar tematik ARKIPEL 2016 menyebut tentang bagaimana social/kapitaltelah melebur status warga “dalam sebuah dunia baru (global) tanpa—atau hanya dengan samar-samar—ingatan-ingatan akan negara,” maka dua filem di atas hendak menyajikan gambaran tersebut dalam dua kutub ekstremnya: komunitas yang “makan” dari sampah dan komunitas yang secara harafiah memakan sampah, yang keduanya terjalin rapat dengan cara kapitalisme global bekerja yang membuat di layar maupun di luar layar negara tampak tidak hadir, samar-samar sekalipun.
Kawasan pembuangan sampah Tire diré mendapat namanya dari seruan “Tire diez!” (“Beri aku sepuluh sen”) yang diteriakkan anak-anak manakala ada kereta lewat, seperti kawan-kawan sekampung saya dulu di Jawa Timur berteriak-teriak “Minta uang” bila ada pesawat terbang lewat. Perlu dicatat di sini dokumenter Cartoneros (2006) karya Ernesto Livon-Grosman yang membahas sampah kertas dan daur-ulangnya tanpa menampilkan gambaran klise para pemulung kumuh yang tinggal di sekitar gunungan sampah. Konteks filem ini adalah Buenos Aires awal 2000-an, ketika krisis ekonomi dan dampak korupsi sistemik membangkrutkan negara dan membuat kelas menengah terpaksa bertahan hidup dengan menjadi pemulung kertas, karton, dan dus (“cartoneros”). Carlos Fuentes dalam novelnya La Silla del Águila (2003) menyebut Mexico City sebagai “el basurero más grande del mundo” (“tempat pembuangan sampah terbesar di dunia”). Secara faktual ia keliru.
Kawasan pembuangan sampah Tire diré mendapat namanya dari seruan “Tire diez!” (“Beri aku sepuluh sen”) yang diteriakkan anak-anak manakala ada kereta lewat, seperti kawan-kawan sekampung saya dulu di Jawa Timur berteriak-teriak “Minta uang” bila ada pesawat terbang lewat. Perlu dicatat di sini dokumenter Cartoneros (2006) karya Ernesto Livon-Grosman yang membahas sampah kertas dan daur-ulangnya tanpa menampilkan gambaran klise para pemulung kumuh yang tinggal di sekitar gunungan sampah. Konteks filem ini adalah Buenos Aires awal 2000-an, ketika krisis ekonomi dan dampak korupsi sistemik membangkrutkan negara dan membuat kelas menengah terpaksa bertahan hidup dengan menjadi pemulung kertas, karton, dan dus (“cartoneros”). Carlos Fuentes dalam novelnya La Silla del Águila (2003) menyebut Mexico City sebagai “el basurero más grande del mundo” (“tempat pembuangan sampah terbesar di dunia”). Secara faktual ia keliru.
Published on August 10, 2016 20:29
August 3, 2016
Daftar Film yang Diangkat dari Literatur Amerika Latin
Dikompilasi oleh Ronny Agustinus. Daftar ini tentunya masih jauh dari lengkap dan akan terus diperbarui. Informasi dan masukan sangat dinantikan.
 Beberapa karya Mario Vargas Llosa yang
Beberapa karya Mario Vargas Llosa yang
sudah diangkat ke layar lebar
1950El crimen de Oribe (judul Inggris: The Crime of Oribe)Sutradara: Leopoldo Torre Nilsson (Argentina)Diangkat dari: Novel El perjurio de la nieve (1944) karya Adolfo Bioy Cesares
1954Días de odio (judul Inggris: Days of Hate)Sutradara: Leopoldo Torre Nilsson (Argentina)Diangkat dari: Cerpen “Emma Zunz” karya Jorge Luis Borges dalam kumpulan El Aleph (1949)
1957La casa del ángel (judul Inggris: The House of the Angel)Sutradara: Leopoldo Torre Nilsson (Argentina)Diangkat dari: Novel La casa del ángel (1957) karya Beatriz Guido
1964El gallo de oro(judul Inggris: The Golden Cockerel)Sutradara: Roberto Gavaldón (Meksiko)Diangkat dari: Novelet El gallo de oro (1959) karya Juan Rulfo; diadaptasi menjadi skenario oleh Carlos Fuentes dan Gabriel García Márquez
1965En este pueblo no hay ladrones (judul Inggris: There Are No Thieves in This Village)Sutradara: Alberto Isaac (Meksiko)Diangkat dari: Cerpen “En este pueblo no hay ladrones” karya Gabriel García Márquez dalam kumpulan Los funerales de la Mamá Grande (1962)
1966Blow-UpSutradara: Michelangelo Antonioni (Italia)Diangkat dari: Cerpen “Las babas del diablo” karya Julio Cortázar dalam kumpulan Las armas secretas (1959)
Emma ZunzSutradara: Jesús Martínez León (Spanyol)Diangkat dari: Cerpen “Emma Zunz” karya Jorge Luis Borges dalam kumpulan El Aleph (1949)
1968Memorias del subdesarrollo (judul Inggris: Memories of Underdevelopment)Sutradara: Tomás Gutiérrez Alea (Kuba)Diangkat dari: Novel Memorias del Subdesarrollo (1966) karya Edmundo Desnoes
Secret CeremonySutradara: Joseph Losey (AS)Diangkat dari: Novel Ceremonia secreta (1960) karya Marco Denevi
1974La tregua (judul Inggris: The Truce)Sutradara: Sergio Renán (Argentina) Diangkat dari: Novel La tregua (1960) karya Mario Benedetti
1976Dona Flor e Seus Dois Maridos (judul Inggris: Dona Flor and Her Two Husbands)Sutradara: Bruno Barreto (Brasil)Diangkat dari: Novel Dona Flor e Seus Dois Maridos (1966) karya Jorge Amado
Acaso irreparableSutradara: Dorotea Guerra (Meksiko)Diangkat dari: Cerpen “Acaso irreparable” karya Mario Benedetti dalam kumpulan La muerte y otras sorpresas (1968)
1978El lugar sin límites (judul Inggris: Hell Without Limits)Sutradara: Arturo Ripstein (Meksiko)Diangkat dari: Novelet El lugar sin límites (1966) karya José Donoso
Los de abajo (judul Inggris: The Underdogs)Sutradara: Servando González (Meksiko)Diangkat dari: Novel Los de abajo (1916) karya Mariano Azuela
1979Emma ZunzSutradara: Isabel Beveridge (Kanada)Diangkat dari: Cerpen “Emma Zunz” (1949) karya Jorge Luis Borges dalam kumpulan El Aleph
1982Kiss Me GoodbyeSutradara: Robert Mulligan (AS)Diangkat dari: Novel Dona Flor e Seus Dois Maridos (1966) karya Jorge Amado
1983EréndiraSutradara: Ruy Guerra (Brasil)Diangkat dari: Novelet La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada (1972) karya Gabriel García Márquez, meskipun novelet itu pun sesungguhnya awalnya berasal dari skenario film yang ditulis Gabo pada 1960an tetapi hilang
Gabriela, cravo e canela (judul Inggris: Gabriela)Sutradara: Bruno Barreto (Brasil)Diangkat dari: Novel Gabriela, cravo e canela (1958) karya Jorge Amado
No habrá más penas ni olvido (judul Inggris: Funny Dirty Little War)Sutradara: Héctor Olivera (Argentina)Diangkat dari: Novel No habrá más penas ni olvido (1980) karya Osvaldo Soriano
1984Emma ZunzSutradara: Peter Delpeut (Belanda)Diangkat dari: Cerpen “Emma Zunz” (1949) karya Jorge Luis Borges dalam kumpulan El Aleph
1985O Beijo da Mulher Aranha (judul Inggris: Kiss of the SpiderWoman)Sutradara: Héctor Babenco (Brasil) Diangkat dari: Novel El beso de la mujer araña (1976) karya Manuel Puig
La ciudad y los perros (judul Inggris: The City and the Dogs)Sutradara: Francisco J. Lombardi (Peru)Diangkat dari: Novel La ciudad y los perros (1963) karya Mario Vargas Llosa
Emma ZunzSutradara: Giangiacomo Tabet (Meksiko)Diangkat dari: Cerpen “Emma Zunz” karya Jorge Luis Borges dalam kumpulan El Aleph (1949)
1986Los amores de LauritaSutradara: Antonio Ottone (Argentina)Diangkat dari: Novel Los amores de Laurita (1984) karya Ana María Shua
Malayunta (judul Inggris: Bad Company)Sutradara: José Santiso (Argentina)Diangkat dari: Drama Paternoster (1972) karya Jacobo Langsner
1987Cronaca di una morte annunciata (judul Inggris: Chronicle of a Death Foretold)Sutradara: Francesco Rosi (Italia)Diangkat dari: Novel Crónica de una muerte anunciada (1981) karya Gabriel García Márquez
Der gläserne HimmelSutradara: Nina Grosse (Jerman)Diangkat dari: Cerpen “El otro cielo” karya Julio Cortázar dalam kumpulan Todos los fuegos el fuego (1966)
El túnel (judul Inggris: The Tunnel)Sutradara: Antonio Drove (Spanyol)Diangkat dari: Novel El túnel (1948) karya Ernesto Sábato
1988Un señor muy viejo con unas alas enormes (judul Inggris: A Very Old Man with Enormous Wings)Sutradara: Fernando Birri (Argentina)Diangkat dari: Cerpen “Un señor muy viejo con unas alas enormes” karya Gabriel García Márquez dalam kumpulan La Hojarasca (1955)
Der Radfahrer von San ChristobalSutradara: Peter Lilienthal (Jerman) Diangkat dari: Cerpen “El ciclista del San Cristóbal” (1973) karya Antonio Skármeta dari kumpulan cerpen berjudul sama
Cinco años de mi vidaSutradara: Antonio Pinar (Spanyol)Diangkat dari: Cerpen “Cinco años de mi vida” karya Mario Benedetti dalam kumpulan La muerte y otras sorpresas (1968)
1989Old GringoSutradara: Luis Puenzo (Argentina)Diangkat dari: Novel Gringo viejo (1985) karya Carlos Fuentes
Cartas del parque (judul Inggris: Letters from the Park)Sutradara: Tomás Gutiérrez Alea (Kuba)Diangkat dari: Novel El amor en los tiempos del cólera (1985) karya Gabriel García Márquez
 Jauh sebelum di-Hollywood-kan oleh Mike Newell pada 2007, Asmara Semasa Kolera karya García Márquez telah lebih dulu difilmkan oleh sutradara Kuba, Tomás Gutiérrez Alea
Jauh sebelum di-Hollywood-kan oleh Mike Newell pada 2007, Asmara Semasa Kolera karya García Márquez telah lebih dulu difilmkan oleh sutradara Kuba, Tomás Gutiérrez Alea
1990Tune in TomorrowSutradara: Jon Amiel (Inggris)Diangkat dari: Novel La tía Julia y el escribidor (1977) karya Mario Vargas Llosa
El almohadónSutradara: Alicia Violante (Meksiko)Diangkat dari: Cerpen “El almohadón de plumas” (1917) karya Horacio Quiroga dalam kumpulan Cuentos de amor, de locura y de muerte
O CorpoSutradara: José Antonio Garcia (Brasil)Diangkat dari: Cerpen “O Corpo” karya Clarice Lispector dalam kumpulan A via crucis do corpo (1974)
1991La cuesta de las comadresSutradara: Óscar Menéndez (Meksiko)Diangkat dari: Cerpen “La cuesta de las comadres” karya Juan Rulfo dalam kumpulan El llano en llamas (1953)
1992Like Water for ChocolateSutradara: Alfonso Arau (Meksiko)
Diangkat dari: Novel Como agua para chocolate (1989) karya Laura Esquivel
Mkholod sikvdili modis autsileblad (judul Inggris: Only Death Is Bound to Come)Sutradara: Marina Tsurtsumia (Georgia/Rusia)Diangkat dari: Novel Crónica de una muerte anunciada (1981) karya Gabriel García Márquez
El lado oscuro del corazón Sutradara: Eliseo Subiela (Argentina)Diangkat dari: Puisi “Corazón, coraza” karya Mario Benedetti dalam kumpulan Noción de patria (1962)
Death and the CompassSutradara: Alex Cox (Inggris)Diangkat dari: Cerpen “La muerte y la brújula” karya Jorge Luis Borges dalam kumpulan Ficciones (1942)
1993House of the SpiritsSutradara: Bille August (Denmark)Diangkat dari: Novel La casa de los espíritus (1982) karya Isabel Allende
1994Of Love and ShadowSutradara: Betty Kaplan (Venezuela)Diangkat dari: Novel De amor y de sombra (1985) karya Isabel Allende
Il PostinoSutradara: Michael Radford (Inggris)Diangkat dari: Novel Ardiente paciencia (1985) karya Antonio Skármeta
Death and the MaidenSutradara: Roman Polanski (Polandia-Perancis)Diangkat dari: Drama La muerte y la doncella (1991) karya Ariel Dorfman
Una sombra ya pronto serás (judul Inggris: A Shadow You Soon Will Be)Sutradara: Héctor Olivera (Argentina)Diangkat dari: Novel Una sombra ya pronto serás (1990) karya Osvaldo Soriano
1995Jonás y la ballena rosada(judul Inggris: Jonah and the Pink Whale)Sutradara: Juan Carlos Valdivia (Bolivia)Diangkat dari: Novel Jonás y la ballena rosada (1987) karya José Wolfango Montes Vannuci
1996Entre Marx y una mujer desnuda (judul Inggris: Between Marx and a Nude Woman)Sutradara: Camilo Luzuriaga (Ekuador)Diangkat dari: Novel Entre Marx y una mujer desnuda(1976) karya Jorge Enrique Adoum
1997O Que É Isso, Companheiro? (judul Inggris: Four Days in September)Sutradara: Bruno Barreto (Brasil)Diangkat dari: Memoar O Que É Isso Companheiro? (1979) karya Fernando Gabeira (eks anggota gerakan revolusioner kiri MR8, kemudian menjadi politisi dan anggota kongres dari Partai Hijau)
1998Doña BárbaraSutradara: Betty Kaplan (Venezuela)Diangkat dari: Novel Doña Bárbara (1929) karya Rómulo Gallegos
1999El coronel no tiene quien le escriba (judul Inggris: No One Writes to the Colonel)Sutradara: Arturo Ripstein (Meksiko)Diangkat dari: Novelet El coronel no tiene quien le escriba (1961) karya Gabriel García Márquez
2000Tinta roja (judul Inggris: Red Ink)Sutradara: Francisco J. Lombardi (Peru)Diangkat dari: Novel Tinta roja (1996) karya Alberto Fuguet
Pantaleón y las visitadoras (judul Inggris: Captain Pantoja and the Special Services)Sutradara: Francisco J. Lombardi (Peru)Diangkat dari: Novel Pantaleón y las visitadoras (1973) karya Mario Vargas Llosa
Plata quemada (judul Inggris: Burnt Money)Sutradara: Marcelo Piñeyro (Argentina)Diangkat dari: Novel Plata quemada(1997) karya Ricardo Piglia
Before Night FallsSutradara: Julian Schnabel (AS)Diangkat dari: Novel Antes que anochezca(1992) karya Reinaldo Arenas
La virgen de los sicarios (judul Inggris: Our Lady of the Assassins)Sutradara: Barbet Schroeder (Perancis-Spanyol)Diangkat dari: Novel La virgen de los sicarios (1994) karya Fernando Vallejo
Coronación (judul Inggris: Coronation)Sutradara: Silvio Caiozzi (Cile)Diangkat dari: Novel Coronación (1957) karya José Donoso
2001The Old Man Who Read Love StoriesSutradara: Rolf de Heer (Belanda)Diangkat dari: Novel Un viejo que leía novelas de amor (1989) karya Luis Sepúlveda
Sonhos tropicaisSutradara: André Sturm (Brasil)Diangkat dari: Novel Sonhos tropicais (1992) karya Moacyr Scliar
Antigua vida míaSutradara: Héctor Olivera (Argentina)Diangkat dari: Novel Antigua vida mía (1995) karya Marcela Serrano
2002Cidade de Deus (judul Inggris: The City of God)Sutradara: Fernando Meirelles (Brasil)Diangkat dari: Novel Cidade de Deus (1997) karya Paulo Lins
Tan de repente (judul Inggris: Suddenly)Sutradara: Diego Lerman (Argentina)Diangkat dari: Novel La prueba (1992) karya César Aira
La pluma del arcángel (judul Inggris: The Archangel's Feather)Sutradara: Luis Manzo (Venezuela)Diangkat dari: Cerpen “La pluma del arcángel” karya Arturo Uslar Pietri dalam kumpulan Los ganadores (1980)
2004Diários de Motocicleta (judul Inggris: The Motorcycle Diaries)Sutradara: Walter Salles (Brasil)Diangkat dari: Memoar Diarios de motocicleta: notas de viaje por America Latina (1967) karya Che Guevara; memoar Con el Che por Sudamérica (1978) karya Alberto Granado
CachimbaSutradara: Silvio Caiozzi (Cile)Diangkat dari: Novel Naturaleza muerta con cachimba (1989) karya José Donoso
2005La fiesta del chivo (judul Inggris: Feast of the Goat)Sutradara: Luis Llosa (Peru)Diangkat dari: Novel La fiesta del chivo (2000) karya Mario Vargas Llosa
Veronika wa shinu koto ni shita (judul Inggris: Veronika Decides to Die)Sutradara: Kei Horie (Jepang)Diangkat dari: Novel Veronika Decide Morrer (1998) karya Paulo Coelho
Rosario TijerasSutradara: Emilio Maillé (Kolombia)Diangkat dari: Novel Rosario Tijeras (1999) karya Jorge Franco
La mujer de mi hermano (judul Inggris: A Beautiful Wife)Sutradara: Ricardo de Montreuil (Peru)Diangkat dari: Novel La mujer de mi hermano (2002) karya Jaime Bayly
 Veronika Memutuskan Mati karya Paulo Coelho juga punya dua versi film:
Veronika Memutuskan Mati karya Paulo Coelho juga punya dua versi film:
Jepang (2005) dan Hollywood (2009)
2006O Veneno da Madrugada (judul Inggris: In Evil Hour)Sutradara: Ruy Guerra (Brasil)Diangkat dari: Novel La mala hora (1962) karya Gabriel García Márquez
2007El búfalo de la noche (judul Inggris: The Night Buffalo)Sutradara: Jorge Hernández Aldana (Meksiko)Diangkat dari: Novel El búfalo de la noche (2001) karya Guillermo Arriaga
Love in the Time of CholeraSutradara: Mike Newell (Inggris)Diangkat dari: Novel El amor en los tiempos del cólera (1985) karya Gabriel García Márquez
Ajolote Sutradara: Leonardo Davicino dan Agustín Falco (Argentina)Diangkat dari: Cerpen “Axolotl” (1956) karya Julio Cortázar dalam kumpulan Final del juego
2008Paraíso TravelSutradara: Simon Brand (Kolombia)Diangkat dari: Novel Paraíso Travel (2002) karya Jorge Franco
The Oxford MurdersSutradara: Álex de la Iglesia (Spanyol)Diangkat dari: Novel Crímenes imperceptibles (2003) karya Guillermo Martínez
Movajehe Sutradara: Saeed Ebrahimifar (Iran)Diangkat dari: Cerpen “El encuentro” karya Jorge Luis Borges dalam kumpulan El informe de Brodie (1970)
2009La teta asustada (judul Inggris: The Milk of Sorrow)Sutradara: Claudia Llosa (Peru)Diangkat dari: Kajian antropologi Entre prójimos: El conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú (2004) karya Kimberly Theidon
Del amor y otros demonios (judul Inggris: Of Love and Other Demons)Hilda Hidalgo (Kosta Rika) Diangkat dari: Novel Del amor y otros demonios (1994) karya Gabriel García Márquez
Veronika Decides to DieSutradara: Emily Young (Inggris)Diangkat dari: Novel Veronika Decide Morrer (1998) karya Paulo Coelho
El secreto de sus ojos(judul Inggris: The Secret in Their Eyes)Sutradara: Juan José Campanella (Argentina)Diangkat dari: Novel La pregunta de sus ojos (2005) karya Eduardo Sacheri
El baile de la Victoria (judul Inggris: The Dancer and the Thief)Sutradara: Fernando Trueba (Spanyol)Diangkat dari: Novel El baile de la Victoria (2003) karya Antonio Skármeta
El niño pez (judul Inggris: The Fish Child)Sutradara: Lucía Puenzo (Argentina)Diangkat dari: Novel El niño pez (2004) karya Lucía Puenzo
El corredor nocturno (judul Inggris: Night Runner) Sutradara: Gerardo Herrero (Argentina)Diangkat dari: Novel El corredor nocturno (2006) karya Hugo Burel
Dormir al sol (judul Inggris: Asleep in the Sun)Sutradara: Alejandro Chomski (Argentina)Diangkat dari: Novel Dormir al sol (1973) karya Adolfo Bioy Casares
2011BonsáiSutradara: Cristián Jiménez (Cile)Diangkat dari: Novel Bonsái (2006) karya Alejandro Zambra
2012NoSutradara: Pablo Larraín (Cile)Diangkat dari: Drama El plebiscito dan novel Los días del arco iris (2010) karya Antonio Skármeta
2013Flores Raras (judul Inggris: Reaching for the Moon)Sutradara: Bruno Barreto (Brasil)Diangkat dari: Kajian sastra-sejarah-biografi Flores raras e banalíssimas: a história de Lota de Macedo Soares e Elizabeth Bishop (1995) karya Carmen L. Oliveira
2015Un monstruo de mil cabezas (judul Inggris: A Monster with a Thousand Heads)Sutradara: Rodrigo Plá (Uruguay)Diangkat dari: Novel Un monstruo de mil cabezas (2013) karya Laura Santullo
 Beberapa karya Mario Vargas Llosa yang
Beberapa karya Mario Vargas Llosa yangsudah diangkat ke layar lebar
1950El crimen de Oribe (judul Inggris: The Crime of Oribe)Sutradara: Leopoldo Torre Nilsson (Argentina)Diangkat dari: Novel El perjurio de la nieve (1944) karya Adolfo Bioy Cesares
1954Días de odio (judul Inggris: Days of Hate)Sutradara: Leopoldo Torre Nilsson (Argentina)Diangkat dari: Cerpen “Emma Zunz” karya Jorge Luis Borges dalam kumpulan El Aleph (1949)
1957La casa del ángel (judul Inggris: The House of the Angel)Sutradara: Leopoldo Torre Nilsson (Argentina)Diangkat dari: Novel La casa del ángel (1957) karya Beatriz Guido
1964El gallo de oro(judul Inggris: The Golden Cockerel)Sutradara: Roberto Gavaldón (Meksiko)Diangkat dari: Novelet El gallo de oro (1959) karya Juan Rulfo; diadaptasi menjadi skenario oleh Carlos Fuentes dan Gabriel García Márquez
1965En este pueblo no hay ladrones (judul Inggris: There Are No Thieves in This Village)Sutradara: Alberto Isaac (Meksiko)Diangkat dari: Cerpen “En este pueblo no hay ladrones” karya Gabriel García Márquez dalam kumpulan Los funerales de la Mamá Grande (1962)
1966Blow-UpSutradara: Michelangelo Antonioni (Italia)Diangkat dari: Cerpen “Las babas del diablo” karya Julio Cortázar dalam kumpulan Las armas secretas (1959)
Emma ZunzSutradara: Jesús Martínez León (Spanyol)Diangkat dari: Cerpen “Emma Zunz” karya Jorge Luis Borges dalam kumpulan El Aleph (1949)
1968Memorias del subdesarrollo (judul Inggris: Memories of Underdevelopment)Sutradara: Tomás Gutiérrez Alea (Kuba)Diangkat dari: Novel Memorias del Subdesarrollo (1966) karya Edmundo Desnoes
Secret CeremonySutradara: Joseph Losey (AS)Diangkat dari: Novel Ceremonia secreta (1960) karya Marco Denevi
1974La tregua (judul Inggris: The Truce)Sutradara: Sergio Renán (Argentina) Diangkat dari: Novel La tregua (1960) karya Mario Benedetti
1976Dona Flor e Seus Dois Maridos (judul Inggris: Dona Flor and Her Two Husbands)Sutradara: Bruno Barreto (Brasil)Diangkat dari: Novel Dona Flor e Seus Dois Maridos (1966) karya Jorge Amado
Acaso irreparableSutradara: Dorotea Guerra (Meksiko)Diangkat dari: Cerpen “Acaso irreparable” karya Mario Benedetti dalam kumpulan La muerte y otras sorpresas (1968)
1978El lugar sin límites (judul Inggris: Hell Without Limits)Sutradara: Arturo Ripstein (Meksiko)Diangkat dari: Novelet El lugar sin límites (1966) karya José Donoso
Los de abajo (judul Inggris: The Underdogs)Sutradara: Servando González (Meksiko)Diangkat dari: Novel Los de abajo (1916) karya Mariano Azuela
1979Emma ZunzSutradara: Isabel Beveridge (Kanada)Diangkat dari: Cerpen “Emma Zunz” (1949) karya Jorge Luis Borges dalam kumpulan El Aleph
1982Kiss Me GoodbyeSutradara: Robert Mulligan (AS)Diangkat dari: Novel Dona Flor e Seus Dois Maridos (1966) karya Jorge Amado
1983EréndiraSutradara: Ruy Guerra (Brasil)Diangkat dari: Novelet La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada (1972) karya Gabriel García Márquez, meskipun novelet itu pun sesungguhnya awalnya berasal dari skenario film yang ditulis Gabo pada 1960an tetapi hilang
Gabriela, cravo e canela (judul Inggris: Gabriela)Sutradara: Bruno Barreto (Brasil)Diangkat dari: Novel Gabriela, cravo e canela (1958) karya Jorge Amado
No habrá más penas ni olvido (judul Inggris: Funny Dirty Little War)Sutradara: Héctor Olivera (Argentina)Diangkat dari: Novel No habrá más penas ni olvido (1980) karya Osvaldo Soriano
1984Emma ZunzSutradara: Peter Delpeut (Belanda)Diangkat dari: Cerpen “Emma Zunz” (1949) karya Jorge Luis Borges dalam kumpulan El Aleph
1985O Beijo da Mulher Aranha (judul Inggris: Kiss of the SpiderWoman)Sutradara: Héctor Babenco (Brasil) Diangkat dari: Novel El beso de la mujer araña (1976) karya Manuel Puig
La ciudad y los perros (judul Inggris: The City and the Dogs)Sutradara: Francisco J. Lombardi (Peru)Diangkat dari: Novel La ciudad y los perros (1963) karya Mario Vargas Llosa
Emma ZunzSutradara: Giangiacomo Tabet (Meksiko)Diangkat dari: Cerpen “Emma Zunz” karya Jorge Luis Borges dalam kumpulan El Aleph (1949)
1986Los amores de LauritaSutradara: Antonio Ottone (Argentina)Diangkat dari: Novel Los amores de Laurita (1984) karya Ana María Shua
Malayunta (judul Inggris: Bad Company)Sutradara: José Santiso (Argentina)Diangkat dari: Drama Paternoster (1972) karya Jacobo Langsner
1987Cronaca di una morte annunciata (judul Inggris: Chronicle of a Death Foretold)Sutradara: Francesco Rosi (Italia)Diangkat dari: Novel Crónica de una muerte anunciada (1981) karya Gabriel García Márquez
Der gläserne HimmelSutradara: Nina Grosse (Jerman)Diangkat dari: Cerpen “El otro cielo” karya Julio Cortázar dalam kumpulan Todos los fuegos el fuego (1966)
El túnel (judul Inggris: The Tunnel)Sutradara: Antonio Drove (Spanyol)Diangkat dari: Novel El túnel (1948) karya Ernesto Sábato
1988Un señor muy viejo con unas alas enormes (judul Inggris: A Very Old Man with Enormous Wings)Sutradara: Fernando Birri (Argentina)Diangkat dari: Cerpen “Un señor muy viejo con unas alas enormes” karya Gabriel García Márquez dalam kumpulan La Hojarasca (1955)
Der Radfahrer von San ChristobalSutradara: Peter Lilienthal (Jerman) Diangkat dari: Cerpen “El ciclista del San Cristóbal” (1973) karya Antonio Skármeta dari kumpulan cerpen berjudul sama
Cinco años de mi vidaSutradara: Antonio Pinar (Spanyol)Diangkat dari: Cerpen “Cinco años de mi vida” karya Mario Benedetti dalam kumpulan La muerte y otras sorpresas (1968)
1989Old GringoSutradara: Luis Puenzo (Argentina)Diangkat dari: Novel Gringo viejo (1985) karya Carlos Fuentes
Cartas del parque (judul Inggris: Letters from the Park)Sutradara: Tomás Gutiérrez Alea (Kuba)Diangkat dari: Novel El amor en los tiempos del cólera (1985) karya Gabriel García Márquez
 Jauh sebelum di-Hollywood-kan oleh Mike Newell pada 2007, Asmara Semasa Kolera karya García Márquez telah lebih dulu difilmkan oleh sutradara Kuba, Tomás Gutiérrez Alea
Jauh sebelum di-Hollywood-kan oleh Mike Newell pada 2007, Asmara Semasa Kolera karya García Márquez telah lebih dulu difilmkan oleh sutradara Kuba, Tomás Gutiérrez Alea1990Tune in TomorrowSutradara: Jon Amiel (Inggris)Diangkat dari: Novel La tía Julia y el escribidor (1977) karya Mario Vargas Llosa
El almohadónSutradara: Alicia Violante (Meksiko)Diangkat dari: Cerpen “El almohadón de plumas” (1917) karya Horacio Quiroga dalam kumpulan Cuentos de amor, de locura y de muerte
O CorpoSutradara: José Antonio Garcia (Brasil)Diangkat dari: Cerpen “O Corpo” karya Clarice Lispector dalam kumpulan A via crucis do corpo (1974)
1991La cuesta de las comadresSutradara: Óscar Menéndez (Meksiko)Diangkat dari: Cerpen “La cuesta de las comadres” karya Juan Rulfo dalam kumpulan El llano en llamas (1953)
1992Like Water for ChocolateSutradara: Alfonso Arau (Meksiko)
Diangkat dari: Novel Como agua para chocolate (1989) karya Laura Esquivel
Mkholod sikvdili modis autsileblad (judul Inggris: Only Death Is Bound to Come)Sutradara: Marina Tsurtsumia (Georgia/Rusia)Diangkat dari: Novel Crónica de una muerte anunciada (1981) karya Gabriel García Márquez
El lado oscuro del corazón Sutradara: Eliseo Subiela (Argentina)Diangkat dari: Puisi “Corazón, coraza” karya Mario Benedetti dalam kumpulan Noción de patria (1962)
Death and the CompassSutradara: Alex Cox (Inggris)Diangkat dari: Cerpen “La muerte y la brújula” karya Jorge Luis Borges dalam kumpulan Ficciones (1942)
1993House of the SpiritsSutradara: Bille August (Denmark)Diangkat dari: Novel La casa de los espíritus (1982) karya Isabel Allende
1994Of Love and ShadowSutradara: Betty Kaplan (Venezuela)Diangkat dari: Novel De amor y de sombra (1985) karya Isabel Allende
Il PostinoSutradara: Michael Radford (Inggris)Diangkat dari: Novel Ardiente paciencia (1985) karya Antonio Skármeta
Death and the MaidenSutradara: Roman Polanski (Polandia-Perancis)Diangkat dari: Drama La muerte y la doncella (1991) karya Ariel Dorfman
Una sombra ya pronto serás (judul Inggris: A Shadow You Soon Will Be)Sutradara: Héctor Olivera (Argentina)Diangkat dari: Novel Una sombra ya pronto serás (1990) karya Osvaldo Soriano
1995Jonás y la ballena rosada(judul Inggris: Jonah and the Pink Whale)Sutradara: Juan Carlos Valdivia (Bolivia)Diangkat dari: Novel Jonás y la ballena rosada (1987) karya José Wolfango Montes Vannuci
1996Entre Marx y una mujer desnuda (judul Inggris: Between Marx and a Nude Woman)Sutradara: Camilo Luzuriaga (Ekuador)Diangkat dari: Novel Entre Marx y una mujer desnuda(1976) karya Jorge Enrique Adoum
1997O Que É Isso, Companheiro? (judul Inggris: Four Days in September)Sutradara: Bruno Barreto (Brasil)Diangkat dari: Memoar O Que É Isso Companheiro? (1979) karya Fernando Gabeira (eks anggota gerakan revolusioner kiri MR8, kemudian menjadi politisi dan anggota kongres dari Partai Hijau)
1998Doña BárbaraSutradara: Betty Kaplan (Venezuela)Diangkat dari: Novel Doña Bárbara (1929) karya Rómulo Gallegos
1999El coronel no tiene quien le escriba (judul Inggris: No One Writes to the Colonel)Sutradara: Arturo Ripstein (Meksiko)Diangkat dari: Novelet El coronel no tiene quien le escriba (1961) karya Gabriel García Márquez
2000Tinta roja (judul Inggris: Red Ink)Sutradara: Francisco J. Lombardi (Peru)Diangkat dari: Novel Tinta roja (1996) karya Alberto Fuguet
Pantaleón y las visitadoras (judul Inggris: Captain Pantoja and the Special Services)Sutradara: Francisco J. Lombardi (Peru)Diangkat dari: Novel Pantaleón y las visitadoras (1973) karya Mario Vargas Llosa
Plata quemada (judul Inggris: Burnt Money)Sutradara: Marcelo Piñeyro (Argentina)Diangkat dari: Novel Plata quemada(1997) karya Ricardo Piglia
Before Night FallsSutradara: Julian Schnabel (AS)Diangkat dari: Novel Antes que anochezca(1992) karya Reinaldo Arenas
La virgen de los sicarios (judul Inggris: Our Lady of the Assassins)Sutradara: Barbet Schroeder (Perancis-Spanyol)Diangkat dari: Novel La virgen de los sicarios (1994) karya Fernando Vallejo
Coronación (judul Inggris: Coronation)Sutradara: Silvio Caiozzi (Cile)Diangkat dari: Novel Coronación (1957) karya José Donoso
2001The Old Man Who Read Love StoriesSutradara: Rolf de Heer (Belanda)Diangkat dari: Novel Un viejo que leía novelas de amor (1989) karya Luis Sepúlveda
Sonhos tropicaisSutradara: André Sturm (Brasil)Diangkat dari: Novel Sonhos tropicais (1992) karya Moacyr Scliar
Antigua vida míaSutradara: Héctor Olivera (Argentina)Diangkat dari: Novel Antigua vida mía (1995) karya Marcela Serrano
2002Cidade de Deus (judul Inggris: The City of God)Sutradara: Fernando Meirelles (Brasil)Diangkat dari: Novel Cidade de Deus (1997) karya Paulo Lins
Tan de repente (judul Inggris: Suddenly)Sutradara: Diego Lerman (Argentina)Diangkat dari: Novel La prueba (1992) karya César Aira
La pluma del arcángel (judul Inggris: The Archangel's Feather)Sutradara: Luis Manzo (Venezuela)Diangkat dari: Cerpen “La pluma del arcángel” karya Arturo Uslar Pietri dalam kumpulan Los ganadores (1980)
2004Diários de Motocicleta (judul Inggris: The Motorcycle Diaries)Sutradara: Walter Salles (Brasil)Diangkat dari: Memoar Diarios de motocicleta: notas de viaje por America Latina (1967) karya Che Guevara; memoar Con el Che por Sudamérica (1978) karya Alberto Granado
CachimbaSutradara: Silvio Caiozzi (Cile)Diangkat dari: Novel Naturaleza muerta con cachimba (1989) karya José Donoso
2005La fiesta del chivo (judul Inggris: Feast of the Goat)Sutradara: Luis Llosa (Peru)Diangkat dari: Novel La fiesta del chivo (2000) karya Mario Vargas Llosa
Veronika wa shinu koto ni shita (judul Inggris: Veronika Decides to Die)Sutradara: Kei Horie (Jepang)Diangkat dari: Novel Veronika Decide Morrer (1998) karya Paulo Coelho
Rosario TijerasSutradara: Emilio Maillé (Kolombia)Diangkat dari: Novel Rosario Tijeras (1999) karya Jorge Franco
La mujer de mi hermano (judul Inggris: A Beautiful Wife)Sutradara: Ricardo de Montreuil (Peru)Diangkat dari: Novel La mujer de mi hermano (2002) karya Jaime Bayly
 Veronika Memutuskan Mati karya Paulo Coelho juga punya dua versi film:
Veronika Memutuskan Mati karya Paulo Coelho juga punya dua versi film:Jepang (2005) dan Hollywood (2009)
2006O Veneno da Madrugada (judul Inggris: In Evil Hour)Sutradara: Ruy Guerra (Brasil)Diangkat dari: Novel La mala hora (1962) karya Gabriel García Márquez
2007El búfalo de la noche (judul Inggris: The Night Buffalo)Sutradara: Jorge Hernández Aldana (Meksiko)Diangkat dari: Novel El búfalo de la noche (2001) karya Guillermo Arriaga
Love in the Time of CholeraSutradara: Mike Newell (Inggris)Diangkat dari: Novel El amor en los tiempos del cólera (1985) karya Gabriel García Márquez
Ajolote Sutradara: Leonardo Davicino dan Agustín Falco (Argentina)Diangkat dari: Cerpen “Axolotl” (1956) karya Julio Cortázar dalam kumpulan Final del juego
2008Paraíso TravelSutradara: Simon Brand (Kolombia)Diangkat dari: Novel Paraíso Travel (2002) karya Jorge Franco
The Oxford MurdersSutradara: Álex de la Iglesia (Spanyol)Diangkat dari: Novel Crímenes imperceptibles (2003) karya Guillermo Martínez
Movajehe Sutradara: Saeed Ebrahimifar (Iran)Diangkat dari: Cerpen “El encuentro” karya Jorge Luis Borges dalam kumpulan El informe de Brodie (1970)
2009La teta asustada (judul Inggris: The Milk of Sorrow)Sutradara: Claudia Llosa (Peru)Diangkat dari: Kajian antropologi Entre prójimos: El conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú (2004) karya Kimberly Theidon
Del amor y otros demonios (judul Inggris: Of Love and Other Demons)Hilda Hidalgo (Kosta Rika) Diangkat dari: Novel Del amor y otros demonios (1994) karya Gabriel García Márquez
Veronika Decides to DieSutradara: Emily Young (Inggris)Diangkat dari: Novel Veronika Decide Morrer (1998) karya Paulo Coelho
El secreto de sus ojos(judul Inggris: The Secret in Their Eyes)Sutradara: Juan José Campanella (Argentina)Diangkat dari: Novel La pregunta de sus ojos (2005) karya Eduardo Sacheri
El baile de la Victoria (judul Inggris: The Dancer and the Thief)Sutradara: Fernando Trueba (Spanyol)Diangkat dari: Novel El baile de la Victoria (2003) karya Antonio Skármeta
El niño pez (judul Inggris: The Fish Child)Sutradara: Lucía Puenzo (Argentina)Diangkat dari: Novel El niño pez (2004) karya Lucía Puenzo
El corredor nocturno (judul Inggris: Night Runner) Sutradara: Gerardo Herrero (Argentina)Diangkat dari: Novel El corredor nocturno (2006) karya Hugo Burel
Dormir al sol (judul Inggris: Asleep in the Sun)Sutradara: Alejandro Chomski (Argentina)Diangkat dari: Novel Dormir al sol (1973) karya Adolfo Bioy Casares
2011BonsáiSutradara: Cristián Jiménez (Cile)Diangkat dari: Novel Bonsái (2006) karya Alejandro Zambra
2012NoSutradara: Pablo Larraín (Cile)Diangkat dari: Drama El plebiscito dan novel Los días del arco iris (2010) karya Antonio Skármeta
2013Flores Raras (judul Inggris: Reaching for the Moon)Sutradara: Bruno Barreto (Brasil)Diangkat dari: Kajian sastra-sejarah-biografi Flores raras e banalíssimas: a história de Lota de Macedo Soares e Elizabeth Bishop (1995) karya Carmen L. Oliveira
2015Un monstruo de mil cabezas (judul Inggris: A Monster with a Thousand Heads)Sutradara: Rodrigo Plá (Uruguay)Diangkat dari: Novel Un monstruo de mil cabezas (2013) karya Laura Santullo
Published on August 03, 2016 17:30
June 5, 2016
“Sungai Kehidupan Kami,” oleh Gabriel García Márquez
“El río de nuestra vida”, El Espectador, 22 Maret 1981, dimuat ulang di El País 25 Maret 1981 dengan judul “El río de la vida”. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Ronny Agustinus.
Satu-satunya yang bisa membuat saya ingin kembali jadi anak-anak adalah pergi sekali lagi naik kapal uap menyusuri Sungai Magdalena. Barangsiapa belum pernah mengalaminya tak bakal bisa membayangkan seperti apa rasanya. Saya harus menjalaninya dua kali setahun —pulang pergi—selama enam tahun di sekolah menengah dan dua tahun di universitas, dan pada setiap kesempatan belajar lebih banyak, dan lebih baik, tentang kehidupan ketimbang yang saya dapatkan di sekolah. Pada saat arus air sedang pasang, perjalanan makan waktu lima hari dari Barranquilla ke Puerto Salgar, di mana kereta akan mengangkut kami ke Bogotá. Pada musim kering, saat yang sangat dan paling menyenangkan buat bepergian, pelayaran bisa mulur sampai tiga minggu.
Kereta dari Puerto Salgar meniti tepian batu seharian penuh. Di tanjakan-tanjakan tercuram ia menggelinding mundur untuk mencari daya dorong, lalu maju lagi mendengus-dengus naik bak seekor naga, dan kadang penumpang sampai perlu turun dan berjalan kaki hingga ke landaian berikutnya, buat meringankan beban. Desa-desa di sepanjang rel beku dan sedih, dan para bakul yang seumur hidupnya berjualan menawar-nawarkan di jendela kereta ayam bumbu kuning besar dimasak utuh serta kentang tumbuk yang baunya seperti makanan rumah sakit. Kereta tiba di Bogotá pukul enam sore, yang buat saya jadi seperti momen tersuram dalam hidup. Kota ini murung dan beku, dengan trem-trem berisik memercikkan bunga api di tiap tikungan, dan kucuran hujan air campur jelaga tak pernah reda. Para prianya berpakaian hitam-hitam, dengan topi hitam, berjalan cepat-cepat dan bersenggolan seperti ada urusan mendesak, dan tak ada satu pun perempuan terlihat di jalanan. Kami harus menghabiskan setahun penuh di sana, pura-pura belajar, padahal yang kami perbuat sesungguhnya cuma menunggu bulan Desember tiba agar bisa melayari Sungai Magdalena sekali lagi.
Di zaman itu kapal uap punya tiga tingkat dan dua cerobong asap, yang pada malam hari melaju seperti kampung terang-benderang, meninggalkan jejak musik dan mimpi-mimpi ilusif ke dukuh-dukuh di pinggiran kali. Bedanya dengan kapal-kapal di Mississippi, roda pendorong kapal kami bukan berada di sisi-sisinya, melainkan di buritan, dan tak pernah di bagian mana pun di dunia saya melihat lagi yang seperti itu. Nama-namanya mudah dan cepat diingat: Atlántico, Medellín, Capitán de Caro, David Arango. Kapten-kapten mereka, seperti dalam cerita-cerita Conrad, berwibawa tapi lembut hati, makannya seperti orang barbar, dan tak pernah tidur sendirian di kabin-kabin mereka yang terpencil. Awak kapal menyebut diri sendiri marineros (pelaut) seolah-olah sedang berada di tengah samudera. Namun di bar-bar dan rumah-rumah bordil Barranquilla, saat sedang berbaur di tengah para pelaut sungguhan, mereka dikenal dengan nama khasnya: vaporinos(tukang kapal uap).
Perjalanan lambat dan penuh kejutan di siang hari, para penumpang duduk-duduk di geladak atas memandangi hidup berlalu. Kami bisa melihat buaya-buaya mengapung di kedangkalan seperti batang pohon, dengan mulut menganga, menanti mangsa masuk. Kami lihat kawanan kuntul terbang ketakutan saat kapal lewat, rombongan itik liar di paya-paya pedalaman, ikan tiada akhir, duyung menyusui anakan mereka dan memekik-mekik seperti sedang menyanyi di pinggiran. Kadang, bau busuk memualkan menganggu tidur siang kami, dan bangkai seekor sapi besar yang tenggelam mengambang-ambang nyaris seperti tak bergerak dibawa arus dengan seekor burung nasar bertengger di perutnya. Sepanjang jalan, kami terbangun saat subuh, kaget oleh hiruk-pikuk monyet-monyet dan ocehan burung bayan.
Pada zaman sekarang susah untuk mengenal siapa-siapa dalam penerbangan udara. Tapi di kapal-kapal Sungai Magdalena itu, para penumpang akhirnya seperti satu keluarga besar, sebab kami sepakat tiap tahunnya bertemu lagi di perjalanan. Keluarga Eljach turun di Calamar, keluarga Peña dan Del Toro –dari dusun—naik di Plato; keluarga Estorino dan Viña di Magangué, keluarga Villafañes di Banco. Makin lama perjalanan, pestanya makin meriah. Kehidupan kami terhubung dengan cara yang sepintas lalu, tapi tak terlupakan, dengan orang-orang di dermaga-dermaga pemberhentian, dan banyak akhirnya yang nasibnya jadi terpaut selamanya. Vicente Escudero, seorang mahasiswa kedokteran, ikut menari tanpa diundang di pesta kawinan di Gamarra, berdansa tanpa minta izin dengan perempuan tercantik di desa itu, lalu ditembak dan dibunuh oleh suami si perempuan. Sebaliknya, Pedro Pablo Guillén menikahi gadis pertama yang ia sukai dalam pesta mabuk-mabukan legendaris di Barrancabermeja, dan sampai sekarang masih hidup berbahagia dengan istrinya itu dan kesembilan anaknya. José Palencia yang tiada duanya, seorang musisi bawaan lahir, ikut lomba genderang di Tenerife, memenangkan seekor sapi dan menjualnya saat itu juga seharga 50 peso: sudah kaya di zaman itu. Kadang kapal bisa kandas sampai lima belas hari di gundukan pasir. Tak ada yang keberatan, sebab ini berarti pesta berlanjut, dan surat dengan stempel sang kapten sudah cukup untuk jadi alasan mengapa terlambat masuk sekolah.
Suatu malam, dalam perjalanan terakhir saya tahun 1948, kami semua terbangun oleh tangis memilukan dari pinggir sungai. Kapten Climaco Conde Abello, salah satu kapten terbesar, memerintahkan orang-orangnya mengarahkan reflektor ke tempat kegaduhan berasal. Seekor duyung betina terjerat ranting-ranting pohon tumbang. Para awak lompat ke air, mengikat hewan itu ke lir, dan berhasil melepaskannya. Hewan yang fantastis dan menggugah, hampir empat meter panjangnya, kulitnya pucat mulus, dan torsonya kelihatan seperti perempuan, dengan tetek besar seorang ibu yang penuh kasih, dan mata lebar sayu yang menitikkan air mata manusia. Dari Kapten Conde Abello jugalah saya mendengar untuk pertama kalinya bahwa dunia akan berakhir apabila semua orang terus membunuhi binatang-binatang sungai. Ia larang siapa pun menembak dari geladak. “Kalau mau bunuh-bunuhan, di rumah sendiri-sendiri saja,” serunya, “Tidak di kapalku.” Namun tak ada yang mengindahkannya. Tiga belas tahun kemudian –pada 19 Januari 1961—seorang kawan menelepon saya di Meksiko mengabarkan bahwa kapal uap David Arango terbakar jadi abu di dermaga Magangué. Saat menutp telepon saya mendapat kesan mengerikan bahwa masa muda saya akhirnya tamat, dan bahwa yang tersisa dari sungai kami tinggallah nostalgia yang sudah hancur terbakar.
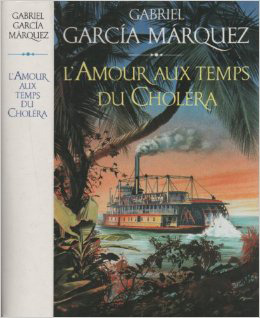 Sungai Magdalena menjadi latar banyak
Sungai Magdalena menjadi latar banyak
karya García Márquez. Kapal uap di artikel ini
tergambar dengan baik di sampul edisi
Perancis El amor en los tiempos del cólera.Dan memang terbukti. Sungai Magdalena mati, dengan air yang teracuni dan hewan-hewan yang diburu sampai punah. Kerja pelestarian yang mulai dibicarakan pemerintah sejak sekelompok jurnalis yang peduli mengangkat permasalahan ini tak lebih dari hiburan lawak. Rehabilitasi Sungai Magdalena hanya mungkin dilakukan melalui upaya intens dan terus-menerus dari sekurang-kurangnya empat generasi yang peduli: dengan kata lain, satu abad penuh.
Orang bicara gampang saja soal reboisasi. Itu saja, dalam kenyataannya, berarti menanam 59,110 juta batang pohon di sepanjang tepian Sungai Magdalena. Ucapkan secara penuh: lima puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu batang pohon. Namun masalah terbesarnya bukan jumlah, tetapi di mana akan ditanam. Hampir semua lahan subur di tepi sungai itu milik swasta, dan penghijauan menyeluruh berarti menutupi 90% luasannya. Layak ditanyakan siapa pemilik tanah baik hati yang mau dengan rela menyerahkan 90% lahan mereka buat ditanami pohon, dan dengan demikian merelakan perginya 90% pendapatan mereka saat ini.
Pencemaran, di lain pihak, bukan cuma berdampak pada Sungai Magdalena, tetapi juga semua anak sungainya. Anak-anak sungai ini bukan cuma menjadi drainase kota-kota dan desa-desa tepian, tapi menyeret dan menumpuk juga limbah industri, pertanian, hewan, dan manusia, yang semuanya mengalir ke dalam tampungan maha luas sampah nasional yakni Bocas de Ceniza. Pada November tahun lalu, di Tocaima, dua orang prajurit gerilya menceburkan diri ke Sungai Bogotá untuk kabur dari sergapan tentara. Mereka berhasil lolos, tapi nyaris mati terinfeksi air sungai. Para penghuni tepian Magdalena, terutama di sisi bawah, sudah lama tak pernah lagi meminum atau memanfaatkan airnya atau makan ikan segar dari sungai. Karena itu akan sama dengan –maafkan bahasa saya, nyonya-nyonya—makan tai.
Kerja besar, tapi setidaknya terukur. Proyek lengkap dari apa yang perlu dilakukan sudah dirinci dalam studi yang dijalankan beberapa tahun lalu oleh tim gabungan Belanda-Kolombia, dan tiga puluh jilid hasilnya teronggok telantar di arsip Instituto de Hidrología y Meteorologia (IMAT). Wakil direktur untuk kerja monumental ini adalah insinyur muda dari Antioquia, Jairo Murillo, yang mengabdikan separuh hayatnya untuk itu, dan sebelum rampung mengorbankan sisa umurnya untuk itu pula: ia tenggelam dalam sungai impiannya. Tak perlu dibilang lagi bahwa tak ada kandidat presiden selama beberapa tahun terakhir ini yang berisiko kehilangan nyawa di perairan seperti itu. Para penduduk desa tepian sungai —yang sebentar lagi akan menjadi pusat perhatian nasional berkat ekspedisi Caracola
Catatan penerjemah: La Caracola adalah perahu yang dibiayai oleh jaringan radio swasta Kolombia pada tahun 1980an untuk meningkatkan kesadaran tentang kerusakan lingkungan di Sungai Magdalena dan daerah alirannya.
Satu-satunya yang bisa membuat saya ingin kembali jadi anak-anak adalah pergi sekali lagi naik kapal uap menyusuri Sungai Magdalena. Barangsiapa belum pernah mengalaminya tak bakal bisa membayangkan seperti apa rasanya. Saya harus menjalaninya dua kali setahun —pulang pergi—selama enam tahun di sekolah menengah dan dua tahun di universitas, dan pada setiap kesempatan belajar lebih banyak, dan lebih baik, tentang kehidupan ketimbang yang saya dapatkan di sekolah. Pada saat arus air sedang pasang, perjalanan makan waktu lima hari dari Barranquilla ke Puerto Salgar, di mana kereta akan mengangkut kami ke Bogotá. Pada musim kering, saat yang sangat dan paling menyenangkan buat bepergian, pelayaran bisa mulur sampai tiga minggu.
Kereta dari Puerto Salgar meniti tepian batu seharian penuh. Di tanjakan-tanjakan tercuram ia menggelinding mundur untuk mencari daya dorong, lalu maju lagi mendengus-dengus naik bak seekor naga, dan kadang penumpang sampai perlu turun dan berjalan kaki hingga ke landaian berikutnya, buat meringankan beban. Desa-desa di sepanjang rel beku dan sedih, dan para bakul yang seumur hidupnya berjualan menawar-nawarkan di jendela kereta ayam bumbu kuning besar dimasak utuh serta kentang tumbuk yang baunya seperti makanan rumah sakit. Kereta tiba di Bogotá pukul enam sore, yang buat saya jadi seperti momen tersuram dalam hidup. Kota ini murung dan beku, dengan trem-trem berisik memercikkan bunga api di tiap tikungan, dan kucuran hujan air campur jelaga tak pernah reda. Para prianya berpakaian hitam-hitam, dengan topi hitam, berjalan cepat-cepat dan bersenggolan seperti ada urusan mendesak, dan tak ada satu pun perempuan terlihat di jalanan. Kami harus menghabiskan setahun penuh di sana, pura-pura belajar, padahal yang kami perbuat sesungguhnya cuma menunggu bulan Desember tiba agar bisa melayari Sungai Magdalena sekali lagi.
Di zaman itu kapal uap punya tiga tingkat dan dua cerobong asap, yang pada malam hari melaju seperti kampung terang-benderang, meninggalkan jejak musik dan mimpi-mimpi ilusif ke dukuh-dukuh di pinggiran kali. Bedanya dengan kapal-kapal di Mississippi, roda pendorong kapal kami bukan berada di sisi-sisinya, melainkan di buritan, dan tak pernah di bagian mana pun di dunia saya melihat lagi yang seperti itu. Nama-namanya mudah dan cepat diingat: Atlántico, Medellín, Capitán de Caro, David Arango. Kapten-kapten mereka, seperti dalam cerita-cerita Conrad, berwibawa tapi lembut hati, makannya seperti orang barbar, dan tak pernah tidur sendirian di kabin-kabin mereka yang terpencil. Awak kapal menyebut diri sendiri marineros (pelaut) seolah-olah sedang berada di tengah samudera. Namun di bar-bar dan rumah-rumah bordil Barranquilla, saat sedang berbaur di tengah para pelaut sungguhan, mereka dikenal dengan nama khasnya: vaporinos(tukang kapal uap).
Perjalanan lambat dan penuh kejutan di siang hari, para penumpang duduk-duduk di geladak atas memandangi hidup berlalu. Kami bisa melihat buaya-buaya mengapung di kedangkalan seperti batang pohon, dengan mulut menganga, menanti mangsa masuk. Kami lihat kawanan kuntul terbang ketakutan saat kapal lewat, rombongan itik liar di paya-paya pedalaman, ikan tiada akhir, duyung menyusui anakan mereka dan memekik-mekik seperti sedang menyanyi di pinggiran. Kadang, bau busuk memualkan menganggu tidur siang kami, dan bangkai seekor sapi besar yang tenggelam mengambang-ambang nyaris seperti tak bergerak dibawa arus dengan seekor burung nasar bertengger di perutnya. Sepanjang jalan, kami terbangun saat subuh, kaget oleh hiruk-pikuk monyet-monyet dan ocehan burung bayan.
Pada zaman sekarang susah untuk mengenal siapa-siapa dalam penerbangan udara. Tapi di kapal-kapal Sungai Magdalena itu, para penumpang akhirnya seperti satu keluarga besar, sebab kami sepakat tiap tahunnya bertemu lagi di perjalanan. Keluarga Eljach turun di Calamar, keluarga Peña dan Del Toro –dari dusun—naik di Plato; keluarga Estorino dan Viña di Magangué, keluarga Villafañes di Banco. Makin lama perjalanan, pestanya makin meriah. Kehidupan kami terhubung dengan cara yang sepintas lalu, tapi tak terlupakan, dengan orang-orang di dermaga-dermaga pemberhentian, dan banyak akhirnya yang nasibnya jadi terpaut selamanya. Vicente Escudero, seorang mahasiswa kedokteran, ikut menari tanpa diundang di pesta kawinan di Gamarra, berdansa tanpa minta izin dengan perempuan tercantik di desa itu, lalu ditembak dan dibunuh oleh suami si perempuan. Sebaliknya, Pedro Pablo Guillén menikahi gadis pertama yang ia sukai dalam pesta mabuk-mabukan legendaris di Barrancabermeja, dan sampai sekarang masih hidup berbahagia dengan istrinya itu dan kesembilan anaknya. José Palencia yang tiada duanya, seorang musisi bawaan lahir, ikut lomba genderang di Tenerife, memenangkan seekor sapi dan menjualnya saat itu juga seharga 50 peso: sudah kaya di zaman itu. Kadang kapal bisa kandas sampai lima belas hari di gundukan pasir. Tak ada yang keberatan, sebab ini berarti pesta berlanjut, dan surat dengan stempel sang kapten sudah cukup untuk jadi alasan mengapa terlambat masuk sekolah.
Suatu malam, dalam perjalanan terakhir saya tahun 1948, kami semua terbangun oleh tangis memilukan dari pinggir sungai. Kapten Climaco Conde Abello, salah satu kapten terbesar, memerintahkan orang-orangnya mengarahkan reflektor ke tempat kegaduhan berasal. Seekor duyung betina terjerat ranting-ranting pohon tumbang. Para awak lompat ke air, mengikat hewan itu ke lir, dan berhasil melepaskannya. Hewan yang fantastis dan menggugah, hampir empat meter panjangnya, kulitnya pucat mulus, dan torsonya kelihatan seperti perempuan, dengan tetek besar seorang ibu yang penuh kasih, dan mata lebar sayu yang menitikkan air mata manusia. Dari Kapten Conde Abello jugalah saya mendengar untuk pertama kalinya bahwa dunia akan berakhir apabila semua orang terus membunuhi binatang-binatang sungai. Ia larang siapa pun menembak dari geladak. “Kalau mau bunuh-bunuhan, di rumah sendiri-sendiri saja,” serunya, “Tidak di kapalku.” Namun tak ada yang mengindahkannya. Tiga belas tahun kemudian –pada 19 Januari 1961—seorang kawan menelepon saya di Meksiko mengabarkan bahwa kapal uap David Arango terbakar jadi abu di dermaga Magangué. Saat menutp telepon saya mendapat kesan mengerikan bahwa masa muda saya akhirnya tamat, dan bahwa yang tersisa dari sungai kami tinggallah nostalgia yang sudah hancur terbakar.
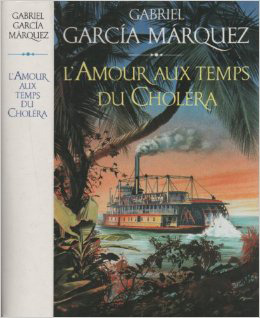 Sungai Magdalena menjadi latar banyak
Sungai Magdalena menjadi latar banyakkarya García Márquez. Kapal uap di artikel ini
tergambar dengan baik di sampul edisi
Perancis El amor en los tiempos del cólera.Dan memang terbukti. Sungai Magdalena mati, dengan air yang teracuni dan hewan-hewan yang diburu sampai punah. Kerja pelestarian yang mulai dibicarakan pemerintah sejak sekelompok jurnalis yang peduli mengangkat permasalahan ini tak lebih dari hiburan lawak. Rehabilitasi Sungai Magdalena hanya mungkin dilakukan melalui upaya intens dan terus-menerus dari sekurang-kurangnya empat generasi yang peduli: dengan kata lain, satu abad penuh.
Orang bicara gampang saja soal reboisasi. Itu saja, dalam kenyataannya, berarti menanam 59,110 juta batang pohon di sepanjang tepian Sungai Magdalena. Ucapkan secara penuh: lima puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu batang pohon. Namun masalah terbesarnya bukan jumlah, tetapi di mana akan ditanam. Hampir semua lahan subur di tepi sungai itu milik swasta, dan penghijauan menyeluruh berarti menutupi 90% luasannya. Layak ditanyakan siapa pemilik tanah baik hati yang mau dengan rela menyerahkan 90% lahan mereka buat ditanami pohon, dan dengan demikian merelakan perginya 90% pendapatan mereka saat ini.
Pencemaran, di lain pihak, bukan cuma berdampak pada Sungai Magdalena, tetapi juga semua anak sungainya. Anak-anak sungai ini bukan cuma menjadi drainase kota-kota dan desa-desa tepian, tapi menyeret dan menumpuk juga limbah industri, pertanian, hewan, dan manusia, yang semuanya mengalir ke dalam tampungan maha luas sampah nasional yakni Bocas de Ceniza. Pada November tahun lalu, di Tocaima, dua orang prajurit gerilya menceburkan diri ke Sungai Bogotá untuk kabur dari sergapan tentara. Mereka berhasil lolos, tapi nyaris mati terinfeksi air sungai. Para penghuni tepian Magdalena, terutama di sisi bawah, sudah lama tak pernah lagi meminum atau memanfaatkan airnya atau makan ikan segar dari sungai. Karena itu akan sama dengan –maafkan bahasa saya, nyonya-nyonya—makan tai.
Kerja besar, tapi setidaknya terukur. Proyek lengkap dari apa yang perlu dilakukan sudah dirinci dalam studi yang dijalankan beberapa tahun lalu oleh tim gabungan Belanda-Kolombia, dan tiga puluh jilid hasilnya teronggok telantar di arsip Instituto de Hidrología y Meteorologia (IMAT). Wakil direktur untuk kerja monumental ini adalah insinyur muda dari Antioquia, Jairo Murillo, yang mengabdikan separuh hayatnya untuk itu, dan sebelum rampung mengorbankan sisa umurnya untuk itu pula: ia tenggelam dalam sungai impiannya. Tak perlu dibilang lagi bahwa tak ada kandidat presiden selama beberapa tahun terakhir ini yang berisiko kehilangan nyawa di perairan seperti itu. Para penduduk desa tepian sungai —yang sebentar lagi akan menjadi pusat perhatian nasional berkat ekspedisi Caracola
Catatan penerjemah: La Caracola adalah perahu yang dibiayai oleh jaringan radio swasta Kolombia pada tahun 1980an untuk meningkatkan kesadaran tentang kerusakan lingkungan di Sungai Magdalena dan daerah alirannya.
Published on June 05, 2016 23:52
April 7, 2016
"Pablo Neruda: Setengah Abad Sudah Abadi", oleh Njoto
Disalin dari Harian Rakjat, 10 Djuli 1954. Njoto menulis dengan nama pena Iramani.

Besok, tg. 11 Djuli, akan berkumpul dikota Santiago, Chili, be-ribu2 kalau tidak ber-puluh2ribu Rakjat, diorganisasi oleh sebuah Panitia terdiri dari pengarang dan pemenang Hadiah Seni Nasional, Pedro de la Barra, pendiri Orkestra Simfoni, Armando Carvajal, ketua Parlemen dan novelis, Baltasar Castro, direktur Perpustakaan Universitet Chili, Hector Fuenzalida, pengarang dan direktur Museum Kesenian Rakjat, Tomas Lago, dan banjak lagi. Mereka akan memperingati genap setengah abad umur salah seorang pengarang dan putera Chili, Pablo Neruda.
Jang paling baik dapat memperkenalkan seorang penjair, bukanlah seseorang lainnja. Jang paling baik dapat memperkenalkan seseorang penjair adalah sjair2 penjair itu sendiri! Dan sjair2 Pablo Neruda bukannja tidak terkenal dikalangan pembatja Indonesia. Se-kurang2nja 6 buah sadjaknja — jang pada umumnja pandjang2 — sudah diterdjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Belum lagi esai2nja. Pembatja bisa menilai sendiri kebesaran dan arti Neruda. Lebih2 disaat dunia kita berada dipersimpangan djalan antara keruntuhan dan pembaruan seperti sekarang ini.
Ia dilahirkan di Parral, Chili, pada 12 Djuli 1904. Sedjak tahun 1937 ia terkenal sebagai penjair, sedjak ia mendjulangkan suaranja untuk pahlawan2 republiken di Spanjol. Neruda bukan hanja bergerak dilapangan kesusasteraan, tetapi djuga dilapangan politik, karena ia sedar bahwa haridepan kesusasteraan bangsanja tergantung dari nasib politik negerinja. Di-tahun2 1928-1930 ia mendjabat Duta Chili di Colombo, ditahun 1934 Duta di Barcelona, kemudian ditahun 1935 di Madrid, dan ditahun 1940 di Mixico. Sesudah itu dia tinggal ditanahairnja, aktif sebagai seorang senator, disamping bersadjak.
Diantara sadjak2nja jg. sangat masjhur jalah “Canto General” jang baru diselesaikannja ditahun 1950. Sepandjang hidupnja, demikian juga sadjak2nja, penuh dinafasi semangat kemerdekaan. Salah sebuah sadjaknja jang sangat indah melukiskan kebesaran Simon Bolivar, bapak kemerdekaan Amerika Selatan jang namanja kini abadi didalam sebutan Bolivia. Pablo memang nama Pablo sendiri, tetapi Neruda bukanlah nama-aslinja. Dia demikian kagumnja akan penjair Tjeko, Jan Neruda — seorang penjair besar dan pentjinta kemerdekaan negerinja —, sehingga ia berketetapan untuk mengganti namanja dengan Neruda: Pablo Neruda.
Kaum fasis jang sementara berkuasa dinegerinja mengusir Pablo Neruda keluarnegeri, dan baru ditahun 1952, atas desakan jang kuat dari Rakjat Chili sendiri, pemerintah Chili memperbolehkan Neruda kembali. Selama dipengasingan, Neruda tidak pernah merasa asing, karena ia satu dengan perdjuangan bangsa2 untuk kemerdekaan dan perdamaian. Se-kurang2nja tiga hadiah penting sudah dia terima, jaitu Hadiah Nasional Chili untuk Kesusasteraan (1945), Hadiah Perdamaian Internasional (1950), dan Hadiah Stalin untuk Perdamaian (1953).
Tudjuan hidupnja tersimpul didalam tulisannja “Kepada Inteligensia Amerika Selatan”:
“Kaum intelektuil Amerika Selatan harus bertindak lebih tegap dalam perdjuangan untuk perdamaian. Dalam perdjuangan ini harus dipersatukan hasil2 kebudajaan Rakjat kita jang terbaik dengan harapan dan usaha mereka. Besar pertanggungdjawaban kita. Kaum penghasut perang hendak mentjeburkan kemadjuan kemanusiaan kedalam samodera darah. Dengan djalan perang, mereka hendak memulai suatu masa kebinatangan pembalasan dan pendjadjahan. Kemerdekaan dan masadepan Amerika Selatan mendjadi taruhan. Perdjuangan untuk perdamaian memberikan kepada kita kemungkinan2 baru untuk mentjipta, untuk melindungi tjita2 kita jg. luhur serta nasib benua kita”.
Lusa Pablo Neruda mengindjak usia setengah abad. Tetapi dia sudah abadi, seperti sadjak2nja abadi!
Iramani

Besok, tg. 11 Djuli, akan berkumpul dikota Santiago, Chili, be-ribu2 kalau tidak ber-puluh2ribu Rakjat, diorganisasi oleh sebuah Panitia terdiri dari pengarang dan pemenang Hadiah Seni Nasional, Pedro de la Barra, pendiri Orkestra Simfoni, Armando Carvajal, ketua Parlemen dan novelis, Baltasar Castro, direktur Perpustakaan Universitet Chili, Hector Fuenzalida, pengarang dan direktur Museum Kesenian Rakjat, Tomas Lago, dan banjak lagi. Mereka akan memperingati genap setengah abad umur salah seorang pengarang dan putera Chili, Pablo Neruda.
Jang paling baik dapat memperkenalkan seorang penjair, bukanlah seseorang lainnja. Jang paling baik dapat memperkenalkan seseorang penjair adalah sjair2 penjair itu sendiri! Dan sjair2 Pablo Neruda bukannja tidak terkenal dikalangan pembatja Indonesia. Se-kurang2nja 6 buah sadjaknja — jang pada umumnja pandjang2 — sudah diterdjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Belum lagi esai2nja. Pembatja bisa menilai sendiri kebesaran dan arti Neruda. Lebih2 disaat dunia kita berada dipersimpangan djalan antara keruntuhan dan pembaruan seperti sekarang ini.
Ia dilahirkan di Parral, Chili, pada 12 Djuli 1904. Sedjak tahun 1937 ia terkenal sebagai penjair, sedjak ia mendjulangkan suaranja untuk pahlawan2 republiken di Spanjol. Neruda bukan hanja bergerak dilapangan kesusasteraan, tetapi djuga dilapangan politik, karena ia sedar bahwa haridepan kesusasteraan bangsanja tergantung dari nasib politik negerinja. Di-tahun2 1928-1930 ia mendjabat Duta Chili di Colombo, ditahun 1934 Duta di Barcelona, kemudian ditahun 1935 di Madrid, dan ditahun 1940 di Mixico. Sesudah itu dia tinggal ditanahairnja, aktif sebagai seorang senator, disamping bersadjak.
Diantara sadjak2nja jg. sangat masjhur jalah “Canto General” jang baru diselesaikannja ditahun 1950. Sepandjang hidupnja, demikian juga sadjak2nja, penuh dinafasi semangat kemerdekaan. Salah sebuah sadjaknja jang sangat indah melukiskan kebesaran Simon Bolivar, bapak kemerdekaan Amerika Selatan jang namanja kini abadi didalam sebutan Bolivia. Pablo memang nama Pablo sendiri, tetapi Neruda bukanlah nama-aslinja. Dia demikian kagumnja akan penjair Tjeko, Jan Neruda — seorang penjair besar dan pentjinta kemerdekaan negerinja —, sehingga ia berketetapan untuk mengganti namanja dengan Neruda: Pablo Neruda.
Kaum fasis jang sementara berkuasa dinegerinja mengusir Pablo Neruda keluarnegeri, dan baru ditahun 1952, atas desakan jang kuat dari Rakjat Chili sendiri, pemerintah Chili memperbolehkan Neruda kembali. Selama dipengasingan, Neruda tidak pernah merasa asing, karena ia satu dengan perdjuangan bangsa2 untuk kemerdekaan dan perdamaian. Se-kurang2nja tiga hadiah penting sudah dia terima, jaitu Hadiah Nasional Chili untuk Kesusasteraan (1945), Hadiah Perdamaian Internasional (1950), dan Hadiah Stalin untuk Perdamaian (1953).
Tudjuan hidupnja tersimpul didalam tulisannja “Kepada Inteligensia Amerika Selatan”:
“Kaum intelektuil Amerika Selatan harus bertindak lebih tegap dalam perdjuangan untuk perdamaian. Dalam perdjuangan ini harus dipersatukan hasil2 kebudajaan Rakjat kita jang terbaik dengan harapan dan usaha mereka. Besar pertanggungdjawaban kita. Kaum penghasut perang hendak mentjeburkan kemadjuan kemanusiaan kedalam samodera darah. Dengan djalan perang, mereka hendak memulai suatu masa kebinatangan pembalasan dan pendjadjahan. Kemerdekaan dan masadepan Amerika Selatan mendjadi taruhan. Perdjuangan untuk perdamaian memberikan kepada kita kemungkinan2 baru untuk mentjipta, untuk melindungi tjita2 kita jg. luhur serta nasib benua kita”.
Lusa Pablo Neruda mengindjak usia setengah abad. Tetapi dia sudah abadi, seperti sadjak2nja abadi!
Iramani
Published on April 07, 2016 02:03
July 27, 2015
"Teka-teki Dua Chávez," oleh Gabriel García Márquez
“El enigma de los dos Chávez”, Gabriel García Márquez. Dimuat pertama kali dalam Revista Cambio, Februari 1999. Diterjemahkan dari terbitan ulang untuk memperingati wafatnya Chávez di Revista Anfibia yang diberi judul “El sol de tu bravura”.
Pada 1999, tak lama sebelum Hugo Chávez Frías resmi dilantik sebagai presiden terpilih Venezuela, Gabriel García Márquez mewawancarainya di atas pesawat dalam penerbangan dari Havana ke Caracas. Seraya mereka bercakap, sang Nobelis dari Kolombia itu menjumpai sebuah kepribadian yang tidak cocok dengan gambaran despot yang dibentuk oleh media. Ada dua Chávez. Yang mana yang benar? Inilah profil sang presiden yang masuk militer agar bisa bermain bisbol, yang bisa merapal puisi-puisi Neruda atau Walt Whitman luar kepala, dan yang meninggal kena kanker pada usia 58 tahun.
 Patung lilin García Márquez dan Hugo Chávez di museum di Kuba (foto: Reuters)
Patung lilin García Márquez dan Hugo Chávez di museum di Kuba (foto: Reuters)Presiden Carlos Andrés Pérez turun sore itu dari pesawat yang membawanya balik dari Davos, Swiss, dan terkejut melihat Menteri Pertahanannya, Jenderal Fernando Ochoa Antich, menunggunya di landasan. “Ada apa?” tanyanya penasaran. Pak Menteri meyakinkannya dengan alasan-alasan yang dapat dipercaya agar Presiden tidak pergi ke Istana Miraflores tapi ke kediaman presidensial di La Casona. Ia baru saja jatuh tertidur ketika Menteri Pertahanan yang sama membangunkannya lewat telepon untuk mengabarkan tentang pemberontakan militer di Maracay. Ia baru saja tiba di Miraflores ketika peluru-peluru artileri yang pertama mulai meletus.
Hari itu tanggal 4 Februari 1992. Kolonel Hugo Chávez Frías, seseorang yang menjadikan tanggal-tanggal bersejarah sebagai kultus sakramental, memimpin serangan itu dari pos komando daruratnya di Museo Histórico de La Planicie. Presiden paham bahwa sumber dayanya satu-satunya adalah dukungan rakyat, maka ia pun pergi ke studio Venevisión untuk berbicara kepada seluruh negeri. Dua belas jam kemudian kudeta militer gagal. Chávez menyerah, dengan syarat bahwa ia juga diperbolehkan berbicara ke hadapan rakyat di televisi. Kolonel kreol muda itu, dengan baret pasukan penerjun payung dan kelihaiannya berkata-kata, mengaku bertanggungjawab atas gerakan ini. Pidatonya adalah suatu kemenangan politik. Ia meringkuk dua tahun di penjara sebelum diberi grasi oleh Presiden Rafael Caldera. Banyak pendukungnya dan segelintir musuhnya meyakini bahwa pengakuan publik Chávez adalah pidato pertama dari kampanye pemilu yang akan membuatnya duduk sebagai sebagai presiden republik kurang dari sembilan tahun sesudahnya.
Presiden Hugo Chávez Frías menceritakan kisah ini pada saya dalam pesawat Angkatan Udara Venezuela yang membawa kami dari Havana ke Caracas dua minggu lalu, saat ia masih belum 15 hari terpilih secara konstitusional sebagai presiden Venezuela oleh suara rakyat. Kami diperkenalkan tiga hari sebelumnya di Havana, selama pertemuannya dengan Presiden Castro dan Presiden Pastrana, dan hal pertama yang membuat saya terkesan adalah kekuatan dari tubuh betonnya. Ia memancarkan keramahan seketika dan keluwesan kreol dari seorang Venezuela tulen. Kami mencoba berjumpa lagi satu sama lain, tapi karena tidak ada kesempatan, maka kami pun pergi ke Caracas bersama-sama agar bisa membicarakan hidup dan mukjizat-mukjizatnya di atas pesawat.
Pengalaman bagus bagi seorang reporter yang sedang tirah. Seraya ia bercerita tentang hidupnya, saya mulai mendapati sebuah kepribadian yang tidak pas dengan citra seorang despot yang dibangun oleh media. Ini Chávez yang lain. Yang mana dari keduanya yang sungguhan?
Argumen kuat untuk menentangnya selama masa kampanye lalu adalah masa lalunya belum lama itu sebagai konspirator dan dalang kudeta. Namun demikian sejarah Venezuela sendiri selama bertahun-tahun dipenuhi lebih dari segelintir tokoh macam itu. Awalnya adalah Rómulo Betancourt, yang dikenang dengan tepat maupun keliru sebagai bapak demokrasi Venezuela, yang menggulingkan Isaías Medina Angarita, mantan demokrat militer yang berusaha membersihkan negerinya dari 36 tahun pemerintahan Juan Vicente Gómez. Penerus Betancourt, sang novelis Rómulo Gallegos, dijatuhkan oleh Jenderal Marcos Pérez Jiménez, yang terus berkuasa di Caracas selama hampir 11 tahun. Ia, pada gilirannya, digulingkan oleh satu angkatan demokrat muda yang mengawali babak terpanjang presiden-presiden terpilih hingga saat ini.
Kudeta Februari itu sepertinya merupakan satu-satunya hal yang pernah berjalan tidak beres bagi Kolonel Hugo Chávez Frías. Namun demikian, ia memandangnya secara positif sebagai rintangan takdir. Itulah caranya untuk memahami nasib baik, kecerdasan, intuisi, kecerdikan, atau apapun hembusan gaib yang membimbing tindak-tanduknya sejak lahir ke dunia ini di Sabaneta, negara bagian Barinas, pada 28 Juli 1954, di bawah rasi bintang kekuasaan: Leo. Chávez, seorang Katolik yang taat, mengaitkan nasib baiknya dengan skapular berusia lebih dari 100 tahun yang ia bawa-bawa sejak kecil, warisan kakek buyutnya dari pihak ibu, Kolonel Pedro Pérez Delgado, salah seorang pahlawan panutannya.
Orang tuanya bertahan hidup pas-pasan dengan gaji guru SD, dan sejak umur 9 tahun ia harus membantu mereka berjualan manisan dan buah-buahan dengan gerobak dorong. Kadang dengan keledai ia pergi mengunjungi neneknya dari pihak ibu di Los Rastrojos, desa tetangga yang terasa bagai kota besar untuk ukuran mereka, sebab punya pembangkit listrik kecil yang memberi dua jam cahaya penerang saat malam tiba dan seorang bidan yang membantu datangnya Chávez serta keempat saudaranya ke dunia ini. Ibunya ingin dia jadi pastor, tapi ia cuma sanggup sampai jadi putra altar dan ia biasa memainkan lonceng dengan keindahan begitu rupa sampai-sampai semua orang tahu denting khasnya. “Itu Hugo yang main,” kata mereka. Di antara buku-buku ibunya ia menemukan sebuah ensiklopedia, yang bab pertamanya langsung memukaunya: Cara menggapai sukses dalam hidup.
Bab itu berisi sederet pilihan, dan ia sudah menjajal nyaris semuanya. Sebagai pelukis ia takjub menghadapi lembar-lembar cetakan karya-karya Michelangelo dan patung Daud, dan pada umur 12 tahun memenangkan hadiah pertama dalam pameran setempat. Sebagai musisi kehadirannya tak terlewatkan di pesta-pesta ulang tahun dan serenade berkat kepiawaiannya bermain cuatro (gitar kecil) dan suaranya yang merdu. Sebagai pemain bisbol ia menjadi penangkap unggulan. Opsi jadi militer tak ada dalam daftar tersebut, dan juga tak terpikir olehnya, sampai ia diberitahu bahwa cara terbaik untuk masuk ke liga besar bisbol adalah dengan mendaftar ke akademi militer di Barinas. Pasti merupakan mukjizat lain dari skapularnya, sebab pada hari itu rencana yang dirintis oleh Andrés Bello dimulai, yang membolehkan lulusan sekolah militer untuk mencapai gelar akademik tertinggi.
Ia mempelajari ilmu politik, sejarah, dan Marxisme-Leninisme. Ia suka mempelajari hayat dan karya Bolívar, yang terbesar di antara para “Leo”, yang proklamasinya ia hafal luar kepala. Namun konflik pertamanya yang ia alami secara sadar dengan politik riil berlangsung dengan tewasnya Allende pada September 1973. Chávez tidak mengerti. Bila rakyat Cile memilih Allende, mengapa militer Cile kini melancarkan kudeta? Tak lama sesudahnya, kapten kompinya menugaskannya mengawasi salah seorang anak José Vicente Rangel, yang diyakini sebagai seorang komunis. “Benar-benar lika-liku kehidupan,” Chávez memberitahu saya diiringi derai tawanya. “Sekarang ayah dia jadi menteriku.” Lebih ironis lagi adalah ketika Chávez lulus, ia menerima pedangnya dari presiden yang bakal coba ia gulingkan 20 tahun sesudahnya: Carlos Andrés Pérez.
“Lebih dari itu,” kata saya, “kau mencoba membunuhnya.” “Sama sekali tidak,” Chávez memprotes. “Idenya adalah untuk mendirikan majelis konstituen lalu kembali ke barak.” Sejak kesempatan pertama itu saya sadar bahwa ia memang seorang pendongeng alami. Ia adalah produk budaya rakyat Venezuela, kreatif dan riang gembira. Ia punya pemahaman yang hebat soal manajemen waktu serta ingatan yang nyaris supranatural, yang memungkinkannya merapal luar kepala puisi-puisi Neruda dan Whitman, dan berhalaman-halaman utuh karya Rómulo Gallegos.
Pada usia muda ia mendapati secara kebetulan bahwa kakek buyutnya bukanlah seorang pembunuh dari dunia khayal, sebagaimana yang diceritakan ibunya, melainkan seorang pejuang legendaris pada era Juan Vicente Gómez [tokoh militer Venezuela dari 1908 hingga 1935 —terjmh.]. Sedemikian besar antusiasme Chávez sampai-sampai ia memutuskan untuk menulis buku guna menjernihkan kenangan atas pria itu. Ia menggali arsip-arsip sejarah dan perpustakaan-perpustakaan militer, dan pergi dari kota ke kota memakai ransel sejarawan untuk menapaktilas perjalanan kakek buyutnya melalui kesaksian-kesaksian orang-orang yang ditinggalkannya. Pada kisaran waktu inilah ia memasukkan kakek buyutnya ke dalam altar para pahlawannya dan mulai mengenakan skapular pelindung yang dulu dimiliki kakeknya itu.
Suatu hari ia melintasi perbatasan secara tidak sengaja di jembatan Arauca, dan kapten dari Kolombia yang memeriksa ranselnya menemukan bukti-bukti untuk menuduhnya sebagai mata-mata: ia membawa kamera foto, alat perekam, surat-surat rahasia, foto-foto kawasan itu, peta militer bergambar-gambar serta dua pistol wajib. Tanda pengenalnya, sebagaimana bisa diharapkan dari seorang mata-mata, bisa saja palsu. Tarik ulur berlangsung berjam-jam di kantor yang gambar satu-satunya yang dipajang hanyalah potret Bolívar berkuda. “Aku sudah nyaris angkat tangan,” Chávez bercerita, “sebab semakin aku menjelaskan semakin dia tidak mengerti.” Sampai kalimat penyelamatnya tercetus: “Lihatlah hidup ini, kapten: tak sampai seabad lalu kita bagian dari tentara yang sama, dan orang yang memandangi kita dari gambar ini adalah bos kita berdua. Bagaimana aku bisa jadi mata-mata?” Terenyuh, si kapten mulai bicara melantur perihal Gran Colombia (Kolombia Raya), dan keduanya menutup malam itu dengan minum bir dari kedua negara di sebuah kedai di Arauca. Pagi harinya, sama-sama pusing kepala, si kapten mengembalikan kepada Chávez piranti sejarawannya dan berpamitan dengan memeluknya di tengah-tengah jembatan lintas-negara itu.
“Pada saat itulah aku mendapat bayangan konkret bahwa ada yang tidak beres di Venezuela,” kata Chávez. Ia dikirim ke timur sebagai komandan regu berisi 13 orang prajurit serta tim komunikasi untuk menghabisi basis-basis gerilya yang tersisa. Pada suatu malam yang berhujan lebat, datanglah mencari perlindungan di kampnya seorang intel kolonel beserta sepasukan tentara dan beberapa orang terduga gerilyawan yang baru ditangkap, dengan kulit kurus kering dan nyaris kehijauan. Sekitar pukul 10 malam, saat Chávez baru saja mau tidur, ia dengar jeritan melengking dari ruang sebelah. “Tentara menggebuki tahanan mereka dengan tongkat bisbol yang dibungkus kain gombal agar tidak meninggalkan bekas-bekas,” kata Chávez. Naik pitam, ia menuntut agar kolonel tersebut menyerahkan para tahanannya atau pergi dari situ, karena ia tidak bisa membiarkan ada orang disiksa di bawah komandonya. “Esok harinya aku diancam dikenai pengadilan militer karena pembangkangan,” kenang Chávez, “tapi mereka cuma menempatkanku sesaat dalam pengawasan.”
Sekian hari sesudahnya ia mendapatkan pengalaman yang melampaui pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ia sedang membeli daging untuk pasukannya ketika sebuah helikopter militer mendarat di lapangan barak bermuatan para prajurit yang terluka parah dalam sergapan gerilya. Chávez memapah seorang prajurit yang badannya kena beberapa tembakan. “Jangan biarkan aku mati, letnan...” kata prajurit itu ketakutan. Ia cuma berhasil memasukkannya ke mobil. Tujuh lainnya tewas. Malam itu, terjaga di tempat tidur gantung, Chávez merenung: “Buat apa aku di sini? Di satu sisi orang tani berseragam tentara menyiksa para tani gerilya dan di sisi lain petani gerilya membunuhi orang tani yang berseragam hijau-hijau. Di titik ini, ketika perang usai, tak masuk akal untuk menembak siapapun.” Dan ia memungkas dalam pesawat yang membawa kami ke Caracas: “Di situlah aku jatuh dalam konflik eksistensialku yang pertama.”
Esok harinya ia bangun dengan keyakinan bahwa sudah menjadi takdirnya untuk mendirikan sebuah gerakan. Pada umur 23 tahun ia melakukannya, di bawah nama yang tanpa tedeng aling-aling: Tentara Bolívarian Rakyat Venezuela. Para anggota pendirinya: lima orang prajurit beserta dirinya, yang berpangkat letnan muda. “Apa tujuannya?” saya bertanya. Sederhana saja, ujarnya: “Tujuannya adalah untuk bersiap kalau-kalau terjadi sesuatu.” Setahun kemudian, sebagai perwira pasukan terjun payung di batalion bersenjata Maracay, ia mulai merancang persekongkolan besar. Tapi pada saya ia jelaskan bahwa ia memakai kata persekongkolan hanya dalam arti kiasan menyatukan tekad untuk menjalankan kewajiban bersama.
Demikianlah situasinya pada 17 Desember 1982 manakala sebuah peristiwa yang tak terduga berlangsung yang menurut Chávez sangat menentukan dalam hidupnya. Ia sudah menjadi kapten dalam resimen terjun payung kedua, serta ajudan perwira intelijen. Sama sekali tak disangka-sangka, komandan resimen, Ángel Manrique, menugaskannya berpidato di hadapan 1.200 orang dari segala kepangkatan.
Pukul satu siang, batalion berkumpul di lapangan bola, dan pembawa acara memperkenalkan Chávez. “Dan pidatonya?” tanya komandan resimen yang melihatnya naik ke panggung tanpa membawa kertas. “Saya tak punya pidato tertulis,” Chávez memberitahunya. Dan ia pun mulai berimprovisasi. Itu pidato yang cukup singkat, diilhami oleh Bolívar dan Martí, tapi dengan tuaian pribadi mengenai kondisi tertekan dan ketidakadilan di Amerika Latin 200 tahun sesudah merdeka. Para perwira, baik yang mendukungnya maupun tidak, menyimaknya tanpa tergerak. Di antara mereka terdapat Kapten Felipe Acosta Carle dan Kapten Jesús Urdaneta Hernández yang bersimpati pada gerakannya. Komandan garnisun, yang sangat kecewa, menerima Chávez seusai pidato dengan dampratan yang bisa terdengar oleh semua orang:
“Chávez, bicaramu seperti politisi.” “Siap,” jawab Chávez.
Felipe Acosta, dengan tinggi dua meter dan perawakan pantang menyerah, menghadap komandan dan berkata: “Anda keliru, komandan. Chávez bukan politisi. Ia kapten zaman kita, dan kalau Anda mendengar apa yang dibilangnya dalam pidato, Anda akan terkencing-kencing di celana.”
Kolonel Manrique menyuruh para prajurit bersiap dan berkata, “Aku ingin kalian tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Kapten Chávez sudah seizinku. Aku yang memerintahkannya berpidato dan segala yang ia sampaikan, sekalipun tidak ditulisnya, sudah ia sampaikan padaku kemarin.” Ia diam sejenak untuk memberi efek dramatis, dan menyimpulkan dengan perintah penutup: “Tentang ini tidak boleh tersiar keluar!”
Di akhir acara, Chávez berlari-lari sore bersama Kapten Felipe Acosta dan Kapten Jesús Urdaneta ke Samán del Guere, sekitar 10 km jauhnya, dan mengulang sumpah khidmat yang sama yang diikrarkan oleh Simón Bolívar di Monte Aventino. “Pada akhirnya, jelas, aku membuat perubahan,” kata Chávez. Alih-alih “ketika kita telah mematahkan belenggu yang menindas kita oleh tekad kekuasaan Spanyol”, mereka bersumpah “sampai kita memutus belenggu yang menindas kita dan menindas rakyat oleh tekad kaum berkuasa.”
Sejak itu, semua perwira yang bergabung dalam gerakan bawah tanah itu harus mengucapkan sumpah tersebut. Yang paling belakangan adalah ketika kampanye pemilu di hadapan ratusan ribu orang. Selama bertahun-tahun rapat-rapat rahasia dengan jumlah peserta yang terus membesar berlangsung, termasuk wakil-wakil militer dari sepenjuru negeri. “Selama dua hari rapat berlangsung di tempat-tempat tersembunyi, untuk mempelajari situasi negeri, menganalisa, dan menjalin kontak-kontak dengan kelompok-kelompok dan kawan-kawan sipil.” “Dalam sepuluh tahun,” kata Chávez pada saya, “kami menggelar lima kongres tanpa ketahuan.”
Pada titik obrolan ini, Presiden tertawa culas, dan mengungkap sesuatu dengan senyum licin: “Kami selalu bilang bahwa mula-mulanya adalah kami bertiga. Tapi kini kami bisa bilang bahwa sesungguhnya kami punya orang keempat, yang identitasnya selalu kami rahasiakan untuk melindunginya, yang tidak ketahuan pada 4 Februari, yang tetap aktif di tentara dan mencapai pangkat kolonel. Tapi ini sudah tahun 1999 dan kami bisa mengungkap bahwa orang keempat itu ada bersama kita di pesawat ini.” Ia tudingkan telunjuknya ke arah seorang pria yang duduk terpisah di kursi dekat situ dan berkata: “Itu dia, Kolonel Badull!”
Sejalan dengan ide yang dimiliki oleh comandante Chávez tentang hidupnya, peristiwa puncaknya adalah El Caracazo, perlawanan rakyat yang meluluhlantakkan Caracas. Ia suka mengulangi: “Napoleon berkata bahwa pertempuran ditentukan pada detik inspirasi strategis.” Dari pemikiran tersebut, Chávez mengembangkan tiga konsep: Pertama, jam historis. Kemudian, menit strategis. Dan terakhir, detik taktis. “Kami khawatir sebab kami tidak mau meninggalkan ketentaraan,” kata Chávez. “Kami telah membentuk gerakan, tapi belum jelas untuk apa.” Namun demikian, drama riil yang bakal terjadi ternyata benar-benar terjadi dan mereka tidak siap. “Dengan kata lain,” Chávez memungkas, “kami dibuat terkejut oleh menit strategis.”
Yang ia maksud, tentu saja, adalah pemberontakan rakyat pada 27 Februari 1989: El Caracazo. Tak ada yang lebih terkejut oleh kejadian itu selain Chávez sendiri. Carlos Andrés Pérez baru saja menaiki takhta kepresidenan sesudah menang telak dan tak terpikirkan bahwa sesuatu yang sedemikian serius akan terjadi hanya dalam waktu 20 hari. “Jadi, aku tengah menuju universitas untuk studi pascasarjanaku, pada malam tanggal 27 itu, dan aku pergi ke pangkalan Tiuna mencari teman yang bisa meminjamiku bensin untuk pulang ke rumah,” Chávez memberitahu saya beberapa menit sebelum mendarat di Caracas. “Lalu aku melihat pasukan dikumpulkan, dan aku pun bertanya ke seorang kolonel: Mau ke mana semua tentara ini? Mengapa mereka menugaskan seksi logistik yang tidak terlatih bertempur, apalagi pertempuran jalanan? Oleh senapannya sendiri saja para rekrutan ini takut. Jadi aku bertanya ke kolonel: Mau ke mana mereka? Dan kolonel itu menjawab: Ke jalan, ke jalan. Ada perintah begini: hentikan kerusuhan ini, apapun itu, jadi ya ke sanalah kita. Ya Tuhan, perintah macam apa itu? Begini Chávez, balas si kolonel: perintahnya adalah menghentikan keributan ini, apapun itu. Aku pun membalas: Tapi kolonel, Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Dan ia membalas lagi: Chávez, ini perintah dan tak ada yang diperbuat soal itu. Sekarang berserah ke tangan Tuhan saja.”
Chávez bercerita bahwa ia sedang demam waktu itu kena serangan rubela, dan saat menyalakan mobil ia melihat seorang prajurit kecil datang berlarian dengan helm copot, senapan menggelantung, dan amunisi bertebaran. “Kuhentikan dan kuteriaki dia,” kata Chávez. “Dan ia mendekat, gugup, berkeringat, bocah baru 18 tahun. Aku pun bertanya: Hai, kau mau ke mana, lari-lari seperti itu? Tidak, katanya, saya ditinggal oleh peleton saya, dan itu letnan saya naik truk! Bawa saya pergi, pak, bawa saya pergi. Aku dekati truk itu dan bertanya pada yang bertugas: Kalian mau ke mana? Dan ia jawab: saya tak tahu apa-apa. Tak ada yang tahu apa-apa, coba bayangkan.” Chávez menghela nafas dan nyaris berteriak, larut dalam derita malam yang mengerikan itu. “Kau tahu, bila kau mengirim prajurit yang ketakutan ke jalanan dengan senapan dan lima ratus selongsong peluru, akan mereka habiskan semuanya. Mereka sapu jalanan dengan peluru, sapu perbukitan, kampung-kampung kelas buruh. Ini bencana! Yang mati: ribuan, termasuk Felipe Acosta. Dan firasatku berkata ia memang sengaja dibunuh,” kata Chávez. “Itulah menit yang kami nanti, menit untuk bertindak.” Kata seiya dengan perbuatan: dari situlah ia mulai merencanakan kudeta yang akan gagal tiga tahun sesudahnya.
Pesawat mendarat di Caracas pukul tiga dini hari. Lewat jendela saya saksikan rawa-rawa lampu dari kota tak terlupakan tempat saya tinggal selama tiga tahun, yang penting bagi Venezuela dan kini juga bagi hidup saya sendiri. Pak Presiden berpamitan dengan pelukan Karibianya dan undangan tersirat: “Kita ketemu lagi di sini tanggal 2 Februari.” Saat ia berjalan menjauh diapit oleh pengawal militer dan teman-teman dari masa-masa awal gerakannya, terbersit pada saya bahwa saya telah pergi dan mengobrol asyik dengan dua orang yang bertentangan. Yang satu adalah orang yang telah diberi peluang oleh nasib untuk menyelamatkan negerinya. Dan yang lain, seorang ilusionis, yang bisa tercatat dalam sejarah cuma sebagai seorang despot lainnya.
Published on July 27, 2015 21:38
April 12, 2015
"Salju," oleh Julia Álvarez
"Salju" karya Julia Álvarez, dalam antologi cerita sangat pendek Amerika Latin yang saya susun, Matinya Burung-burung (Moka Media, 2015) hlm. 106 mengalami kesalahan cetak yang cukup fatal karena terpotong tak selesai. Pemuatan di blog ini sebagai koreksi sekaligus permintaan maaf kepada pembaca.
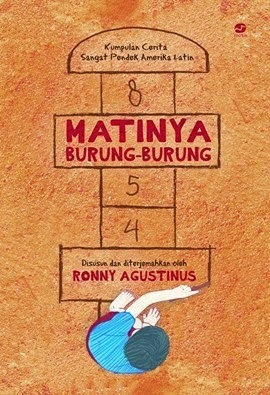 Tahun pertama di New York kami menyewa apartemen kecil dekat sebuah sekolah Katolik yang diasuh oleh suster-suster Karitas, para perempuan kekar dengan gaun hitam panjang dan kap rambut yang membuat mereka terlihat khas, seperti boneka sedang berkabung. Aku suka sekali mereka, terutama guru kelas empatku yang seperti nenek sendiri, Suster Zoe. Aku punya nama yang indah, katanya, dan ia menyuruhku mengajari seisi kelas cara melafalkannya. Yo-lan-da. Sebagai satu-satunya imigran di kelas, aku didudukkan di bangku spesial baris depan dekat jendela, terpisah dari anak-anak lain agar Suster Zoe bisa mengajariku secara khusus tanpa mengganggu mereka. Perlahan-lahan ia mengeja rangkaian kata-kata baru yang harus kuulangi: mesin cuci, keripik jagung, kereta bawah tanah, salju.Dengan lekas aku menguasai cukup bahasa Inggris untuk bisa mengerti bahwa bencana sedang menjelang. Kepada seisi kelas yang terbelalak Suster Zoe menjelaskan apa yang tengah berlangsung di Kuba. Peluru-peluru kendali sedang dirakit, konon diarahkan ke kota New York. Presiden Kennedy, yang juga terlihat khawatir, muncul di televisi di rumah, menjelaskan bahwa kita sepertinya perlu berperang melawan Komunis. Di sekolah, kami berlatih serangan udara: bel yang menakutkan akan berbunyi dan kami pun berbaris tiarap menuju aula, menudungi kepala dengan mantel, dan membayangkan rambut kami rontok, tulang-tulang di tangan kami melunak. Di rumah, Mami dan aku serta saudara-saudara perempuanku berdoa rosario untuk perdamaian dunia. Aku mendengar kosakata baru: bom nuklir, debu radioaktif, benteng perlindungan.Suster Zoe menjelaskan kejadiannya. Ia menggambar jamur di papan tulis dan membuat titik-titik kapur acak-acakan untuk debu yang akan membunuh kami semua.Bulan demi bulan bertambah dingin, November, Desember. Hari gelap saat aku bangun di pagi hari, membeku saat aku mengikuti hembus nafasku ke sekolah. Suatu pagi saat duduk di bangku melamun menghadap keluar jendela, kulihat bintik-bintik di udara seperti yang digambar Suster Zoe, awalnya jarang-jarang, lalu banyak dan banyak. Aku memekik, “Bom! Bom!” Suster Zoe tersentak, rok hitam panjangnya menggembung saat ia terbirit-birit ke arahku. Beberapa anak perempuan mulai menangis.Tapi lantas raut terkejut Suster Zoe sirna. “Ampun, Yolanda sayang, itu salju!” Ia tertawa. “Salju.”“Salju,” aku ulangi. Aku memandang keluar jendela dengan hati-hati. Seumur hidup aku sudah mendengar soal kristal-kristal putih yang menghujani langit Amerika di musim dingin. Dari bangkuku aku melihat debu halus itu menyalut trotoar dan mobil-mobil yang diparkir di bawah. Tiap kepingnya berbeda, kata Suster Zoe, seperti manusia, indah dan tak tergantikan.
Tahun pertama di New York kami menyewa apartemen kecil dekat sebuah sekolah Katolik yang diasuh oleh suster-suster Karitas, para perempuan kekar dengan gaun hitam panjang dan kap rambut yang membuat mereka terlihat khas, seperti boneka sedang berkabung. Aku suka sekali mereka, terutama guru kelas empatku yang seperti nenek sendiri, Suster Zoe. Aku punya nama yang indah, katanya, dan ia menyuruhku mengajari seisi kelas cara melafalkannya. Yo-lan-da. Sebagai satu-satunya imigran di kelas, aku didudukkan di bangku spesial baris depan dekat jendela, terpisah dari anak-anak lain agar Suster Zoe bisa mengajariku secara khusus tanpa mengganggu mereka. Perlahan-lahan ia mengeja rangkaian kata-kata baru yang harus kuulangi: mesin cuci, keripik jagung, kereta bawah tanah, salju.Dengan lekas aku menguasai cukup bahasa Inggris untuk bisa mengerti bahwa bencana sedang menjelang. Kepada seisi kelas yang terbelalak Suster Zoe menjelaskan apa yang tengah berlangsung di Kuba. Peluru-peluru kendali sedang dirakit, konon diarahkan ke kota New York. Presiden Kennedy, yang juga terlihat khawatir, muncul di televisi di rumah, menjelaskan bahwa kita sepertinya perlu berperang melawan Komunis. Di sekolah, kami berlatih serangan udara: bel yang menakutkan akan berbunyi dan kami pun berbaris tiarap menuju aula, menudungi kepala dengan mantel, dan membayangkan rambut kami rontok, tulang-tulang di tangan kami melunak. Di rumah, Mami dan aku serta saudara-saudara perempuanku berdoa rosario untuk perdamaian dunia. Aku mendengar kosakata baru: bom nuklir, debu radioaktif, benteng perlindungan.Suster Zoe menjelaskan kejadiannya. Ia menggambar jamur di papan tulis dan membuat titik-titik kapur acak-acakan untuk debu yang akan membunuh kami semua.Bulan demi bulan bertambah dingin, November, Desember. Hari gelap saat aku bangun di pagi hari, membeku saat aku mengikuti hembus nafasku ke sekolah. Suatu pagi saat duduk di bangku melamun menghadap keluar jendela, kulihat bintik-bintik di udara seperti yang digambar Suster Zoe, awalnya jarang-jarang, lalu banyak dan banyak. Aku memekik, “Bom! Bom!” Suster Zoe tersentak, rok hitam panjangnya menggembung saat ia terbirit-birit ke arahku. Beberapa anak perempuan mulai menangis.Tapi lantas raut terkejut Suster Zoe sirna. “Ampun, Yolanda sayang, itu salju!” Ia tertawa. “Salju.”“Salju,” aku ulangi. Aku memandang keluar jendela dengan hati-hati. Seumur hidup aku sudah mendengar soal kristal-kristal putih yang menghujani langit Amerika di musim dingin. Dari bangkuku aku melihat debu halus itu menyalut trotoar dan mobil-mobil yang diparkir di bawah. Tiap kepingnya berbeda, kata Suster Zoe, seperti manusia, indah dan tak tergantikan.
Published on April 12, 2015 21:15
March 7, 2015
Pengantar yang Tak Seberapa Pendek untuk Kumpulan Cerita Sangat Pendek
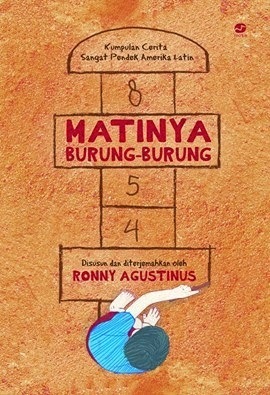 Pengantar untuk kumpulan cerita sangat pendek Amerika Latin, Matinya Burung-burung, yang akan diterbitkan oleh Moka Media
Pengantar untuk kumpulan cerita sangat pendek Amerika Latin, Matinya Burung-burung, yang akan diterbitkan oleh Moka MediaGenre cerita sangat pendek, dengan pelbagai macam varian dan istilahnya, tampaknya makin populer belakangan ini. Mengutip beberapa contoh dari Indonesia saja kita bisa menyebut, misalnya, komunitas Fiksimini yang sebagian anggotanya telah menerbitkan kumpulan Cemburu itu Peluru (2011) dan Dunia di Dalam Mata (2013); para penulis blog 100kata yang juga telah menerbitkan kumpulan 100Kata: Kumpulan Cerita 100 Kata (2009); pasangan penulis Primadonna Angela dan Isman H. Suryaman yang telah menerbitkan Flash Fiction: Jangan Berkedip! (2006); juga komunitas Fiksimini Basa Sunda yang khusus menulis cerita sangat pendek dalam bahasa Sunda. Belum lagi para cerpenis yang lebih “konvensional“ yang juga memasukkan satu atau dua cerita sangat pendek dalam buku kumpulan cerpennya.
Popularitas ini oleh sebagian pengamat dipulangkan pada perubahan sosial dan teknologi yang memengaruhi cara kita membaca. Padatnya kehidupan sehari-hari membuat waktu membaca makin terjepit, yang pada gilirannya berdampak pada cara kita menulis.Sinyalemen yang mengaitkan perkembangan teknologi informasi dengan genre cerita sangat pendek tersebut tentu ada benarnya. Komunitas Fiksimini misalnya, bermula di jagat twitter, dan dengan itu memakai batasan 140 karakter yang diberikan oleh media sosial tersebut sebagai ciri khas ekspresinya. Kita bisa mencari perbandingannya misalnya dalam genre keitai shosetsu (“sastra ponsel”) di Jepang, yakni cerita sangat pendek yang harus muat dalam pesan singkat (sms) di ponsel.Kendati demikian, mengaitkan genre ini semata-mata dengan teknologi jelas keliru, karena sepanjang sejarah, bentuk-bentuk cerita sangat pendek telah dikenal di pelbagai belahan dunia jauh sebelum era merebaknya teknologi informasi. Fabel-fabel Aesop dari zaman Yunani kuno misalnya, jelas bisa kita golongkan ke dalam genre ini. Jepang mengenal haibun sejak abad ke-17,Amerika Latin adalah wilayah tempat cerita sangat pendek bertumbuh paling subur dalam kesusastraan modernnya, kendati dunia mungkin lebih mengenal sastra Amerika Latin dalam bentuk novel-novel panjang. Cerita-cerita sangat pendek sudah bisa kita dapati sejak awal abad ke-20 meski saat itu belum dikenal sebagai genre atau subgenre tersendiri, misalnya pada Ensayos y poemas (1917) karya Julio Torri; El plano oblicuo (1920) karya Alfonso Reyes; dan La torre de Timón (1925) karya José Antonio Ramos Sucre (Torri dan Reyes berasal dari Meksiko, sedangkan Ramos Sucre dari Venezuela). Pada Juni 1939 Edmundo Valadés bersama Horacio Quiñones mendirikan majalah cerpen El Cuento yang konsisten mendorong pemuatan karya-karya microficción di samping cerpen konvensional.Memasuki pertengahan abad ke-20 kita dapati karya-karya yang sepenuhnya memuat cerita-cerita sangat pendek, misalnya Varia invención (1949), Confabulario (1952), dan Bestiario (1959) karya Juan José Arreola dari Meksiko; Obras completas y otros cuentos (1959) dan La oveja negra y demás fábulas (1969) karya Augusto Monterroso dari Guatemala; Historias de Cronopios y de Famas (1962) karya Julio Cortázar dari Argentina. Karya-karya ini kini menjadi bacaan wajib bagi para pengkaji sastra Amerika Latin. Selain itu, para penulis tersohor Amerika Latin lainnya seperti Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Elena Poniatowska, dll pada satu atau lebih kesempatan juga pernah menjajal kemampuan mereka mengolah cerita sangat pendek.
Dengan demikian jelas bahwa secara historis, cerita sangat pendek mempunyai kedudukannya tersendiri dalam khazanah sastra Amerika Latin yang bukan melulu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Cerita sangat pendek Amerika Latin terus ditulis dan dibukukan hingga kini, dan beberapa penulis kontemporer seperti Raúl Brasca dan Ana María Shua (keduanya dari Argentina) mengkhususkan diri mendalami genre ini. Cerita sangat pendek Amerika Latin juga terus dibahas, dibedah, dan dianalisa. Pelbagai kajian akademik telah dilahirkanAhli sastra yang berbeda memakai pendekatan yang berbeda pula untuk menilai dan memilah-milah jenis-jenis cerita sangat pendek Amerika Latin. Pengantar ini bukan tempatnya untuk menguraikan seluruh diskusi tentang genre ini. Saya hanya ingin menyitir sedikit tipologi sederhana yang dijabarkan oleh akademisi sastra dari Meksiko Lauro Zavala.
Dalam bukunya, Zavala mendefinisikan minificción sebagai “narasi yang muat dalam satu halaman.”Memakai tipologi Zavala, maka yang dimaksud cerita sangat pendek dalam antologi ini adalah yang kurang dari 1.000 kata (el cuento muy corto dan el cuento ultracorto). Kebanyakan cerita jauh di bawah batas tersebut; satu-satunya yang paling mendekati (900 kata) hanyalah “Hantu-hantu Agustus” karya Gabriel García Márquez (hlm. 79).
Melalui antologi ini saya tak bermaksud mengklaim telah menghadirkan representasi utuh dari genre cerita sangat pendek Amerika Latin. Butuh penelitian jauh lebih lama dan wawasan jauh lebih luas untuk bisa menghadirkan antologi semacam itu. Kesulitan utama jelas adalah melacak buku-buku lama (terbit sebelum 1960an) yang sudah tidak dicetak lagi dan karenanya langka, serta memperoleh terbitan-terbitan sangat baru (katakanlah, sepuluh tahun ke belakang) yang belum dijual buku bekasnya dan oleh karenanya mahal. Maka sebab itulah, mayoritas cerita di buku ini berkisar pada kurun waktu 1960-2000an awal.
Tapi terlepas dari kekurangan tersebut, paling tidak antologi ini bisa memberi pembaca gambaran awal tentang keragaman bentuk dan tema (atau juga berulangnya motif-motif tertentu) dalam cerita sangat pendek Amerika Latin. Karya-karya yang dianggap “kanonik” dalam genre ini dan selalu menjadi bahan ulasan dalam kajian sastra Amerika Latin saya sertakan semua, semisal “Taman Sambung-Menyambung” karya Cortázar (hlm. 94) atau “Gerhana” (hlm. 21) dan “Dinosaurus” (hlm. 23) karya Monterroso.Demikian juga, yang dimuat dalam antologi ini adalah cerita-cerita sangat pendek yang memang ditulis dan dimaksudkan sebagai cerita sangat pendek, dan bukan kutipan atau potongan semena-mena dari cerita atau tulisan lain yang lebih panjang tapi diklaim sebagai cerita sangat pendek. Yang demikian ini banyak kita dapati di era internet ini, di mana kemudahan untuk berbagi informasi sering tidak diikuti oleh ketelitian dan ketekunan dalam verifikasinya. Semisal cerita berikut ini yang konon berjudul “El adivino” (“Peramal”). Cerita ini bisa dengan mudah ditemui di internet dan disebut-sebut sebagai fiksi mini karya Jorge Luis Borges:
Di Sumatera, seseorang sedang mempertahankan disertasi doktoralnya di bidang ramal-meramal. Si dukun penguji bertanya padanya apakah ia akan gagal atau lulus. Si kandidat doktor menjawab ia akan gagal…
Sekalipun benar Borges yang menulisnya, tapi ini sebenarnya adalah kutipan kecil saja dari ulasan Borges atas buku Edward Kasner dan James Newman, Mathematics and the Imagination, yang dimuat dalam buku Borges Discusión (1932), dan tidak dimaksudkan sebagai cerita yang berdiri sendiri. Maka yang sejenis ini tidak mendapat tempat di buku ini. Perkecualian dibuat di sini untuk “Salju” karya Julia Álvarez (hlm. 84). Cerita ini memang merupakan salah satu bab dalam novelnya yang lebih panjang, tapi sebelum itu, ia terbit terlebih dahulu secara mandiri sebagai cerita sangat pendek dan dimuat ulang dalam beberapa antologi cerpen sebelum akhirnya dicakupkan ke dalam novel.
Untuk melengkapi pembacaan, biodata ringkas para pengarang dan sumber karya dituliskan di penutup buku ini. Akhir kata, selamat berpendek-pendek!
Serpong, November 2014
Lihat, misalnya, pandangan Damhuri Muhammad dalam “Cerita Minikata, Kata Tipis Makna?”, paparannya pada diskusi buku 100Kata: Kumpulan Cerita 100 Kata, Aksara Bookstore, Jakarta, 29 November 2009: “...peminat, atau mungkin layak disebut “pecandu” sastra –utamanya puisi dan prosa—yang sebagian besar adalah mereka yang setiap hari disesaki oleh kesibukan-kesibukan pekerjaan yang menyita waktu, malah lebih gandrung dengan keringkasan, kelugasan, dan ketegasan dalam merangkai kisah.” Pendapat senada diungkapkan oleh novelis Irlandia Julian Gough: “Generasiku, dan yang lebih muda, mencerap informasi bukan dalam satuan-satuan panjang, utuh, koheren (film, album, novel), tapi dalam letupan-letupan singkat, dengan nada yang amat berbeda-beda. (Pindah-pindah saluran teve, menelusuri internet sambil memain-mainkan iPod.) Itu mengubah cara kita membaca fiksi, dan karenanya pasti mengubah cara kita menuliskannya.” Lihat dalam Aleksandar Hemon (ed.), Best European Fiction 2010 (Illinois: Dalkey Archive Press, 2009), hlm. 374–375. Sebenarnya keitai shosetsu memuat juga novel panjang dalam format cerita bersambung melalui pesan singkat. Pada 2007, separuh dari 10 buku fiksi paling laris di Jepang berasal dari sastra ponsel ini. Lihat Barry Yourgrau, “Thumb novels: Mobile phone fiction,” The Independent, 29 Juli 2009. Haruo Shirane, Early Modern Japanese Literature: An Anthology, 1600–1900 (New York: Columbia University Press, 2008), hlm. 99. Holly Howitt-Dring, “Making micro meanings: reading and writing microfiction,” Short Fiction in Theory and Practice 1:1 (2011), hlm. 48. Pada 2014, untuk memperingati 75 tahun El Cuento diluncurkan buku kumpulan cerita sangat pendek Minificcionistas de El Cuento. Revista de imaginación, yang disusun oleh Alfonso Pedraza, berisi karya 103 penulis dari 12 negara. Sejak 1980, El Cuento juga merintis pemberian anugerah sastra bagi genre ini. Lihat, antara lain:- Dolores M. Koch, “El micro-relato en México: Torri, Arreola y Monterroso,” disertasi doktoral, City University of New York, 1987.- Concepción del Valle Pedrosa, “Como mínimo. Un acercamiento a la microficción hispanoamericana,” disertasi doktoral, Universidad Complutense de Madrid, 1987.- Andrea Bell, “The cuento breve in modern Latin American Literature,” disertasi doktoral, Stanford University, 1991.- Karla Seidy Rojas González, “Estrategias de lectura en el minicuento hispanoamericano,” tesis master, Universidad Autónoma Metropolitana, Meksiko, 2000.- Lauro Zavala, Cartografías del Cuento y la Minificcion (Sevilla: Editorial Renacimiento, 2004).- David Lagmanovich, El Microrrelato. Teoría e historia (Palencia: Menoscuarto, 2006).- Colin Peters, “Minificción: A Narratological Investigation,“ tesis master, Universität Wien, 2008.- Irene Andres-Suárez dan Antonio Rivas, La era de la brevedad. El microrrelato hispánico (Palencia: Menoscuarto Ediciones, 2008).- Violeta Rojo, Breve manual (ampliado) para reconocer minicuentos (Caracas: Editorial Equinoccio, 2009).- Mariví Alonso Ceballos, “El microrrelato argentino: intertextualidad y metaliteratura,” disertasi doktoral, Universidad Complutense de Madrid, 2014. I Congreso Internacional de Minificción digelar di Meksiko (1998); II di Salamanca, Spanyol (2002); III di Valparaíso, Cile, dan Oregon, AS (2004); IV di Neuchâtel, Swiss (2006); V di Neuquén, Argentina (2008); VI di Bogota, Kolombia (2010); VII di Berlin, Jerman (2012); VIII di Kentucky, AS (Oktober 2014). Lauro Zavala, Cartografías del Cuento y la Minificcion (Sevilla: Editorial Renacimiento, 2004), hlm. 69. Ibid., hlm. 87. Secara khusus, “Gerhana” karya Monterroso banyak disebut dalam kajian Amerika Latin (bukan hanya kajian sastranya) karena cerita itu merupakan kritik atas Eurosentrisme sebagaimana diwakili oleh komik Tintin dalam edisi Tawanan Dewa Matahari.
Published on March 07, 2015 01:11
Ronny Agustinus's Blog
- Ronny Agustinus's profile
- 64 followers
Ronny Agustinus isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.



