Andi Eriawan's Blog
January 28, 2020
Soerat Oendangan
Dear, People...
Saya kabarkan bahwa setelah lebaran saya akan menikah. Mudah-mudahan dapat membalut luka sebagian teman dan semakin membuka lebar luka teman yang lain (yang jomblo, maksud saya).
Adapun gedung dan hal teknis lain, akan saya kabarkan pada kesempatan berikutnya. Dan jangan khawatir, tentu saja tidak melalui e-mail atau sms atau intercom atau telepon atau HT atau radio dan benda-benda canggih tapi murah lainnya.
Namun, undangan itu akan sampai pada kalian di waktu dan cara yang tidak pernah kalian sangka-sangka. Mungkin tengah malam lewat cerobong asap, bisa juga dini hari lewat celah pintu kamar. Memang sempat terpikir saya kirim via lubang toilet, tapi khawatir kalian tidak sudi menyentuhnya, meski undangan itu telah dirancang tahan tahi (tapi tidak tahan bau).
Regards,
Andi Eriawan
Tulisan jadul tahun 2003.Ditemukan tidak sengaja sewaktu mengais-ais file film jadoel.
Saya kabarkan bahwa setelah lebaran saya akan menikah. Mudah-mudahan dapat membalut luka sebagian teman dan semakin membuka lebar luka teman yang lain (yang jomblo, maksud saya).
Adapun gedung dan hal teknis lain, akan saya kabarkan pada kesempatan berikutnya. Dan jangan khawatir, tentu saja tidak melalui e-mail atau sms atau intercom atau telepon atau HT atau radio dan benda-benda canggih tapi murah lainnya.
Namun, undangan itu akan sampai pada kalian di waktu dan cara yang tidak pernah kalian sangka-sangka. Mungkin tengah malam lewat cerobong asap, bisa juga dini hari lewat celah pintu kamar. Memang sempat terpikir saya kirim via lubang toilet, tapi khawatir kalian tidak sudi menyentuhnya, meski undangan itu telah dirancang tahan tahi (tapi tidak tahan bau).
Regards,
Andi Eriawan
Tulisan jadul tahun 2003.Ditemukan tidak sengaja sewaktu mengais-ais file film jadoel.
Published on January 28, 2020 09:14
July 30, 2014
Hadir...
Published on July 30, 2014 15:19
September 18, 2013
Farewell, Profesor...
Memasuki gedung berlantai empat berwarna cokelat membosankan itu, Ruski menarik napas dalam-dalam. Ia mantapkan langkah kakinya saat menaiki setiap anak tangga. Napasnya tersengal-sengal di anak tangga terakhir.
“Selamat pagi, Pak Diran,” sapa Ruski penuh formalitas ketika memasuki sebuah ruangan.
Profesor Diran sedang duduk menyandar pada sebuah kursi berlengan. Kacamatanya tebal dengan rambut tipis yang hampir seluruhnya berwarna putih. Pak tua itu sudah menjadi dosen sejak tiga puluh lima tahun yang lalu. “Kamu terlambat sepuluh menit,” sambutnya dingin.
“Maaf, Pak.” Tanpa dipersilakan, Ruski duduk di hadapan dosen itu.
“Kamu tahu, sudah berapa lama kamu tidak datang kemari? Lima bulan,” kata Profesor Diran tanpa menunggu jawaban. “Sebelum itu, enam bulan. Juga dengan dua pertemuan kita sebelumnya, kamu sempat pula menghilang lama. Bila dijumlahkan, kamu sudah menghabiskan waktu hampir tiga tahun untuk mengerjakan skripsi ini … tanpa perkembangan berarti.”
Ruski hanya menundukkan kepala tanpa benar-benar memperhatikan. Ia sudah hafal benar semua kalimat pembuka itu yang didengarnya dari Profesor Diran setiap kali ia datang untuk asistensi tugas akhir.
“Bla … bla … bla …”
Tanpa sengaja, terlihat olehnya sepasang kaki muncul di kolong meja. Pak tua itu tidak mengenakan sepatu; Ruski hampir saja kehilangan kontrol wajahnya untuk menahan tawa.
“Jadi, kamu mengerti?”
“Iya, Pak.”
“Apa yang kamu mengerti?”
“Saya harus segera menyelesaikan skripsi ini dalam waktu dua bulan. Selain itu, karena Bapak mau pensi…” Urat leher Ruski tiba-tiba mengencang. “Apa??! Bapak mau pensiun??”
Profesor Diran mengangguk tanpa senyum.
“Kapan?”
“Dua bulan lagi,” jawab Profesor Diran tenang.
“Kenapa?”
Profesor Diran menunjuk kepalanya sendiri. “Kamu tidak melihat jumlah dan warna rambut saya?”
Ruski mulai panik. “Tapi, bagaimana dengan nasib skripsi saya, Pak? Bapak jangan egois.”
Profesor Diran tersenyum lebar. “Justru itu ... saya jadi penasaran sekarang, apakah dalam dua bulan ini kamu akan diwisuda dan saya pensiun dengan tenang dan menghabiskan waktu dengan menanam bonsai? Atau, kamu akan di-dropout dan saya tetap menanam bonsai dengan tenang?”
Ruski melongo. “Kenapa … saya akan di-dropout dalam dua bulan?”
Profesor Diran menyandarkan tubuhnya pada kursi, tersenyum angkuh. “Karena tidak pernah ada mahasiswa kuliah hingga semester lima belas dalam sejarah institusi ini ....,” katanya dengan suara tegas, dalam dan tanpa bisa ditawar.
“…”
“Kecuali …,” Profesor Diran terbatuk, “pada jaman saya kuliah dulu.”
(taken from Love for Show)

“Tugas seorang guru itu tidak hanya mengajar para muridnya saja. Tugas seorang guru pada hakikatnya adalah membuat para muridnya mengetahui secara persis apa kekuatan dan kelemahan dirinya, dan bisa bersikap dengan tepat atas kekuatan dan kelemahannya tersebut. Seorang guru yang membuat muridnya tidak tahu apa kekuatan dan kelemahannya, bisa dikatakan sebagai pendidik yang gagal…”
[Profesor Oetarjo Diran, Founding Father of Aerospace Technology in Indonesia]
“Selamat pagi, Pak Diran,” sapa Ruski penuh formalitas ketika memasuki sebuah ruangan.
Profesor Diran sedang duduk menyandar pada sebuah kursi berlengan. Kacamatanya tebal dengan rambut tipis yang hampir seluruhnya berwarna putih. Pak tua itu sudah menjadi dosen sejak tiga puluh lima tahun yang lalu. “Kamu terlambat sepuluh menit,” sambutnya dingin.
“Maaf, Pak.” Tanpa dipersilakan, Ruski duduk di hadapan dosen itu.
“Kamu tahu, sudah berapa lama kamu tidak datang kemari? Lima bulan,” kata Profesor Diran tanpa menunggu jawaban. “Sebelum itu, enam bulan. Juga dengan dua pertemuan kita sebelumnya, kamu sempat pula menghilang lama. Bila dijumlahkan, kamu sudah menghabiskan waktu hampir tiga tahun untuk mengerjakan skripsi ini … tanpa perkembangan berarti.”
Ruski hanya menundukkan kepala tanpa benar-benar memperhatikan. Ia sudah hafal benar semua kalimat pembuka itu yang didengarnya dari Profesor Diran setiap kali ia datang untuk asistensi tugas akhir.
“Bla … bla … bla …”
Tanpa sengaja, terlihat olehnya sepasang kaki muncul di kolong meja. Pak tua itu tidak mengenakan sepatu; Ruski hampir saja kehilangan kontrol wajahnya untuk menahan tawa.
“Jadi, kamu mengerti?”
“Iya, Pak.”
“Apa yang kamu mengerti?”
“Saya harus segera menyelesaikan skripsi ini dalam waktu dua bulan. Selain itu, karena Bapak mau pensi…” Urat leher Ruski tiba-tiba mengencang. “Apa??! Bapak mau pensiun??”
Profesor Diran mengangguk tanpa senyum.
“Kapan?”
“Dua bulan lagi,” jawab Profesor Diran tenang.
“Kenapa?”
Profesor Diran menunjuk kepalanya sendiri. “Kamu tidak melihat jumlah dan warna rambut saya?”
Ruski mulai panik. “Tapi, bagaimana dengan nasib skripsi saya, Pak? Bapak jangan egois.”
Profesor Diran tersenyum lebar. “Justru itu ... saya jadi penasaran sekarang, apakah dalam dua bulan ini kamu akan diwisuda dan saya pensiun dengan tenang dan menghabiskan waktu dengan menanam bonsai? Atau, kamu akan di-dropout dan saya tetap menanam bonsai dengan tenang?”
Ruski melongo. “Kenapa … saya akan di-dropout dalam dua bulan?”
Profesor Diran menyandarkan tubuhnya pada kursi, tersenyum angkuh. “Karena tidak pernah ada mahasiswa kuliah hingga semester lima belas dalam sejarah institusi ini ....,” katanya dengan suara tegas, dalam dan tanpa bisa ditawar.
“…”
“Kecuali …,” Profesor Diran terbatuk, “pada jaman saya kuliah dulu.”
(taken from Love for Show)

“Tugas seorang guru itu tidak hanya mengajar para muridnya saja. Tugas seorang guru pada hakikatnya adalah membuat para muridnya mengetahui secara persis apa kekuatan dan kelemahan dirinya, dan bisa bersikap dengan tepat atas kekuatan dan kelemahannya tersebut. Seorang guru yang membuat muridnya tidak tahu apa kekuatan dan kelemahannya, bisa dikatakan sebagai pendidik yang gagal…”
[Profesor Oetarjo Diran, Founding Father of Aerospace Technology in Indonesia]
Published on September 18, 2013 19:47
May 13, 2013
Always, Laila (Repackaged)
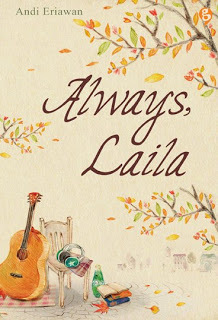 Sebuah Pengantar Seseorang di seberang pulau nun jauh di sana berjarak milyaran langkah pernah melemparkan tuduhan yang kurang bertanggung jawab.
Sebuah Pengantar Seseorang di seberang pulau nun jauh di sana berjarak milyaran langkah pernah melemparkan tuduhan yang kurang bertanggung jawab.“Kamu lebih tahu tentang perempuan daripada apa yang diketahui Sigmund Freud.”
Begitu katanya seusai ia membaca always, Laila.
Berhubung tidak bisa menatap matanya, saya kesulitan membaca maksud si penuduh. Tengah mengejekkah atau sedang jujur memberi apresiasi. Saya lebih merasa tersinggung daripada terpuji. Maklum, waktu itu saya belum tahu siapa itu si Freud.
Seandainya saja si penuduh membaca lagi kisah ini lebih teliti tanpa melewatkan satu pun huruf titik koma spasi, beliau pasti akan menarik kembali kata-katanya dan menggantinya dengan kalimat:
“Kamu lebih tahu tentang perempuan dan juga laki-laki daripada apa yang diketahui Sigmund Freud.”
Maklum, dia sendiri tidak tahu siapa itu si Freud.
Tapi Always, Laila memang berkisah tentang perempuan dan juga laki-laki. Karakter mereka dibangun melalui riset panjang dan mendalam yang dikombinasikan dengan pengalaman pribadi, rekayasa memori, plus imajinasi. Hasilnya adalah dua tokoh ini: Laila dan Pram.
Laila adalah seorang perempuan cantik. Teramat cantik. Bahkan kata cantik pun masih kurang pas terdengar. Cuantikk mungkin lebih tepat. Namun, kecantikannya itu tidak bisa ditangkap oleh kamera. Canon, Philips, Minolta. Ia adalah seorang perempuan terhormat. Hormat pramuka, hormat bendera. Perempuan yang cintanya ia bagi tanpa pandang bulu. Bulu kaki, bulu mata, hidung dan ketiak. Perempuan yang hatinya untuk semua yang mengenal tanpa pandang warna kulit. Putih, kuning, cokelat, abu, merah jambu. Perempuan yang akan dikagumi anak-anak, diminati remaja, dimimpikan lelaki dewasa. Para orangtua akan berebut menjadikannya mantu mereka.
Laila adalah seorang perempuan yang takkan bisa berhenti untuk terus dicintai banyak manusia.
Sementara Pram, ia hanyalah seorang lelaki biasa, baik tingkah maupun rupa. Tapi lelaki ini memiliki apa yang Laila cari: kunci membuka beribu rahasia, pintu menuju masa lalu, jendela mengintip masa depan. Pram mempunyai kantung yang berisikan semua hal yang Laila suka, laci penyimpan keping demi keping kenangan, dan peti untuk menaruh sebentuk rindu, segenggam cemburu dan gairah menggebu.
Dan ini adalah kisah cinta antara keduanya.
Kisah mereka ditulis sembilan tahun lalu dalam wujud deretan abjad yang tersusun rapi. Komputer sudah ditemukan waktu itu. Projek GagasVintage yang digagas penerbit memaksa saya membuka kembali lembaran-lembarannya yang sudah sejak lama saya tutup, saya bungkus plastik dan menyimpannya sebagai warisan berharga bagi anak cucu kelak. Saya selipkan ia di sebuah almari rotan yang juga warisan. Sesekali saya bersihkan dari debu yang menempel, lalu saya semprot dengan pewangi dari Arab oleh-oleh sanak yang pulang berhaji. Berharap sangat si buku selamat dari kutu dan rayap yang jahat. Alhamdulillah, tidak saya temukan satupun mereka di sana.
Iya, saya sedikit berlebihan.
Membaca lagi kisah ini adalah berziarah ke masa lampau. Saya telusuri kota Bandung dalam rentang waktu tahun 1995-2004 yang menjadi latar belakangnya. Saya berjalan-jalan di tiap sudut kota, melacak jejak riwayat yang pernah hilang sambil mengendus jalan pulang. Baru kemudian saya sadari bahwa Always, Laila bukan hanya kisah cinta tokoh-tokoh di dalamnya, namun juga kisah cinta si penulis dengan kotanya.
Memori lama yang sudah terdistorsi dan tercecer, satu persatu saya pungut dengan hati-hati. Saya masih amat muda waktu menulis kisah ini. Masih gagah-gagahnya. Juga, lugu. Si saya muda pernah bercita-cita hendak menguasai dunia waktu itu. Hidupnya hanya demi misi yang ia reka sendiri. Ingin dikuasainya seluruh hati manusia, membuat mereka menangis dan tertawa sesukanya. Dan baginya, takdir hanyalah untuk diperangi.
Namun sayang, ia dikalahkan dengan cara yang demikian kejam.
Dunia menulis akhirnya saya tinggalkan pada Desember 2009. Saya memilih pensiun. Tidak tahu sampai kapan, entah nanti. Tiga judul novel yang sudah sangat langka ditemukan di lapak-lapak toko buku, puluhan surat maki dan cinta yang pernah terkirim, serta blog harian yang saya biarkan tak berpenghuni menjadi saksi bahwa sekurang-kurangnya saya pernah mengetik. Tidak lupa saya ucapkan salam perpisahan pada mereka yang setia membaca tulisan-tulisan saya. Juga pada kota Bandung, kota saya. Kotanya Laila dan Pram.
"Saya mau hidup di desa dan membangun Alfamart di sana."
Begitu saya bilang pada sang istri. Bandung sudah terlalu hiruk dan pikuk. Terlalu padat oleh kendaraan dan pengembangan properti. Nyaris tidak ada lagi yang tersisa bagi kami untuk sekedar berjalan-jalan menikmati udara sore sepulang kerja, mengantarkan si ucrit dan usro bersepeda di taman kelak, atau berkeliling kota di malam minggu sambil memandangi lampu-lampu. Banyak hal telah berubah, banyak hal tinggal sejarah. Perlahan saya menjadi orang asing di sini. Kota ini tak lagi menginspirasi.
"Tapi di desa itu banyak ayam berkeliaran."
Begitu yang dibilang sang istri. Kekhawatirannya akan banyak kotoran ayam bertebaran di pekarangan rumah mengurungkan niat saya untuk pindah. Akhirnya, tiga tahun berlalu tanpa satu pun huruf titik koma spasi. Saya coba jalani misi lainnya: beranak pinak melahirkan anak cucu kelak demi menyelamatkan populasi manusia.
bandung di bulan januari
setelah mencontek catatan-catatan lama
yang sudah menguning
Published on May 13, 2013 01:07
February 6, 2013
D 17 UAL

pada tangki bensin yang sering bocor kampas rem yang tak pernah bekerja maksimal lampu yang telah sekian lama padam

pada pelat nomor yang buntung setengahjarum kilometer yang selalu berada di angka noldan rantai yang sesekali putusserta oli yang kerap menetes

mohon dirahasiakansetiap perbincangan saya dengan penumpang di jok belakang
Bandung, 07 Februari 2013
Tidak, kalian dijual bukan demi rupiah yang tak seberapa.
Published on February 06, 2013 23:03
January 31, 2013
Kembalian
Published on January 31, 2013 01:22
October 1, 2010
Maaf, Tak Diundang
datanglah pada hari perkawinan kami
lihat si tante menangis harupaman-paman tertawa kecilpara ponakan berlariantatkala menyaksikankami berdua dipersatukan
dan kelak putra-putri kamiterlahir, tumbuh,dan bahagiakisah ini takkan pernah lelahuntuk diceritakan
hingga rambut yang memutihberjalan yang tertatihtuhan, biarkan cinta kamilulus teruji
dan yang kami pertengkarkan hanyalahsiapa yang lebih mencintai siapa

“We fell in love with each other at first sight but we spent three years to negotiate the price of such a marriage.” [Wang Guoliang]
Bandung, 02 Oktober 2010
lihat si tante menangis harupaman-paman tertawa kecilpara ponakan berlariantatkala menyaksikankami berdua dipersatukan
dan kelak putra-putri kamiterlahir, tumbuh,dan bahagiakisah ini takkan pernah lelahuntuk diceritakan
hingga rambut yang memutihberjalan yang tertatihtuhan, biarkan cinta kamilulus teruji
dan yang kami pertengkarkan hanyalahsiapa yang lebih mencintai siapa

“We fell in love with each other at first sight but we spent three years to negotiate the price of such a marriage.” [Wang Guoliang]
Bandung, 02 Oktober 2010
Published on October 01, 2010 20:46
November 11, 2009
Telur Dadar
pada masanya nanti
usai mengajar para kanak
berhitung dan mengaji
diam-diam kita akan menangis
melihat mereka terlahir
tumbuh
dan bahagia
“Air matanya jangan sampai tumpah, Bu.”
begitu kata si bungsu
yang belum bisa terpisah
dari ranjang ibu-bapaknya
”Bekal besok, telur dadarnya jangan terlalu garing, Bu...”
demikian pesan si bapak
yang tidak pernah mau terpisah
dari ibu anak-anaknya....
Bandung, 11 November 2009
usai mengajar para kanak
berhitung dan mengaji
diam-diam kita akan menangis
melihat mereka terlahir
tumbuh
dan bahagia
“Air matanya jangan sampai tumpah, Bu.”
begitu kata si bungsu
yang belum bisa terpisah
dari ranjang ibu-bapaknya
”Bekal besok, telur dadarnya jangan terlalu garing, Bu...”
demikian pesan si bapak
yang tidak pernah mau terpisah
dari ibu anak-anaknya....
Bandung, 11 November 2009
Published on November 11, 2009 00:01
October 10, 2009
Alif Ba Ta
Dan tiba-tiba saja saya bilang,“Di hari yang cerah ini, ijinkanlah saya membaca satu dua bait puisi cinta.”
“Ijin diberikan.”Begitu kamu menjawab pelan.
“Apa?”Tanya saya, pura-pura tidak mendengar.[image error]
Kamu meraih secarik post-it dan menuliskan sesuatu di sana. Diserahkannya pada saya dengan acuh tak acuh: Surat Ijin Membaca Puisi. Lengkap dengan tandatangan. Yang kurang hanya cap jempol saja.
Mengatur nafas, saya perhatikan kamu sesaat. Terlambat saya sadari bahwa Tuhan telah menitipkan padamu kecerdasan, selain bola mata yang begitu menarik, tentunya. Tapi, yang namanya titipan itu, harus dipergunakan dan dipelihara baik-baik, ya. Jangan digadai ke mana-mana. Atau dipakai lirik-melirik sembarangan. Juga bukan untuk dikedip-kedip pada laki-laki tidak dikenal.
“Ehm.”Kamu berdehem, mengais perhatian.
“Ya?”Saya bertanya dengan pandangan dermawan.
“Surat ijin itu ada masa berlakunya, Andi. Jangan terlalu lama membuat saya menunggu.”Kamu memperingatkan saya. Ada nada mengancam dan tidak main-main yang berhasil saya tangkap di sana.
Meski begitu, sepertinya kamu sungguh tahu jika saya paling senang sewaktu nama saya disebut penuh. Apalagi kalau kamu bersedia menambah sebutan “Pak” di depannya. Padahal, belum terlalu lama kita saling kenal. Mungkin di kehidupan sebelumnya, kita adalah saudara kembar.
Kamu duduk di situ, saya berdiri di sini. Memandang langit, mencoba mencari kata-kata pembuka. Mungkin awan bagus juga, keras saya berpikir. Atau gunung hijau di kejauhan? Sayang, di sini tidak ada pantai. Dan masih terlalu lama sampai matahari tenggelam.
“Boleh sambil merokok?”Saya bertanya, mencari alasan untuk berlama-lama.
Kamu mengangguk, memandang saya tanpa berkedip.
Aih. Padahal sekiranya menolak, masih banyak waktu untuk berdebat. Rokok pun dibakar, dan asapnya mulai keluar-masuk paru-paru.
“Kamu mau?”Tidak bermaksud kurang ajar, lho. Juga bukan sedang mencari perkara.
Masih menatap, kamu menggelengkan kepala dan tangan mengelus perut.“Tidak baik untuk janin.”“Sungguh?”“Iya. Itu tertulis di kotak pembungkusnya, Pak Andi.”Setengah tidak percaya, saya periksa si kotak pembungkus rokok di tangan kiri. Dan saya dapatkan peringatan itu.
Wow. Lagi-lagi, kamu benar. Selalu saja kamu perhatikan banyak hal. Hal besar, hal kecil tidak pernah luput dari perhatian kamu. Kamu hanya tidak tertarik memperhatikan kekurangan orang lain. Itu saja.
Saya pun membuat keputusan yang saya nilai teramat bijaksana, yaitu mengambil jarak lebih jauh dari kamu. Saya mundur. Sepuluh langkah. Dua puluh langkah. Berusaha agar si asap tidak kamu hisap.
“Segini, cukup?!”Saya berteriak.
“Apa? Tidak terdengar!”Kamu balas berteriak.
Aih. Padahal asap rokok tadi kan tidak berbahaya bagi pendengaran, lalu kenapa tiba-tiba suara saya tidak sampai ke telinga kamu.
Tadinya, saya hendak maju dua atau tiga langkah. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata kamu cantik juga jika dipandang dari jarak segini. Bukan. Bukan berarti jika sedang berdekatan, kamu jadi tidak menarik. Bukan itu. Jauhkan pikiran itu segera. Saat ini juga. Maksud saya adalah, saya berhasil melihat sesuatu lain sewaktu kita berjauhan. Ada sudut warna dan cahaya baru yang berhasil saya tangkap.
Sayang, saya tidak bawa kamera.
Eh, ralat.Sayang, saya belum punya kamera. Jika punya, sudah saya abadikan kamu saat ini juga. Saya cetak besar-besar, lalu saya pampang di kamar. Biar dilepaskan saja itu poster What Women Want.
“Pak Andi, kapan mulainya?!”
Ya, ampun. Ditunggu, rupanya. Saya pikir kamu sudah lupa. Ternyata kamu punya daya ingat juga, ya. Maaf. Tapi, senang rasanya menjadi lelaki yang ditunggu.
“Baiklah, saya mulai sekarang, ya. Siap?”
Kamu mengangguk.
“Suara saya jelas terdengar?”“Iya. Cepat mulai!”“Sungguh?”“Iya.”
Saya pun mulai menghitung aba-aba dalam hati. Satu, dua. Belum juga keluar kata-kata. Lima… Keringat dingin mulai bercucuran. Sepuluh... Dan suara adzan ashar di masjid sebelah menyelamatkan saya.
“Nanti dilanjutkan, ya. Waktunya untuk sembahyang.”
Saya berjalan mendekat, dan kamu bangkit tanpa bisa menolak.
biar ibu yang ajarkan melukis
bapak yang ajarkan menulislalu kanak-kanak kitamembaca alif ba tadengan lancarnya
Bandung, 11 Oktober 2009
“Ijin diberikan.”Begitu kamu menjawab pelan.
“Apa?”Tanya saya, pura-pura tidak mendengar.[image error]
Kamu meraih secarik post-it dan menuliskan sesuatu di sana. Diserahkannya pada saya dengan acuh tak acuh: Surat Ijin Membaca Puisi. Lengkap dengan tandatangan. Yang kurang hanya cap jempol saja.
Mengatur nafas, saya perhatikan kamu sesaat. Terlambat saya sadari bahwa Tuhan telah menitipkan padamu kecerdasan, selain bola mata yang begitu menarik, tentunya. Tapi, yang namanya titipan itu, harus dipergunakan dan dipelihara baik-baik, ya. Jangan digadai ke mana-mana. Atau dipakai lirik-melirik sembarangan. Juga bukan untuk dikedip-kedip pada laki-laki tidak dikenal.
“Ehm.”Kamu berdehem, mengais perhatian.
“Ya?”Saya bertanya dengan pandangan dermawan.
“Surat ijin itu ada masa berlakunya, Andi. Jangan terlalu lama membuat saya menunggu.”Kamu memperingatkan saya. Ada nada mengancam dan tidak main-main yang berhasil saya tangkap di sana.
Meski begitu, sepertinya kamu sungguh tahu jika saya paling senang sewaktu nama saya disebut penuh. Apalagi kalau kamu bersedia menambah sebutan “Pak” di depannya. Padahal, belum terlalu lama kita saling kenal. Mungkin di kehidupan sebelumnya, kita adalah saudara kembar.
Kamu duduk di situ, saya berdiri di sini. Memandang langit, mencoba mencari kata-kata pembuka. Mungkin awan bagus juga, keras saya berpikir. Atau gunung hijau di kejauhan? Sayang, di sini tidak ada pantai. Dan masih terlalu lama sampai matahari tenggelam.
“Boleh sambil merokok?”Saya bertanya, mencari alasan untuk berlama-lama.
Kamu mengangguk, memandang saya tanpa berkedip.
Aih. Padahal sekiranya menolak, masih banyak waktu untuk berdebat. Rokok pun dibakar, dan asapnya mulai keluar-masuk paru-paru.
“Kamu mau?”Tidak bermaksud kurang ajar, lho. Juga bukan sedang mencari perkara.
Masih menatap, kamu menggelengkan kepala dan tangan mengelus perut.“Tidak baik untuk janin.”“Sungguh?”“Iya. Itu tertulis di kotak pembungkusnya, Pak Andi.”Setengah tidak percaya, saya periksa si kotak pembungkus rokok di tangan kiri. Dan saya dapatkan peringatan itu.
Wow. Lagi-lagi, kamu benar. Selalu saja kamu perhatikan banyak hal. Hal besar, hal kecil tidak pernah luput dari perhatian kamu. Kamu hanya tidak tertarik memperhatikan kekurangan orang lain. Itu saja.
Saya pun membuat keputusan yang saya nilai teramat bijaksana, yaitu mengambil jarak lebih jauh dari kamu. Saya mundur. Sepuluh langkah. Dua puluh langkah. Berusaha agar si asap tidak kamu hisap.
“Segini, cukup?!”Saya berteriak.
“Apa? Tidak terdengar!”Kamu balas berteriak.
Aih. Padahal asap rokok tadi kan tidak berbahaya bagi pendengaran, lalu kenapa tiba-tiba suara saya tidak sampai ke telinga kamu.
Tadinya, saya hendak maju dua atau tiga langkah. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata kamu cantik juga jika dipandang dari jarak segini. Bukan. Bukan berarti jika sedang berdekatan, kamu jadi tidak menarik. Bukan itu. Jauhkan pikiran itu segera. Saat ini juga. Maksud saya adalah, saya berhasil melihat sesuatu lain sewaktu kita berjauhan. Ada sudut warna dan cahaya baru yang berhasil saya tangkap.
Sayang, saya tidak bawa kamera.
Eh, ralat.Sayang, saya belum punya kamera. Jika punya, sudah saya abadikan kamu saat ini juga. Saya cetak besar-besar, lalu saya pampang di kamar. Biar dilepaskan saja itu poster What Women Want.
“Pak Andi, kapan mulainya?!”
Ya, ampun. Ditunggu, rupanya. Saya pikir kamu sudah lupa. Ternyata kamu punya daya ingat juga, ya. Maaf. Tapi, senang rasanya menjadi lelaki yang ditunggu.
“Baiklah, saya mulai sekarang, ya. Siap?”
Kamu mengangguk.
“Suara saya jelas terdengar?”“Iya. Cepat mulai!”“Sungguh?”“Iya.”
Saya pun mulai menghitung aba-aba dalam hati. Satu, dua. Belum juga keluar kata-kata. Lima… Keringat dingin mulai bercucuran. Sepuluh... Dan suara adzan ashar di masjid sebelah menyelamatkan saya.
“Nanti dilanjutkan, ya. Waktunya untuk sembahyang.”
Saya berjalan mendekat, dan kamu bangkit tanpa bisa menolak.
biar ibu yang ajarkan melukis
bapak yang ajarkan menulislalu kanak-kanak kitamembaca alif ba tadengan lancarnya
Bandung, 11 Oktober 2009
Published on October 10, 2009 20:11
September 4, 2009
1000 Miles to KUA
Setelah menggunakan KTP palsu selama enam tahun, hari ini saya memutuskan untuk membuat yang asli. Original. The real one.
Ada pun kenapa akhirnya saya berubah pikiran, itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena syarat dari KUA. Bagi mereka yang hendak menikah, KTP asli merupakan modal utama. Di samping rumah, mobil, karir dan uang tunai, tentunya. Masa, mengawali rumah tangga dengan kepalsuan?
Sebagai seorang calon suami dan calon ayah yang penuh dedikasi dan komitmen, mengurus KTP harus dilakukan sendiri, dong. Bersih dan lurus. Tidak bengkok disertai pelicin. Kalau mengurus KTP saja tidak becus, bagaimana dalam mengurusi badan yang gemuk?
Ups…Ini hari minggu, dan pada pukul delapan saya sudah mandi. Biasanya, minggu pagi saya gunakan sebaik-baiknya untuk mencuci baju atau tidur sepanjang hari. Tapi tidak kali ini. Saya fokuskan untuk membuat KTP asli.
Sarapan nasi goreng dibuatkan si Mba… yang saya lupa namanya. Padahal, kami sudah hidup nyaris lima tahun di bawah atap yang sama. Tapi, apalah artinya nama, bukan? Jengkol tetap bau meski kita ganti namanya jadi mawar.
Bukan, Mba. Mba ngga bau sama sekali. Yah, maafkan saya jika becanda berlebihan. Maklum. Anak muda.
Seusai sarapan, motor saya keluarkan dari garasi. Sebagai pengemudi hebat, saya periksa air akki terlebih dahulu. Isinya sudah nyaris kering. Ah, peduli. Pak RT dan Pak RW di dekat rumah lama sudah menunggu. Berangkatlah saya dengan penuh semangat.
Entah kenapa saya begitu semangat hari ini. Juga, hari kemarin. Juga, beberapa hari sebelumnya. Saya pikir, ini mungkin disebabkan oleh pengaruh alkohol. Tapi setelah direnungkan kembali, itu tidak mungkin. Alkohol tidak menyebabkan orang yang meminumnya menjadi bersemangat. Alkohol menyebabkan orang yang meminumnya masuk neraka. Itu yang ustadz saya bilang sewaktu saya kecil. Eh, bukan. Salah, bukan begitu. Ustadzah yang benar, soalnya dia perempuan.
Ketika sampai di rumah yang dituju, Pak RT yang saya temui rupanya sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua RT. Tidak pula naik jabatan menjadi Ketua RW. Tidak pula dimutasi dari Ketua RT 05 menjadi Ketua RT 02. Tapi saya tidak patah arang. Masa, baru diberi sedikit kesulitan sudah mundur menyerah? Hidup itu harus seru, sehingga bisa bercerita pada anak-cucu.
Karena itu, perjalanan dilanjutkan menuju Ketua RT baru. Namanya Pak Heri. Atau, Herry? Ah, saya tidak akan mempermasalahkannya. Biarlah mereka para sarjana hukum saja yang sibuk mengurusi hal seperti itu.“A-N-D-Y atau A-N-D-E-E?” tanya Pak Heri (atau Herry) sewaktu menulis surat keterangan pindah.
Berikutnya, saya bawa surat tersebut ke rumah Ketua RW untuk meminta tandatangannya. Saya beruntung, rumah beliau sangat teramat dekat. Tinggal menyeberang. Sungguh kebetulan yang diatur-Nya, pagar rumah Pak RW terbuka. Saya pun melangkah masuk dan ucapkan salam.
Bagai gayung tak bersambut. Ibarat menjaring air. Bertepuk sebelah tangan. Mengharap bulan membalas senyum. Bermimpi naik gaji. Sepuluh salam saya tak satupun dijawab orang. Mungkin seluruh penghuni rumah beserta isinya sedang berasyik-masyuk. Tidak boleh putus asa, hibur saya dalam hati. Tuhan bersama orang-orang yang bersabar.
Atas kebaikan Pak Heri (atau Harry), saya diberi tahu letak rumah Sekretaris RW. Konon, beliau bisa membantu karena beliaulah si pemegang stempel. Saya pun menuju ke sana dan berharap pada-Nya agar si sekretaris yang akan saya temui ini bukan tipe sekretaris seksi penggoda iman.
Keringat mulai banjiri tubuh satu-satunya ini. Matahari sudah naik tinggi ketika rumah yang dimaksud terlihat. Saya ketuk pintu dan ucapkan salam, lalu pintu pun terbuka. Tuhan mengabulkan doa saya. Si Sekretaris RW adalah seorang bapak-bapak berkumis tebal. Usianya mungkin sudah lewat empatpuluh. Iman saya tetap kokoh di tempatnya.
“Stempelnya sedang dipinjam Pak RW.”...Hmm…Ini seperti dejavu. Saya pernah mengalami ini. Sungguh. Yah, mirip banyak sekali. Beda sedikit jangan disinggung. Kita kan akrab.
Sungguh mirip dengan kejadian enam tahun lalu. Sewaktu saya baru saja pindah dari tempat tinggal lama menuju tempat tinggal baru. Dan waktu itu, atas kejadian tersebut, saya memutuskan untuk menggunakan KTP palsu.
Itulah yang membuat saya tidak bisa mengurus passport (atau paspor?), baru-baru ini ditolak pihak bank saat mencairkan chek (atau cheque?), serta tidak mendapat hak pilih dalam pemilu (atau pemillu?).Hiks…
Wahai, Pak RW.Cepatlah kembali.Saya mau kawin.
“Now, son, you don’t want to drink beer. That’s for daddies and kids with fake IDs.”[Homer Simpson]
Bandung, 05 September 2010
Ada pun kenapa akhirnya saya berubah pikiran, itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena syarat dari KUA. Bagi mereka yang hendak menikah, KTP asli merupakan modal utama. Di samping rumah, mobil, karir dan uang tunai, tentunya. Masa, mengawali rumah tangga dengan kepalsuan?
Sebagai seorang calon suami dan calon ayah yang penuh dedikasi dan komitmen, mengurus KTP harus dilakukan sendiri, dong. Bersih dan lurus. Tidak bengkok disertai pelicin. Kalau mengurus KTP saja tidak becus, bagaimana dalam mengurusi badan yang gemuk?
Ups…Ini hari minggu, dan pada pukul delapan saya sudah mandi. Biasanya, minggu pagi saya gunakan sebaik-baiknya untuk mencuci baju atau tidur sepanjang hari. Tapi tidak kali ini. Saya fokuskan untuk membuat KTP asli.
Sarapan nasi goreng dibuatkan si Mba… yang saya lupa namanya. Padahal, kami sudah hidup nyaris lima tahun di bawah atap yang sama. Tapi, apalah artinya nama, bukan? Jengkol tetap bau meski kita ganti namanya jadi mawar.
Bukan, Mba. Mba ngga bau sama sekali. Yah, maafkan saya jika becanda berlebihan. Maklum. Anak muda.
Seusai sarapan, motor saya keluarkan dari garasi. Sebagai pengemudi hebat, saya periksa air akki terlebih dahulu. Isinya sudah nyaris kering. Ah, peduli. Pak RT dan Pak RW di dekat rumah lama sudah menunggu. Berangkatlah saya dengan penuh semangat.
Entah kenapa saya begitu semangat hari ini. Juga, hari kemarin. Juga, beberapa hari sebelumnya. Saya pikir, ini mungkin disebabkan oleh pengaruh alkohol. Tapi setelah direnungkan kembali, itu tidak mungkin. Alkohol tidak menyebabkan orang yang meminumnya menjadi bersemangat. Alkohol menyebabkan orang yang meminumnya masuk neraka. Itu yang ustadz saya bilang sewaktu saya kecil. Eh, bukan. Salah, bukan begitu. Ustadzah yang benar, soalnya dia perempuan.
Ketika sampai di rumah yang dituju, Pak RT yang saya temui rupanya sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua RT. Tidak pula naik jabatan menjadi Ketua RW. Tidak pula dimutasi dari Ketua RT 05 menjadi Ketua RT 02. Tapi saya tidak patah arang. Masa, baru diberi sedikit kesulitan sudah mundur menyerah? Hidup itu harus seru, sehingga bisa bercerita pada anak-cucu.
Karena itu, perjalanan dilanjutkan menuju Ketua RT baru. Namanya Pak Heri. Atau, Herry? Ah, saya tidak akan mempermasalahkannya. Biarlah mereka para sarjana hukum saja yang sibuk mengurusi hal seperti itu.“A-N-D-Y atau A-N-D-E-E?” tanya Pak Heri (atau Herry) sewaktu menulis surat keterangan pindah.
Berikutnya, saya bawa surat tersebut ke rumah Ketua RW untuk meminta tandatangannya. Saya beruntung, rumah beliau sangat teramat dekat. Tinggal menyeberang. Sungguh kebetulan yang diatur-Nya, pagar rumah Pak RW terbuka. Saya pun melangkah masuk dan ucapkan salam.
Bagai gayung tak bersambut. Ibarat menjaring air. Bertepuk sebelah tangan. Mengharap bulan membalas senyum. Bermimpi naik gaji. Sepuluh salam saya tak satupun dijawab orang. Mungkin seluruh penghuni rumah beserta isinya sedang berasyik-masyuk. Tidak boleh putus asa, hibur saya dalam hati. Tuhan bersama orang-orang yang bersabar.
Atas kebaikan Pak Heri (atau Harry), saya diberi tahu letak rumah Sekretaris RW. Konon, beliau bisa membantu karena beliaulah si pemegang stempel. Saya pun menuju ke sana dan berharap pada-Nya agar si sekretaris yang akan saya temui ini bukan tipe sekretaris seksi penggoda iman.
Keringat mulai banjiri tubuh satu-satunya ini. Matahari sudah naik tinggi ketika rumah yang dimaksud terlihat. Saya ketuk pintu dan ucapkan salam, lalu pintu pun terbuka. Tuhan mengabulkan doa saya. Si Sekretaris RW adalah seorang bapak-bapak berkumis tebal. Usianya mungkin sudah lewat empatpuluh. Iman saya tetap kokoh di tempatnya.
“Stempelnya sedang dipinjam Pak RW.”...Hmm…Ini seperti dejavu. Saya pernah mengalami ini. Sungguh. Yah, mirip banyak sekali. Beda sedikit jangan disinggung. Kita kan akrab.
Sungguh mirip dengan kejadian enam tahun lalu. Sewaktu saya baru saja pindah dari tempat tinggal lama menuju tempat tinggal baru. Dan waktu itu, atas kejadian tersebut, saya memutuskan untuk menggunakan KTP palsu.
Itulah yang membuat saya tidak bisa mengurus passport (atau paspor?), baru-baru ini ditolak pihak bank saat mencairkan chek (atau cheque?), serta tidak mendapat hak pilih dalam pemilu (atau pemillu?).Hiks…
Wahai, Pak RW.Cepatlah kembali.Saya mau kawin.
“Now, son, you don’t want to drink beer. That’s for daddies and kids with fake IDs.”[Homer Simpson]
Bandung, 05 September 2010
Published on September 04, 2009 20:54
Andi Eriawan's Blog
- Andi Eriawan's profile
- 19 followers
Andi Eriawan isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.





