Siddha Malilang's Blog
September 16, 2015
Kembali Terbang
Sebulan sudah saya berada di bagian utara benua Eropa yang konon katanya dingin menusuk tulang. Banyak sekali pengalaman-pengalaman menarik yang mendatangi, termasuk kerinduanku akan Eropa yang akhirnya terpuaskan (untuk sementara). Ada banyak keajaiban yang terjadi, ada banyak mukjizat yang datang tanpa ternubuatkan. Dari semua itu, ada suatu peristiwa besar yang cukup mengubah arah hidupku.
Dua hari terakhirku di Indonesia tahun ini membawaku ke sebuah kencan buta. Semua diawali dari kunjungan rutin ke dokter gigi. Kebetulan, si dokter gigi langgananku ini adalah seorang dokter yang sangat usil dan hobi menjadi mak comblang antara orang-orang yang dikenalnya. Hebatnya lagi, hasil percomblangannya sebagian besar berhasil. Salah satu hasil keusilan tangan dan mulutnya adalah percomblangan seorang sahabatku sendiri yang akan berjalan ke pelaminan di bulan Januari mendatang. Nah, si dokter gigi ini dulu pernah mencoba mencomblangkanku dengan seorang temannya. Sayang seribu sayang, ada sebuah kelemahan dalam rencananya saat itu – si temannya itu ternyata masih dalam status berpacaran dengan orang lain. Saking penasarannya, dia mencoba lagi mencomblangkanku untuk kedua kalinya.
Semua konspirasi dan rencananya berjalan mulus. Aku bertemu dengan seorang dokter gigi manis untuk makan siang bersama. Jujur saja, si ibu dokter gigi ini memang memiliki paras yang cukup rupawan dan sederhana. Ia berasal dari keluarga baik-baik dan sudah memiliki karir yang cukup stabil. Kurang apa lagi, coba?
Seandainya saja si ibu dokter ini bisa mengerti dan memahami idealisme saya dalam menuntut ilmu. Mungkin itu yang cukup mengganjal. Dari percakapan yang ada (dan juga dari post-date report oleh dokter gigi langganan saya), ternyata si ibu dokter juga memiliki ketertarikan kepadaku. WHOAAA! Jarang-jarang kan ada orang yang tertarik pada manusia aneh seperti ini? Hanya saja, dia sudah memiliki visi untuk membangun karir dan keluarga di Indonesia. Berkali-kali ia melontarkan gagasan agar saya berhenti setelah menyelesaikan S3 dan kembali bekerja di kota kelahiran saya.
Mungkin pengaruh usia saya yang sudah mulai menua dan banyaknya teman-teman yang sudah mulai berkeluarga, godaan itu mulai merasuki pikiran. Apakah memang ini jalannya? Apakah memang saya harus kembali pulang dan membuang semua asa dan harapan yang sudah terajut selama bertahun-tahun, semua mimpi yang menjiwai setiap langkah dan resiko yang sudah terambil. Semua itu sempat tercurah dalam sebuah status yang tertulis, mengenai jalanan yang terbelah menjadi dua simpangan. Jalan tempatku masih bersikeras mengejar mimpi – jalanan yang tidak rata dan berbatu – serta jalan di mana aku bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman. Dilema itu menyerangku berkali-kali, hingga dalam keputusasaan, aku berpikir untuk menjalani jalanan yang nyaman itu. Saya nyaman, hidup mapan, semua senang. Selesai. Happy Ending! Toh jalan ini akan membawaku kepada sebuah masa depan yang pernah terbesit dan tertulis dalam sebuah cerita dari tahun-tahun putih abu-abu.
Biarlah Swedia dan Macau menjadi petualangan terakhirku, sebelum akhirnya aku merantai diriku sendiri di Yogyakarta; sepercik pikir menyala lemah di dalam kepala. Mungkin ini akan menjadi pelabuhan terakhirku, tempat aku bisa beristirahat tanpa terbeban semua mimpi-mimpi besar.
Hanya selang beberapa hari setelah mendarat di Swedia, aku bertemu dengan seseorang. Tak ada harapan dan ekspektasi apapun, karena aku sudah lelah sakit hati. Tetapi ada sebuah kalimat darinya yang mampu membuatku luluh, “Aku ini seorang dokter. Di manapun kamu akan berkarya kelak, aku tetap dapat mendampingi dan mengikutimu!”
Kata-kata itu seolah menumbuhkan kembali sayap yang pernah kurobek sendiri. Bukan lagi cinta tai kucing atau romantika mendayu-dayu yang ia tawarkan. Bukan juga kehidupan dan stabilitas yang disodorkan. Ia datang memperbaharui mimpi dan harapanku. Saat kami saling mengikat komitmen dalam sebuah hubungan pacaran, ia menjadi separuh sayap yang mengepak dalam perjalananku. Semua asa dan cita-cita yang sudah siap kutanggalkan, dijahitnya baru dan dikenakannya erat membalut jiwa dan ragaku.
Mungkin, inilah keajaiban yang ditawarkan Swedia.
Dua hari terakhirku di Indonesia tahun ini membawaku ke sebuah kencan buta. Semua diawali dari kunjungan rutin ke dokter gigi. Kebetulan, si dokter gigi langgananku ini adalah seorang dokter yang sangat usil dan hobi menjadi mak comblang antara orang-orang yang dikenalnya. Hebatnya lagi, hasil percomblangannya sebagian besar berhasil. Salah satu hasil keusilan tangan dan mulutnya adalah percomblangan seorang sahabatku sendiri yang akan berjalan ke pelaminan di bulan Januari mendatang. Nah, si dokter gigi ini dulu pernah mencoba mencomblangkanku dengan seorang temannya. Sayang seribu sayang, ada sebuah kelemahan dalam rencananya saat itu – si temannya itu ternyata masih dalam status berpacaran dengan orang lain. Saking penasarannya, dia mencoba lagi mencomblangkanku untuk kedua kalinya.
Semua konspirasi dan rencananya berjalan mulus. Aku bertemu dengan seorang dokter gigi manis untuk makan siang bersama. Jujur saja, si ibu dokter gigi ini memang memiliki paras yang cukup rupawan dan sederhana. Ia berasal dari keluarga baik-baik dan sudah memiliki karir yang cukup stabil. Kurang apa lagi, coba?
Seandainya saja si ibu dokter ini bisa mengerti dan memahami idealisme saya dalam menuntut ilmu. Mungkin itu yang cukup mengganjal. Dari percakapan yang ada (dan juga dari post-date report oleh dokter gigi langganan saya), ternyata si ibu dokter juga memiliki ketertarikan kepadaku. WHOAAA! Jarang-jarang kan ada orang yang tertarik pada manusia aneh seperti ini? Hanya saja, dia sudah memiliki visi untuk membangun karir dan keluarga di Indonesia. Berkali-kali ia melontarkan gagasan agar saya berhenti setelah menyelesaikan S3 dan kembali bekerja di kota kelahiran saya.
Mungkin pengaruh usia saya yang sudah mulai menua dan banyaknya teman-teman yang sudah mulai berkeluarga, godaan itu mulai merasuki pikiran. Apakah memang ini jalannya? Apakah memang saya harus kembali pulang dan membuang semua asa dan harapan yang sudah terajut selama bertahun-tahun, semua mimpi yang menjiwai setiap langkah dan resiko yang sudah terambil. Semua itu sempat tercurah dalam sebuah status yang tertulis, mengenai jalanan yang terbelah menjadi dua simpangan. Jalan tempatku masih bersikeras mengejar mimpi – jalanan yang tidak rata dan berbatu – serta jalan di mana aku bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman. Dilema itu menyerangku berkali-kali, hingga dalam keputusasaan, aku berpikir untuk menjalani jalanan yang nyaman itu. Saya nyaman, hidup mapan, semua senang. Selesai. Happy Ending! Toh jalan ini akan membawaku kepada sebuah masa depan yang pernah terbesit dan tertulis dalam sebuah cerita dari tahun-tahun putih abu-abu.
Biarlah Swedia dan Macau menjadi petualangan terakhirku, sebelum akhirnya aku merantai diriku sendiri di Yogyakarta; sepercik pikir menyala lemah di dalam kepala. Mungkin ini akan menjadi pelabuhan terakhirku, tempat aku bisa beristirahat tanpa terbeban semua mimpi-mimpi besar.
Hanya selang beberapa hari setelah mendarat di Swedia, aku bertemu dengan seseorang. Tak ada harapan dan ekspektasi apapun, karena aku sudah lelah sakit hati. Tetapi ada sebuah kalimat darinya yang mampu membuatku luluh, “Aku ini seorang dokter. Di manapun kamu akan berkarya kelak, aku tetap dapat mendampingi dan mengikutimu!”
Kata-kata itu seolah menumbuhkan kembali sayap yang pernah kurobek sendiri. Bukan lagi cinta tai kucing atau romantika mendayu-dayu yang ia tawarkan. Bukan juga kehidupan dan stabilitas yang disodorkan. Ia datang memperbaharui mimpi dan harapanku. Saat kami saling mengikat komitmen dalam sebuah hubungan pacaran, ia menjadi separuh sayap yang mengepak dalam perjalananku. Semua asa dan cita-cita yang sudah siap kutanggalkan, dijahitnya baru dan dikenakannya erat membalut jiwa dan ragaku.
Mungkin, inilah keajaiban yang ditawarkan Swedia.
Published on September 16, 2015 04:40
January 28, 2015
Lela Ledhung
Sore ini, saya ditemani sebuah lagu bahasa Jawa yang cukup akrab di telinga hampir semua anak-anak dari kota kelahiran saya. Lagu ini - Lela Ledhung - biasa dinyanyikan oleh kaum ibu untuk menidurkan anak mereka. Tentu saja, lagu ini membawa pikiran saya berkeliaran jauh ke berbagai tempat dalam memori.
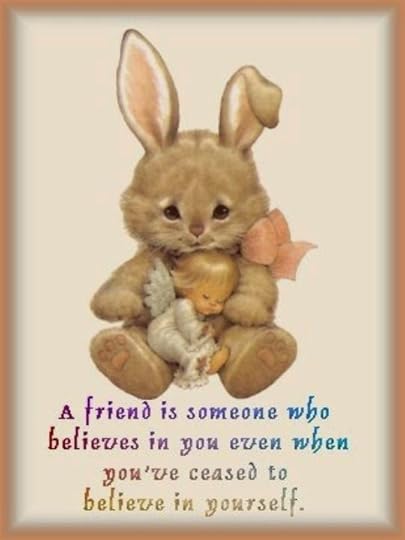 Dan entah kenapa, saya jadi ingin menangis. Menangis menumpahkan semua beban hati, semua lelah letih yang menumpuk jauh di dalam dada. Lagu ini semakin mempertajam kesedihan itu, serasa saya ingin kembali ke dalam pelukan ibu dan menangis lama, hanya menangis dan menceritakan semuanya kepada beliau. Saya hanya ingin masuk dalam pelukan hangat dan mendapatkan ketenangan dalam belaian beliau. Rasanya, semua beban dan masalah akan dapat lenyap hanya dengan usapan lembut beliau di rambut dan kepala saya. Rasanya, semua hantu dan setan yang menghantui dan bergelayut memberati pundak akan sontak hilang berlari tunggang langgang hanya dengan sebuah ucap, "Semuanya akan baik-baik saja, nak!"
Dan entah kenapa, saya jadi ingin menangis. Menangis menumpahkan semua beban hati, semua lelah letih yang menumpuk jauh di dalam dada. Lagu ini semakin mempertajam kesedihan itu, serasa saya ingin kembali ke dalam pelukan ibu dan menangis lama, hanya menangis dan menceritakan semuanya kepada beliau. Saya hanya ingin masuk dalam pelukan hangat dan mendapatkan ketenangan dalam belaian beliau. Rasanya, semua beban dan masalah akan dapat lenyap hanya dengan usapan lembut beliau di rambut dan kepala saya. Rasanya, semua hantu dan setan yang menghantui dan bergelayut memberati pundak akan sontak hilang berlari tunggang langgang hanya dengan sebuah ucap, "Semuanya akan baik-baik saja, nak!"
Terkesan sederhana bukan? Bukankah saya bisa menelepon ibu saya dan menangis bercerita tentang semuanya itu?
Tidak!
Tidak!
Alih-alih mendapatkan kenyamanan dan rasa aman, beliau pasti justru akan menambah banyak beban dan hantu. Bukannya rasa lega, saya hanya akan merasa tambah terbeban dengan semua kemarahannya. Ada beberapa bagian dari hidup saya yang tidak pernah diterima oleh beliau, ada fragmen-fragmen kehidupan saya yang senantiasa ditolak dan dilihat dengan penuh pandangan jijik, dan ada luka yang masih belum sembuh - luka yang pernah ditorehkan oleh beliau.
Setiap kali saya bercerita, selalu saja ada bagian yang tidak pernah dapat terucap. Ada bagian yang tidak dapat diungkap dan disampaikan. Bagian-bagian itulah yang lalu berkembang menjadi duri dalam daging, tumbuh besar menjadi tombak dan pedang yang menyobek rasa dari dalam. Dipupuk kesedihan, dipendam kesendirian, mereka berkembang besar seolah berusaha untuk mengoyakku dari dalam.
Saya benar-benar rindu momen-momen itu, ketika saya bisa berlindung dalam peluk seorang ayah atau ibu. Tapi, bisakah seseorang merindukan apa yang tidak pernah dialaminya? Bisakah rindu akan sesuatu yang mungkin tidak pernah ada itu terbentuk? Saya tidak tahu.
Mungkin saat ini saya hanya ingin menangis lepas. Peluk dan ketenangan itu hanya dapat terbentuk dalam bayangan dan suara musik "Lela Ledhung". Mungkin saat ini, atau mungkin juga tidak akan pernah dapat kuraih di kehidupan ini.
Saat ini, biarkan saya menangis tanpa suara, tanpa air mata. Tinggalkan saya di pojok ruangan, tempat saya tertunduk terduduk sembari mencakar udara mencari sosok ibunda.
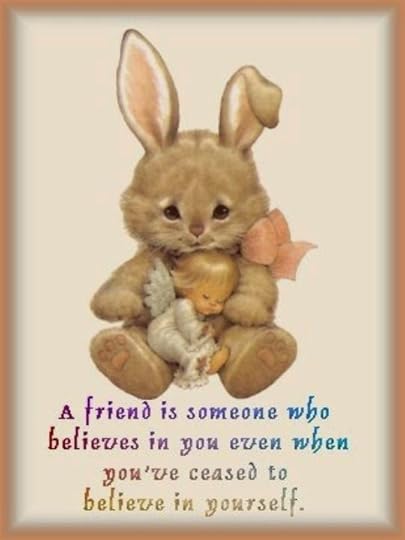 Dan entah kenapa, saya jadi ingin menangis. Menangis menumpahkan semua beban hati, semua lelah letih yang menumpuk jauh di dalam dada. Lagu ini semakin mempertajam kesedihan itu, serasa saya ingin kembali ke dalam pelukan ibu dan menangis lama, hanya menangis dan menceritakan semuanya kepada beliau. Saya hanya ingin masuk dalam pelukan hangat dan mendapatkan ketenangan dalam belaian beliau. Rasanya, semua beban dan masalah akan dapat lenyap hanya dengan usapan lembut beliau di rambut dan kepala saya. Rasanya, semua hantu dan setan yang menghantui dan bergelayut memberati pundak akan sontak hilang berlari tunggang langgang hanya dengan sebuah ucap, "Semuanya akan baik-baik saja, nak!"
Dan entah kenapa, saya jadi ingin menangis. Menangis menumpahkan semua beban hati, semua lelah letih yang menumpuk jauh di dalam dada. Lagu ini semakin mempertajam kesedihan itu, serasa saya ingin kembali ke dalam pelukan ibu dan menangis lama, hanya menangis dan menceritakan semuanya kepada beliau. Saya hanya ingin masuk dalam pelukan hangat dan mendapatkan ketenangan dalam belaian beliau. Rasanya, semua beban dan masalah akan dapat lenyap hanya dengan usapan lembut beliau di rambut dan kepala saya. Rasanya, semua hantu dan setan yang menghantui dan bergelayut memberati pundak akan sontak hilang berlari tunggang langgang hanya dengan sebuah ucap, "Semuanya akan baik-baik saja, nak!"Terkesan sederhana bukan? Bukankah saya bisa menelepon ibu saya dan menangis bercerita tentang semuanya itu?
Tidak!
Tidak!
Alih-alih mendapatkan kenyamanan dan rasa aman, beliau pasti justru akan menambah banyak beban dan hantu. Bukannya rasa lega, saya hanya akan merasa tambah terbeban dengan semua kemarahannya. Ada beberapa bagian dari hidup saya yang tidak pernah diterima oleh beliau, ada fragmen-fragmen kehidupan saya yang senantiasa ditolak dan dilihat dengan penuh pandangan jijik, dan ada luka yang masih belum sembuh - luka yang pernah ditorehkan oleh beliau.
Setiap kali saya bercerita, selalu saja ada bagian yang tidak pernah dapat terucap. Ada bagian yang tidak dapat diungkap dan disampaikan. Bagian-bagian itulah yang lalu berkembang menjadi duri dalam daging, tumbuh besar menjadi tombak dan pedang yang menyobek rasa dari dalam. Dipupuk kesedihan, dipendam kesendirian, mereka berkembang besar seolah berusaha untuk mengoyakku dari dalam.
Saya benar-benar rindu momen-momen itu, ketika saya bisa berlindung dalam peluk seorang ayah atau ibu. Tapi, bisakah seseorang merindukan apa yang tidak pernah dialaminya? Bisakah rindu akan sesuatu yang mungkin tidak pernah ada itu terbentuk? Saya tidak tahu.
Mungkin saat ini saya hanya ingin menangis lepas. Peluk dan ketenangan itu hanya dapat terbentuk dalam bayangan dan suara musik "Lela Ledhung". Mungkin saat ini, atau mungkin juga tidak akan pernah dapat kuraih di kehidupan ini.
Saat ini, biarkan saya menangis tanpa suara, tanpa air mata. Tinggalkan saya di pojok ruangan, tempat saya tertunduk terduduk sembari mencakar udara mencari sosok ibunda.
Published on January 28, 2015 00:51
January 25, 2015
Penyangkalan Diri / Denial
Tiba-tiba saya tergelitik ingin berbicara mengenai penyangkalan diri – atau istilah kerennya self-denial. Entah mengapa, akhir-akhir ini banyak sekali teman dan kenalan saya yang sepertinya sedang bergulat dan bergumul dengan masalah ini. Well, sebelum masuk ke tulisan saya yang aneh, panjang, (se)lebar (perut saya), dan (mungkin tidak) bermutu, saya ingin menyampaikan kesimpulan dulu. (Tuh kan, benar-benar sangat bermutu. Kesimpulan kok di depan? Harusnya kan di belakang!)
Nah, kesimpulan dari penyangkalan diri ini adalah penderitaan diri sendiri (yang sebenarnya tidak usah ditulis juga semua orang sudah tahu). Nah, kebetulan saya sendiri juga pernah punya pengalaman dengan yang namanya self-denial ini dan berakhir dengan tersiksanya diri saya selama empat tahun. Mau nonton tv nggak enak, mau baca buku tidak bisa sepenuhnya konsentrasi, tapi kalau mau makan tetap lahap sih.
Semua berawal dengan kebencian saya terhadap suatu benda bernama kacamata. Iya, bertahun-tahun saya benci dengan kacamata. Bagi diri saya yang masih kecil dan imut-imut waktu itu, memakai kacamata membuat saya terlihat lemah dan cacat. Habisnya, selalu ada himbauan untuk tidak memukul orang yang berkacamata. Sudah begitu, pelajaran IPA sejak SD selalu menyebutnya dengan ‘cacat mata’. Nah, sebagai siswa yang baik, saya kan mengamini semua yang saya pelajari dan memasukkan semuanya ke dalam memori otak, hati, dan jiwa.
 Dari upaya menggali-gali memori, saya menemukan sebuah fragmen hidup yang sebenarnya cukup menggelikan dan memalukan. Kejadiannya saat saya masih duduk di bangku kelas 2 SD. Nah, keantian dan kebencian saya terhadap kacamata berpadu dengan fantasi anak-anak yang masih sangat liar (sampai sekarang masih liar sih sebenarnya). Saat itu, dengan mulai bertambah banyak anak-anak yang memakai kacamata di kelas, saya mulai menganggap bahwa ada penyakit dan virus yang menyebar di sekolah. Virus KM (alias Kaca Mata), begitu kami menyebutnya. Eh, kami??? Iyaa!! Saya membentuk sebuah kelompok detektif untuk menyelidiki penyebaran virus KM ini. Saking liarnya fantasi saya (yang saat itu menjadi pimpinan dari grup detektif ini, kami sampai punya sebuah buku khusus yang berisi analisa penyebaran virus KM dari kedekatan tempat duduk, kedekatan rumah, dan juga silsilah keluarga.
Dari upaya menggali-gali memori, saya menemukan sebuah fragmen hidup yang sebenarnya cukup menggelikan dan memalukan. Kejadiannya saat saya masih duduk di bangku kelas 2 SD. Nah, keantian dan kebencian saya terhadap kacamata berpadu dengan fantasi anak-anak yang masih sangat liar (sampai sekarang masih liar sih sebenarnya). Saat itu, dengan mulai bertambah banyak anak-anak yang memakai kacamata di kelas, saya mulai menganggap bahwa ada penyakit dan virus yang menyebar di sekolah. Virus KM (alias Kaca Mata), begitu kami menyebutnya. Eh, kami??? Iyaa!! Saya membentuk sebuah kelompok detektif untuk menyelidiki penyebaran virus KM ini. Saking liarnya fantasi saya (yang saat itu menjadi pimpinan dari grup detektif ini, kami sampai punya sebuah buku khusus yang berisi analisa penyebaran virus KM dari kedekatan tempat duduk, kedekatan rumah, dan juga silsilah keluarga.
Nah, ternyata karma itu menyebalkan. Saat saya mengecap bangku pendidikan di kelas 6 SD, penglihatan mata kiri saya mulai kabur. MAMPUSSS!!! Itu pikiran pertama yang terlintas di benak saya saat itu. Saya jadi orang cacaaat!!! Saya jadi orang lemaaaaah!!!!! Pokoknya waktu itu membayangkan diri saya memakai kacamata itu sudah sebuah mimpi buruk tersendiri. Lebih parah lagi, sahabat dekat saya waktu itu mulai memakai kacamata juga. (Sepertinya kami berdua terlalu banyak bermain video game dan membaca komik sambil tiduran).
Kenapa saya ikutan panik sewaktu mengetahui sahabat dekat saya memakai kacamata? Karena yang ada di pikiran saat itu adalah pertanyaan dari orang tua mengenai dia, lalu kecurigaan mereka akan keadaan mata anaknya. Mampus! Pasti bakal dicek mata!!! Sudah begitu, tiba-tiba di dua kelas sebelah tiba-tiba ada pengecekan mata dari Puskesmas setempat. Tiba-tiba saja di minggu berikutnya, jumlah anak yang memakai kacamata di sekolah bertambah cukup banyak.
Bukan saya namanya kalau hanya diam berpasrah pada nasib. Lalu apa yang saya lakukan? Pertama, mulai mencuri wortel mentah dari kulkas di rumah saya dan rumah Opa. Kan konon katanya wortel itu bagus untuk mata. Jadilah saya semacam siluman kelinci yang setiap siang isinya menggigiti wortel mentah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, saya membaca pola jadwal pemeriksaan mata yang ternyata seminggu sekali. Jadilah di tiap hari yang saya curigai akan ada pemeriksaan mata, malamnya saya tidur telanjang di depan kipas angin. Harapannya akan masuk angin, sehinga bisa bolos sekolah persis di hari itu.
Nah, ternyata keberuntungan itu tidak jauh dari saya. Kelas saya dilompati!!! Entah kenapa, tapi benar-benar semua amaaan……
Memasuki jenjang SMP, saya masih dengan pedenya tidak memakai kacamata. Padahal pandangan semakin lama semakin bertambah kabur. Alhasil, setiap kali saya terlambat dan kebagian tempat duduk di belakang kelas, doa saya adalah guru-guru yang mengajar di hari itu tidak menuliskan catatan di papan tulis. Yang lebih parah lagi adalah soal ulangan yang ditulis di papan tulis. Aduh, mata sudah dipicing-picingkan seperti apapun masih tetap tidak terlihat semuanya. Akibatnya, saya sering dengan takut-takut minta tolong teman sebangku untuk menuliskan soal ulangan itu. Nah, karena soal ulangan itu ditulis di secarik kertas kecil, jadilah saya terlihat seperti sedang menyontek. Haduh, pertaruhan nama baik saya sebagai seorang siswa baik-baik.
Di rumah, nasib saya tidak jauh lebih baik. Saat itu, TV ditaruh di atas lemari yang cukup tinggi. Nah, jadilah saya menonton TV dengan jarak yang cukup dekat. Sudah begitu, agar tidak ketahuan orang tua kalau saya selalu memicingkan mata, saya punya posisi sendiri, dimana saya terlihat seperti sedang bertopang dagu. Padahal sebenarnya posisi telapak tangan saya itu menyamarkan picingan mata. Sayang sekali, dengan posisi itu saya jadi tidak bisa menonton TV sambil makan. Sialnya lagi, pada waktu itu bapak baru saja membeli VCD player. Film-film yang seharusnya bisa menghibur saya justru menciptakan sebuah tantangan baru.
Begitu lulus SMP, saya memutuskan untuk jujur saja kepada orang tua saya. Pikiran saya waktu itu toh teman-teman di SMA juga teman-teman baru. Mereka tidak kenal saya sebelum saya berkacamata. Eh, sudah ada keputusan untuk jujur, saya malah bingung bagaimana saya harus mengaku kepada mereka?
Entah malaikat mana yang secara tiba-tiba mengetok kepala orang tua saya, sehingga suatu sore mereka sadar mendadak. Saya sedang makan malam sambil membaca buku di meja makan dengan posisi sama seperti biasanya, ibu tiba-tiba berteriak, “Baca buku kok dekat-dekat! Matamu nggak keliatan? Jangan-jangan kamu minus?”
BADALAAAAAH! Posisi ini dan kebiasaan ini sudah saya lakukan selama empat tahun, biasanya tidak ada komentar. Eeeh, ini kok tumben sadar. Benar-benar ada malaikat yang menggetok nih.
Dan dari sore itulah, saya akhirnya menerima nasib sebagai seorang pemuda harapan bangsa yang berkacamata. Ternyata, masih tetap tampan sih….
Kesimpulannya? Sudah ditulis di ataaas!!!!
Nah, kesimpulan dari penyangkalan diri ini adalah penderitaan diri sendiri (yang sebenarnya tidak usah ditulis juga semua orang sudah tahu). Nah, kebetulan saya sendiri juga pernah punya pengalaman dengan yang namanya self-denial ini dan berakhir dengan tersiksanya diri saya selama empat tahun. Mau nonton tv nggak enak, mau baca buku tidak bisa sepenuhnya konsentrasi, tapi kalau mau makan tetap lahap sih.
Semua berawal dengan kebencian saya terhadap suatu benda bernama kacamata. Iya, bertahun-tahun saya benci dengan kacamata. Bagi diri saya yang masih kecil dan imut-imut waktu itu, memakai kacamata membuat saya terlihat lemah dan cacat. Habisnya, selalu ada himbauan untuk tidak memukul orang yang berkacamata. Sudah begitu, pelajaran IPA sejak SD selalu menyebutnya dengan ‘cacat mata’. Nah, sebagai siswa yang baik, saya kan mengamini semua yang saya pelajari dan memasukkan semuanya ke dalam memori otak, hati, dan jiwa.
 Dari upaya menggali-gali memori, saya menemukan sebuah fragmen hidup yang sebenarnya cukup menggelikan dan memalukan. Kejadiannya saat saya masih duduk di bangku kelas 2 SD. Nah, keantian dan kebencian saya terhadap kacamata berpadu dengan fantasi anak-anak yang masih sangat liar (sampai sekarang masih liar sih sebenarnya). Saat itu, dengan mulai bertambah banyak anak-anak yang memakai kacamata di kelas, saya mulai menganggap bahwa ada penyakit dan virus yang menyebar di sekolah. Virus KM (alias Kaca Mata), begitu kami menyebutnya. Eh, kami??? Iyaa!! Saya membentuk sebuah kelompok detektif untuk menyelidiki penyebaran virus KM ini. Saking liarnya fantasi saya (yang saat itu menjadi pimpinan dari grup detektif ini, kami sampai punya sebuah buku khusus yang berisi analisa penyebaran virus KM dari kedekatan tempat duduk, kedekatan rumah, dan juga silsilah keluarga.
Dari upaya menggali-gali memori, saya menemukan sebuah fragmen hidup yang sebenarnya cukup menggelikan dan memalukan. Kejadiannya saat saya masih duduk di bangku kelas 2 SD. Nah, keantian dan kebencian saya terhadap kacamata berpadu dengan fantasi anak-anak yang masih sangat liar (sampai sekarang masih liar sih sebenarnya). Saat itu, dengan mulai bertambah banyak anak-anak yang memakai kacamata di kelas, saya mulai menganggap bahwa ada penyakit dan virus yang menyebar di sekolah. Virus KM (alias Kaca Mata), begitu kami menyebutnya. Eh, kami??? Iyaa!! Saya membentuk sebuah kelompok detektif untuk menyelidiki penyebaran virus KM ini. Saking liarnya fantasi saya (yang saat itu menjadi pimpinan dari grup detektif ini, kami sampai punya sebuah buku khusus yang berisi analisa penyebaran virus KM dari kedekatan tempat duduk, kedekatan rumah, dan juga silsilah keluarga. Nah, ternyata karma itu menyebalkan. Saat saya mengecap bangku pendidikan di kelas 6 SD, penglihatan mata kiri saya mulai kabur. MAMPUSSS!!! Itu pikiran pertama yang terlintas di benak saya saat itu. Saya jadi orang cacaaat!!! Saya jadi orang lemaaaaah!!!!! Pokoknya waktu itu membayangkan diri saya memakai kacamata itu sudah sebuah mimpi buruk tersendiri. Lebih parah lagi, sahabat dekat saya waktu itu mulai memakai kacamata juga. (Sepertinya kami berdua terlalu banyak bermain video game dan membaca komik sambil tiduran).
Kenapa saya ikutan panik sewaktu mengetahui sahabat dekat saya memakai kacamata? Karena yang ada di pikiran saat itu adalah pertanyaan dari orang tua mengenai dia, lalu kecurigaan mereka akan keadaan mata anaknya. Mampus! Pasti bakal dicek mata!!! Sudah begitu, tiba-tiba di dua kelas sebelah tiba-tiba ada pengecekan mata dari Puskesmas setempat. Tiba-tiba saja di minggu berikutnya, jumlah anak yang memakai kacamata di sekolah bertambah cukup banyak.
Bukan saya namanya kalau hanya diam berpasrah pada nasib. Lalu apa yang saya lakukan? Pertama, mulai mencuri wortel mentah dari kulkas di rumah saya dan rumah Opa. Kan konon katanya wortel itu bagus untuk mata. Jadilah saya semacam siluman kelinci yang setiap siang isinya menggigiti wortel mentah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, saya membaca pola jadwal pemeriksaan mata yang ternyata seminggu sekali. Jadilah di tiap hari yang saya curigai akan ada pemeriksaan mata, malamnya saya tidur telanjang di depan kipas angin. Harapannya akan masuk angin, sehinga bisa bolos sekolah persis di hari itu.
Nah, ternyata keberuntungan itu tidak jauh dari saya. Kelas saya dilompati!!! Entah kenapa, tapi benar-benar semua amaaan……
Memasuki jenjang SMP, saya masih dengan pedenya tidak memakai kacamata. Padahal pandangan semakin lama semakin bertambah kabur. Alhasil, setiap kali saya terlambat dan kebagian tempat duduk di belakang kelas, doa saya adalah guru-guru yang mengajar di hari itu tidak menuliskan catatan di papan tulis. Yang lebih parah lagi adalah soal ulangan yang ditulis di papan tulis. Aduh, mata sudah dipicing-picingkan seperti apapun masih tetap tidak terlihat semuanya. Akibatnya, saya sering dengan takut-takut minta tolong teman sebangku untuk menuliskan soal ulangan itu. Nah, karena soal ulangan itu ditulis di secarik kertas kecil, jadilah saya terlihat seperti sedang menyontek. Haduh, pertaruhan nama baik saya sebagai seorang siswa baik-baik.
Di rumah, nasib saya tidak jauh lebih baik. Saat itu, TV ditaruh di atas lemari yang cukup tinggi. Nah, jadilah saya menonton TV dengan jarak yang cukup dekat. Sudah begitu, agar tidak ketahuan orang tua kalau saya selalu memicingkan mata, saya punya posisi sendiri, dimana saya terlihat seperti sedang bertopang dagu. Padahal sebenarnya posisi telapak tangan saya itu menyamarkan picingan mata. Sayang sekali, dengan posisi itu saya jadi tidak bisa menonton TV sambil makan. Sialnya lagi, pada waktu itu bapak baru saja membeli VCD player. Film-film yang seharusnya bisa menghibur saya justru menciptakan sebuah tantangan baru.
Begitu lulus SMP, saya memutuskan untuk jujur saja kepada orang tua saya. Pikiran saya waktu itu toh teman-teman di SMA juga teman-teman baru. Mereka tidak kenal saya sebelum saya berkacamata. Eh, sudah ada keputusan untuk jujur, saya malah bingung bagaimana saya harus mengaku kepada mereka?
Entah malaikat mana yang secara tiba-tiba mengetok kepala orang tua saya, sehingga suatu sore mereka sadar mendadak. Saya sedang makan malam sambil membaca buku di meja makan dengan posisi sama seperti biasanya, ibu tiba-tiba berteriak, “Baca buku kok dekat-dekat! Matamu nggak keliatan? Jangan-jangan kamu minus?”
BADALAAAAAH! Posisi ini dan kebiasaan ini sudah saya lakukan selama empat tahun, biasanya tidak ada komentar. Eeeh, ini kok tumben sadar. Benar-benar ada malaikat yang menggetok nih.
Dan dari sore itulah, saya akhirnya menerima nasib sebagai seorang pemuda harapan bangsa yang berkacamata. Ternyata, masih tetap tampan sih….
Kesimpulannya? Sudah ditulis di ataaas!!!!
Published on January 25, 2015 21:32
November 16, 2014
Kelas Hidup dan Pelabuhan Terakhir
Satu kelas hidup telah selesai. Saya sudah mempelajari semua hal yang harus dipelajari dari kelas itu. Saatnya melangkah menuju kelas lain dengan tingkat lebih lanjut.
Rasa-rasanya itulah yang coba saya tanamkan dalam otak dan benak belakangan ini, sebuah percobaan untuk menghibur diri sendiri dari satu peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Lagi-lagi saya menjadi korban permainan paling kejam di dunia ini, permainan cinta dan hati. Entah mengapa, saya yang oleh banyak teman digelari sebagai seorang strategis dan manipulator handal selalu menemui kekalahan dalam permainan ini. Entahlah....
Jika pada kejatuhan-kejatuhan kemarin, saya terfokus pada segala hal yang buruk dan negatif, saat ini saya mencoba hanya melihat hikmahnya saja. Setidaknya, saya belajar kembali untuk membaca semua tindakan secara positif, tanpa ada motif apapun di baliknya. Dua kali berpacaran dengan drama queen mau tidak mau membuat saya selalu curiga dengan segala macam tindakan. Yah, kali ini walaupun ujung-ujungnya saya tetap disakiti dan dikecewakan, ternyata tidak ada motif apapun di balik semua kata-kata ataupun tindakannya.
Saya juga belajar bahwa ternyata masih tersisa kemampuan untuk mencintai dan menyayangi seseorang dengan sungguh-sungguh. Setelah kegagalan saya di relasi terakhir, tak pelak otak dan logika seolah berkata bahwa saya tidak lagi mampu mencintai. Semua berondongan ejekan, hinaan, dan tuduhan-tuduhan buruk seolah masuk merasuk ke dalam hati dan pikiran, membuat saya merasa bahwa semua itu benar. Apakah masih ada orang yang sanggup menyayangi saya? Itulah pemikiran yang selalu terbayang, selalu melayang menutupi akal sehat.
 Mungkin, saya memang masih harus banyak belajar mengenai segala macam hubungan, relasi, dan masalah hati. Mungkin, saya masih diberikan banyak waktu untuk belajar lebih banyak. Maka dari itu, Yang Di Atas belum memberi saya kelulusan dan garis finish pencarian saya akan pelabuhan terakhir. Bukankah itu sejalan dengan misi hidup saya? Misi hidup untuk selalu belajar, belajar, dan belajar. Yah, anggap saja bahwa ini salah satu pengabulan doa saya untuk tidak pernah berhenti belajar. Semua itu kelas, semua itu mata pelajaran. Lulus dari satu kelas, masih terbuka kemungkinan untuk melanjutkan di kelas yang lain. Saat ini, saya sepertinya masih diberi banyak sekali SKS hidup, untuk terus mendalami misteri-misteri sosial yang ada.
Mungkin, saya memang masih harus banyak belajar mengenai segala macam hubungan, relasi, dan masalah hati. Mungkin, saya masih diberikan banyak waktu untuk belajar lebih banyak. Maka dari itu, Yang Di Atas belum memberi saya kelulusan dan garis finish pencarian saya akan pelabuhan terakhir. Bukankah itu sejalan dengan misi hidup saya? Misi hidup untuk selalu belajar, belajar, dan belajar. Yah, anggap saja bahwa ini salah satu pengabulan doa saya untuk tidak pernah berhenti belajar. Semua itu kelas, semua itu mata pelajaran. Lulus dari satu kelas, masih terbuka kemungkinan untuk melanjutkan di kelas yang lain. Saat ini, saya sepertinya masih diberi banyak sekali SKS hidup, untuk terus mendalami misteri-misteri sosial yang ada.
Tidakkah saya rindu untuk melabuhkan diri? Tentu saja jawabannya adalah iya. Tetapi saya ingin sekali mencari dan menemukan pelabuhan terakhir itu, pelabuhan di mana kapal saya bisa terikat dan langkah di atas bumi bisa segera diayunkan. Tidak ada yang lebih sakit daripada mengalami pelabuhan sementara. Ilusi yang lebih menusuk dibanding sebilah pedang, ketika terlihat sebuah pelabuhan yang seolah nyaman dan mengundang. Ketika sudah berlabuh, ternyata karena satu dan lain hal layar harus kembali dikembangkan. Dan pelabuhan itu tidak lagi bersahabat untuk kembali dikunjungi.
Syukurlah sebuah pelabuhan ilusi berhasil dihindari sebelum saya sempat berlabuh dan meregangkan otot. Selalu ada hikmah dari setiap luka yang tergores. Selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari. Dan kelas tidak akan pernah berhenti.
Rasa-rasanya itulah yang coba saya tanamkan dalam otak dan benak belakangan ini, sebuah percobaan untuk menghibur diri sendiri dari satu peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Lagi-lagi saya menjadi korban permainan paling kejam di dunia ini, permainan cinta dan hati. Entah mengapa, saya yang oleh banyak teman digelari sebagai seorang strategis dan manipulator handal selalu menemui kekalahan dalam permainan ini. Entahlah....
Jika pada kejatuhan-kejatuhan kemarin, saya terfokus pada segala hal yang buruk dan negatif, saat ini saya mencoba hanya melihat hikmahnya saja. Setidaknya, saya belajar kembali untuk membaca semua tindakan secara positif, tanpa ada motif apapun di baliknya. Dua kali berpacaran dengan drama queen mau tidak mau membuat saya selalu curiga dengan segala macam tindakan. Yah, kali ini walaupun ujung-ujungnya saya tetap disakiti dan dikecewakan, ternyata tidak ada motif apapun di balik semua kata-kata ataupun tindakannya.
Saya juga belajar bahwa ternyata masih tersisa kemampuan untuk mencintai dan menyayangi seseorang dengan sungguh-sungguh. Setelah kegagalan saya di relasi terakhir, tak pelak otak dan logika seolah berkata bahwa saya tidak lagi mampu mencintai. Semua berondongan ejekan, hinaan, dan tuduhan-tuduhan buruk seolah masuk merasuk ke dalam hati dan pikiran, membuat saya merasa bahwa semua itu benar. Apakah masih ada orang yang sanggup menyayangi saya? Itulah pemikiran yang selalu terbayang, selalu melayang menutupi akal sehat.
 Mungkin, saya memang masih harus banyak belajar mengenai segala macam hubungan, relasi, dan masalah hati. Mungkin, saya masih diberikan banyak waktu untuk belajar lebih banyak. Maka dari itu, Yang Di Atas belum memberi saya kelulusan dan garis finish pencarian saya akan pelabuhan terakhir. Bukankah itu sejalan dengan misi hidup saya? Misi hidup untuk selalu belajar, belajar, dan belajar. Yah, anggap saja bahwa ini salah satu pengabulan doa saya untuk tidak pernah berhenti belajar. Semua itu kelas, semua itu mata pelajaran. Lulus dari satu kelas, masih terbuka kemungkinan untuk melanjutkan di kelas yang lain. Saat ini, saya sepertinya masih diberi banyak sekali SKS hidup, untuk terus mendalami misteri-misteri sosial yang ada.
Mungkin, saya memang masih harus banyak belajar mengenai segala macam hubungan, relasi, dan masalah hati. Mungkin, saya masih diberikan banyak waktu untuk belajar lebih banyak. Maka dari itu, Yang Di Atas belum memberi saya kelulusan dan garis finish pencarian saya akan pelabuhan terakhir. Bukankah itu sejalan dengan misi hidup saya? Misi hidup untuk selalu belajar, belajar, dan belajar. Yah, anggap saja bahwa ini salah satu pengabulan doa saya untuk tidak pernah berhenti belajar. Semua itu kelas, semua itu mata pelajaran. Lulus dari satu kelas, masih terbuka kemungkinan untuk melanjutkan di kelas yang lain. Saat ini, saya sepertinya masih diberi banyak sekali SKS hidup, untuk terus mendalami misteri-misteri sosial yang ada.Tidakkah saya rindu untuk melabuhkan diri? Tentu saja jawabannya adalah iya. Tetapi saya ingin sekali mencari dan menemukan pelabuhan terakhir itu, pelabuhan di mana kapal saya bisa terikat dan langkah di atas bumi bisa segera diayunkan. Tidak ada yang lebih sakit daripada mengalami pelabuhan sementara. Ilusi yang lebih menusuk dibanding sebilah pedang, ketika terlihat sebuah pelabuhan yang seolah nyaman dan mengundang. Ketika sudah berlabuh, ternyata karena satu dan lain hal layar harus kembali dikembangkan. Dan pelabuhan itu tidak lagi bersahabat untuk kembali dikunjungi.
Syukurlah sebuah pelabuhan ilusi berhasil dihindari sebelum saya sempat berlabuh dan meregangkan otot. Selalu ada hikmah dari setiap luka yang tergores. Selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari. Dan kelas tidak akan pernah berhenti.
Published on November 16, 2014 03:10
November 12, 2014
Mantan Terindah
You never forget your first. And maybe that’s the reason why I can never erase you from my memory, from my brain. But really, who can easily forget their first relationship?
‘Tir’, that’s how I always refer to you. That nickname always invokes an image of a girl with oversized frisbee as her weapon, a female fighter from Soul Calibur series. Ahaha, such a typical geeky reference, isn’t it? But didn’t we have those gaming moments together? Those were the times when you kind of breaking my confidence (and my winning streak) in Tekken 5 and Soul Calibur 3. How often can a man share his video game moments with his significant other (not to mention being beaten repeatedly)?
I got back at you by showing up in front of your door, carrying in my hand a bouquet of white and yellow roses. Your expression at that time was just too precious to forget. I could even see a big question mark formed on your forehead, along with your shaky voice and trembling hands. It was the night when I finally got enough courage to ask you to walk our life together.
But if I have to be very honest now, please allow me to confess. You were beautiful to me for erasing my doubt then. Recalling those years, I really had massive hesitation to be in a relationship. Before you, I was this close to go steady with a girl I met in my class. My heart said that having a relationship before going for my master study was a stupid decision. That was why I didn’t follow up the approach with her. You, Tir, was a different case. You had me at our first meeting; you trapped me in that gentle hug and sweet conversation. Those things culminated in that very night, inside the roses.
I came with my share of baggage, a gigantic memory from my first love, terrible moments from several months before I met you, and my family problem. They always scared people off, both before and after you. It didn’t happen with you, though. You seemed to handle everything normally, even made it easier for me to deal with them. We understood each other, also in being a social butterfly. Hanging out with our friends never seem to cause any problem for both of us. Nobody felt neglected, we understand the concept of our own times and private spaces.
With all those, I naturally thought that we would last. No. We were still young and stupid back then. You are my first; I am also your first. We couldn’t handle all those emotional roller coasters, all the turmoil and frictions. Both of our naïve minds called it off on Christmas Eve. (And today I just read that Agnetha and Benny from ABBA also splited up on Christmas Eve. Well, maybe nothing significant, just my random mind wandering around)
After the separation, we still retain that chemistry. You were there, in my every relationship and in their demise. You were hurt every time, and I am sorry for that. It was never of my intention to hurt you. Every time we tried to rekindle the flame, I was always the one putting that off. Maybe I am the bastard of our connection, constantly grafting new scars in you. Maybe you won’t believe me again when I said that it was unintentional. But you were always there. How can I not be moved?
Each and every time, you can always lift me up again. We may walk our own road right now, with no light of meeting up again; but you were always there to cheer me. In your own way, in your own time. How can I forget our conversation of Marcell’s song? How can I forget our skype sessions?
Last night, you were there when I was down. You provided me with ears to listen, you gave me a virtual lap when I can sleep on for a while, and you provided me with the warmth I need in this cold winter, cold heart, cold soul. I was able to finally sleep in peace, knowing that there was one thing I did right in the past. You. Yes, you.
Talking to you is slapping me with some senses, that at least for one person, I was precious. Instead of wiping off my tears from heartbroken, you instilled laughter in my heart. It was fun. You made everything fun. Or should I say, you made fun of everything. And it worked!!!
This morning, as I woke up from my slumber, one song came to mind. Mantan Terindah. And it reminds me of you.
So I wrote this for you, a small gratitude of what you’ve done to me…..
‘Tir’, that’s how I always refer to you. That nickname always invokes an image of a girl with oversized frisbee as her weapon, a female fighter from Soul Calibur series. Ahaha, such a typical geeky reference, isn’t it? But didn’t we have those gaming moments together? Those were the times when you kind of breaking my confidence (and my winning streak) in Tekken 5 and Soul Calibur 3. How often can a man share his video game moments with his significant other (not to mention being beaten repeatedly)?

I got back at you by showing up in front of your door, carrying in my hand a bouquet of white and yellow roses. Your expression at that time was just too precious to forget. I could even see a big question mark formed on your forehead, along with your shaky voice and trembling hands. It was the night when I finally got enough courage to ask you to walk our life together.
But if I have to be very honest now, please allow me to confess. You were beautiful to me for erasing my doubt then. Recalling those years, I really had massive hesitation to be in a relationship. Before you, I was this close to go steady with a girl I met in my class. My heart said that having a relationship before going for my master study was a stupid decision. That was why I didn’t follow up the approach with her. You, Tir, was a different case. You had me at our first meeting; you trapped me in that gentle hug and sweet conversation. Those things culminated in that very night, inside the roses.
I came with my share of baggage, a gigantic memory from my first love, terrible moments from several months before I met you, and my family problem. They always scared people off, both before and after you. It didn’t happen with you, though. You seemed to handle everything normally, even made it easier for me to deal with them. We understood each other, also in being a social butterfly. Hanging out with our friends never seem to cause any problem for both of us. Nobody felt neglected, we understand the concept of our own times and private spaces.
With all those, I naturally thought that we would last. No. We were still young and stupid back then. You are my first; I am also your first. We couldn’t handle all those emotional roller coasters, all the turmoil and frictions. Both of our naïve minds called it off on Christmas Eve. (And today I just read that Agnetha and Benny from ABBA also splited up on Christmas Eve. Well, maybe nothing significant, just my random mind wandering around)
After the separation, we still retain that chemistry. You were there, in my every relationship and in their demise. You were hurt every time, and I am sorry for that. It was never of my intention to hurt you. Every time we tried to rekindle the flame, I was always the one putting that off. Maybe I am the bastard of our connection, constantly grafting new scars in you. Maybe you won’t believe me again when I said that it was unintentional. But you were always there. How can I not be moved?
Each and every time, you can always lift me up again. We may walk our own road right now, with no light of meeting up again; but you were always there to cheer me. In your own way, in your own time. How can I forget our conversation of Marcell’s song? How can I forget our skype sessions?
Last night, you were there when I was down. You provided me with ears to listen, you gave me a virtual lap when I can sleep on for a while, and you provided me with the warmth I need in this cold winter, cold heart, cold soul. I was able to finally sleep in peace, knowing that there was one thing I did right in the past. You. Yes, you.
Talking to you is slapping me with some senses, that at least for one person, I was precious. Instead of wiping off my tears from heartbroken, you instilled laughter in my heart. It was fun. You made everything fun. Or should I say, you made fun of everything. And it worked!!!
This morning, as I woke up from my slumber, one song came to mind. Mantan Terindah. And it reminds me of you.
So I wrote this for you, a small gratitude of what you’ve done to me…..
Published on November 12, 2014 01:59
November 10, 2014
Days of Cursing
Sometimes I cannot help thinking that in the race of love and romance, I will always finish last.
Maybe it's my confidence issue, maybe it's the baggage I've carried since my childhood, or maybe it's just my terrible luck. I don't know.....
 Is this the payback for all my academic opportunities? I used to think that it's okay to be devoid of love as long as I can advance in academia; but what I meant was me being unable to feel love within. The love deprivation that I have now is just too torturing, constantly being in a roller-coaster of emotion; of love and hatred; of adrenaline rush and tear shedding.
Is this the payback for all my academic opportunities? I used to think that it's okay to be devoid of love as long as I can advance in academia; but what I meant was me being unable to feel love within. The love deprivation that I have now is just too torturing, constantly being in a roller-coaster of emotion; of love and hatred; of adrenaline rush and tear shedding.
Back in the past, I was thinking of swearing off love and relationship. Yet Big Boss is such a big fat joker, He kept making me falling in love, getting my hope up high, and suddenly... BAMM! I was tossed to the ground from such height.
Maybe once is okay, maybe twice is still tolerable, but repeatedly? REPEATEDLY? Will I even have enough energy to pick up my pieces every time?
I don't know. Even this writing is all over the place, such an incoherent composition.
I hate your jokes, dear Big Boss!!!!
Maybe it's my confidence issue, maybe it's the baggage I've carried since my childhood, or maybe it's just my terrible luck. I don't know.....
 Is this the payback for all my academic opportunities? I used to think that it's okay to be devoid of love as long as I can advance in academia; but what I meant was me being unable to feel love within. The love deprivation that I have now is just too torturing, constantly being in a roller-coaster of emotion; of love and hatred; of adrenaline rush and tear shedding.
Is this the payback for all my academic opportunities? I used to think that it's okay to be devoid of love as long as I can advance in academia; but what I meant was me being unable to feel love within. The love deprivation that I have now is just too torturing, constantly being in a roller-coaster of emotion; of love and hatred; of adrenaline rush and tear shedding.Back in the past, I was thinking of swearing off love and relationship. Yet Big Boss is such a big fat joker, He kept making me falling in love, getting my hope up high, and suddenly... BAMM! I was tossed to the ground from such height.
Maybe once is okay, maybe twice is still tolerable, but repeatedly? REPEATEDLY? Will I even have enough energy to pick up my pieces every time?
I don't know. Even this writing is all over the place, such an incoherent composition.
I hate your jokes, dear Big Boss!!!!
Published on November 10, 2014 02:27
October 15, 2014
Surat bagi diriku sendiri, 15 tahun yang lalu
Halo le,
Ini aku, kamu sendiri lima belas tahun yang akan datang. Aku membayangkan (dan mengingat) kamu pasti masih memakai baju seragam putih biru itu. Rasanya masih segar dalam ingatan, kemeja putih yang sudah berubah warna kekuning-kuningan dan celana pendek biru yang jahitan di bagian kanannya sudah sedikit robek. Iya, aku masih ingat celana seragam yang terlalu pendek itu, yang membuatmu banyak dihina orang-orang karena dianggap memamerkan keseksian paha. Padahal apanya sih yang seksi? Paha kecil kurus kering milik seorang anak kelas dua SMP? Seksi dari mana?
Dalam bayanganku, kau saat ini pasti sedang berjalan di jalan Juwadi, bagian belakang SMP 5 yang berdebu itu. Rambut ikalmu berantakan, kepala menunduk, dan kedua tangan menggenggam erat tas ranselmu. Masih kuingat, terlalu segar dalam ingatan dan takkan bisa terlupa. Kalau tidak salah ingat, saat itu kau menyenandungkan perlahan sebuah lagu yang kau tulis sendiri liriknya, lagu dengan irama yang tidak jelas juntrungannya. Tapi apa peduli kita pada kualitas melodinya? Kita hanya butuh berteriak, mengeluarkan apa yang ada di hati. “I’m in trouble, I have a problem, please my Lord help me, give me a way!” Kira-kira begitu kan bunyi refren lagu itu?
Kau saat itu sedang bertanya-tanya, beranikah dirimu melompat ke tengah jalan di saat sebuah bus kota melintas. Beranikah kau mengakhiri hidupmu sendiri? Dan masih banyak sekali alternatif bunuh diri lain yang berkelebat dalam otakmu. Aku tahu, pasti banyak orang yang membaca ini akan berpikir bahwa kau tak lebih dari seorang pengecut yang tak berani menghadapi kerasnya hidup. Dan aku ingat, kau juga pernah berpikir seperti itu, bahwa kau tak lebih dari seorang pengecut tanpa keberanian.
Seandainya aku bisa berada di sana, bisa berada di saat itu, aku pasti akan menepuk-nepuk pundakmu. Hanya itu yang kau inginkan, hanya itu yang kau butuhkan. Seseorang yang tahu bagaimana rasanya menjadi seorang yang tidak diharapkan, yang selalu kenyang dengan hinaan sehari-hari. Kau butuh menangis keras, sesuatu yang tidak pernah berani kau lakukan di saat itu. Dengan hinaan “banci” yang disematkan karena kau tidak bermain bola, tidak mendengarkan musik-musik mainstream di saat itu, menangis menurutmu hanya akan membuatmu menjadi lebih tidak lelaki. Tapi kau butuh melakukannya, kau butuh menangis dan mendengar kata-kata, “Semuanya akan baik-baik saja di masa depan!”
Aku ingin sekali bisa memberikanmu kata-kata itu, menjanjikan bahwa semua akan baik-baik saja, menunjukkan bahwa akhirnya kau akan bisa keluar dari stigma ‘berbeda’ dan hidup seperti orang-orang yang lain. Tapi kenyataan yang ada tidak seperti itu, doel.
Sampai kapanpun, kamu akan selalu berbeda. Kamu itu unik, doel, berbeda dengan teman-temanmu yang lain. Bahkan sekarang, lima belas tahun setelah tahun-tahun mengerikan itu, kamu masih berbeda dengan mereka semua. Tapi semua yang kamu alami itu akan membuatmu lebih kuat, membuatmu mampu bertahan dalam banyak hal. Jangan menyerah, karena aku tahu kamu akan bertahan (kalau tidak, bagaimana mungkin surat ini datang padamu?).
Bully tidak pernah hilang, le. Mereka akan selalu ada, selalu menghadangmu di depan. Mereka hanya berubah bentuk, mereka hanya berubah rupa dan suara. Tapi kamu sudah pernah mengalaminya, sudah ditempa dengan kuat untuk melaluinya. Akan tiba waktunya ketika kamu menyadari bahwa seharusnya kamulah yang harus mengasihani mereka; atas kelemahan mereka.
Kalau meminjam kata-kata Yesus di Alkitab (jangan khawatir, doel, kamu tidak akan tumbuh menjadi manusia super religius kok!), semakin bagus anggur yang dihasilkan, semakin keras pula tekanan yang diberikan. Tekanan-tekanan yang diberikan padamu justru membuatmu bekerja semakin keras, karena ingin membuktikan dirimu sendiri.
Aku ingat bahwa kamu pernah (atau mungkin sedang) mencoba menjadi bagian dari mereka. Kamu bangun di pagi-pagi buta demi menonton pertandingan demi pertandingan Fiorentia, kamu memelototi semua berita olahraga dan sepak bola di koran setiap pagi, bahkan berusaha menghafal semua nama-nama pemain bola yang asing itu dari majalah Liga Italia dan Liga Inggris. Semua hanya demi bisa bercakap-cakap dengan teman-teman sekelasmu kan? Padahal kamu tidak pernah benar-benar menikmatinya. Hanya membuat batinmu tersiksa. Atau ketika kamu membeli sebuah bola bersama-sama dengan empat empat teman yang lain, memaksa diri bermain bola (walaupun sebenarnya kamu hanya ingin duduk di kelas dan lanjut membaca Animorphs), bahkan ikut tim kelas dan berdiri di lapangan menjadi bek (yang bahkan kamu sendiri tidak tahu harus melakukan apa).
Jangan khawatir atas kegagalanmu masuk dan ‘berubah’. Justru kalau kamu berubah, selalu berubah, semua tidak akan pernah selesai. Tuntutan sosial dan masyarakat selalu berganti, dan kamu hanya akan kehilangan dirimu sendiri. Jangan khawatir, pada waktunya kamu justru akan melihat betapa mereka sesungguhnya adalah korban konstruksi sosial, korban-korban yang terperangkap dan tidak bisa keluar dari tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal. Di saat itulah, rasa kasihan akan membuncah dan sedikit banyak kau akan lega atas semua pencerahanmu.
Yang kuat, le! Pada saatnya, kamu akan membantu orang-orang sepertimu, seperti kita. Tanpa pengalaman ini, kamu tidak akan bisa memahami mereka. Dan kita tahu, yang mereka butuhkan hanya dipahami, hanya tempat yang aman. Kita membantu dan pada saat yang sama kita juga dibantu.
SMP cuma tiga tahun kok. Setelah itu, masa SMA tidak akan seburuk yang kamu bayangkan. Kamu akan bertemu banyak teman-teman yang membantumu melihat dunia. Masa SMA-mu akan cukup berbeda, tidak seperti yang kau baca dan tonton. Lepas dari tiga tahun di SMA, kamu akan menemukan banyak teman dan sahabat –orang-orang yang tidak akan mempermasalahkan keunikan-keunikan dirimu.
Doel, kamu akan bisa melihat dunia lebih banyak daripada teman-temanmu itu. Kamu akan pergi jauh, memperoleh perspektif baru, dan berkelana. Surat ini pun tidak kutulis dari Indonesia, doel! Bukan kaya harta, tahta, atau wanita, kamu akan menemukan kebebasan yang lebih berharga dari semua itu. Dunia tidak hanya selebar SMP 5 atau Kotabaru, dunia tidak hanya seluas kota Yogya, atau bahkan Indonesia. Bermimpilah, karena mimpi-mimpimu itu yang akan menjadi sayapmu, mengepak jauh pergi. Saat kau melayang, akan kau sadari betapa orang-orang itu tidak lebih besar dari semut hitam…….
Ini aku, kamu sendiri lima belas tahun yang akan datang. Aku membayangkan (dan mengingat) kamu pasti masih memakai baju seragam putih biru itu. Rasanya masih segar dalam ingatan, kemeja putih yang sudah berubah warna kekuning-kuningan dan celana pendek biru yang jahitan di bagian kanannya sudah sedikit robek. Iya, aku masih ingat celana seragam yang terlalu pendek itu, yang membuatmu banyak dihina orang-orang karena dianggap memamerkan keseksian paha. Padahal apanya sih yang seksi? Paha kecil kurus kering milik seorang anak kelas dua SMP? Seksi dari mana?
Dalam bayanganku, kau saat ini pasti sedang berjalan di jalan Juwadi, bagian belakang SMP 5 yang berdebu itu. Rambut ikalmu berantakan, kepala menunduk, dan kedua tangan menggenggam erat tas ranselmu. Masih kuingat, terlalu segar dalam ingatan dan takkan bisa terlupa. Kalau tidak salah ingat, saat itu kau menyenandungkan perlahan sebuah lagu yang kau tulis sendiri liriknya, lagu dengan irama yang tidak jelas juntrungannya. Tapi apa peduli kita pada kualitas melodinya? Kita hanya butuh berteriak, mengeluarkan apa yang ada di hati. “I’m in trouble, I have a problem, please my Lord help me, give me a way!” Kira-kira begitu kan bunyi refren lagu itu?
Kau saat itu sedang bertanya-tanya, beranikah dirimu melompat ke tengah jalan di saat sebuah bus kota melintas. Beranikah kau mengakhiri hidupmu sendiri? Dan masih banyak sekali alternatif bunuh diri lain yang berkelebat dalam otakmu. Aku tahu, pasti banyak orang yang membaca ini akan berpikir bahwa kau tak lebih dari seorang pengecut yang tak berani menghadapi kerasnya hidup. Dan aku ingat, kau juga pernah berpikir seperti itu, bahwa kau tak lebih dari seorang pengecut tanpa keberanian.
Seandainya aku bisa berada di sana, bisa berada di saat itu, aku pasti akan menepuk-nepuk pundakmu. Hanya itu yang kau inginkan, hanya itu yang kau butuhkan. Seseorang yang tahu bagaimana rasanya menjadi seorang yang tidak diharapkan, yang selalu kenyang dengan hinaan sehari-hari. Kau butuh menangis keras, sesuatu yang tidak pernah berani kau lakukan di saat itu. Dengan hinaan “banci” yang disematkan karena kau tidak bermain bola, tidak mendengarkan musik-musik mainstream di saat itu, menangis menurutmu hanya akan membuatmu menjadi lebih tidak lelaki. Tapi kau butuh melakukannya, kau butuh menangis dan mendengar kata-kata, “Semuanya akan baik-baik saja di masa depan!”
Aku ingin sekali bisa memberikanmu kata-kata itu, menjanjikan bahwa semua akan baik-baik saja, menunjukkan bahwa akhirnya kau akan bisa keluar dari stigma ‘berbeda’ dan hidup seperti orang-orang yang lain. Tapi kenyataan yang ada tidak seperti itu, doel.
Sampai kapanpun, kamu akan selalu berbeda. Kamu itu unik, doel, berbeda dengan teman-temanmu yang lain. Bahkan sekarang, lima belas tahun setelah tahun-tahun mengerikan itu, kamu masih berbeda dengan mereka semua. Tapi semua yang kamu alami itu akan membuatmu lebih kuat, membuatmu mampu bertahan dalam banyak hal. Jangan menyerah, karena aku tahu kamu akan bertahan (kalau tidak, bagaimana mungkin surat ini datang padamu?).
Bully tidak pernah hilang, le. Mereka akan selalu ada, selalu menghadangmu di depan. Mereka hanya berubah bentuk, mereka hanya berubah rupa dan suara. Tapi kamu sudah pernah mengalaminya, sudah ditempa dengan kuat untuk melaluinya. Akan tiba waktunya ketika kamu menyadari bahwa seharusnya kamulah yang harus mengasihani mereka; atas kelemahan mereka.
Kalau meminjam kata-kata Yesus di Alkitab (jangan khawatir, doel, kamu tidak akan tumbuh menjadi manusia super religius kok!), semakin bagus anggur yang dihasilkan, semakin keras pula tekanan yang diberikan. Tekanan-tekanan yang diberikan padamu justru membuatmu bekerja semakin keras, karena ingin membuktikan dirimu sendiri.
Aku ingat bahwa kamu pernah (atau mungkin sedang) mencoba menjadi bagian dari mereka. Kamu bangun di pagi-pagi buta demi menonton pertandingan demi pertandingan Fiorentia, kamu memelototi semua berita olahraga dan sepak bola di koran setiap pagi, bahkan berusaha menghafal semua nama-nama pemain bola yang asing itu dari majalah Liga Italia dan Liga Inggris. Semua hanya demi bisa bercakap-cakap dengan teman-teman sekelasmu kan? Padahal kamu tidak pernah benar-benar menikmatinya. Hanya membuat batinmu tersiksa. Atau ketika kamu membeli sebuah bola bersama-sama dengan empat empat teman yang lain, memaksa diri bermain bola (walaupun sebenarnya kamu hanya ingin duduk di kelas dan lanjut membaca Animorphs), bahkan ikut tim kelas dan berdiri di lapangan menjadi bek (yang bahkan kamu sendiri tidak tahu harus melakukan apa).
Jangan khawatir atas kegagalanmu masuk dan ‘berubah’. Justru kalau kamu berubah, selalu berubah, semua tidak akan pernah selesai. Tuntutan sosial dan masyarakat selalu berganti, dan kamu hanya akan kehilangan dirimu sendiri. Jangan khawatir, pada waktunya kamu justru akan melihat betapa mereka sesungguhnya adalah korban konstruksi sosial, korban-korban yang terperangkap dan tidak bisa keluar dari tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal. Di saat itulah, rasa kasihan akan membuncah dan sedikit banyak kau akan lega atas semua pencerahanmu.
Yang kuat, le! Pada saatnya, kamu akan membantu orang-orang sepertimu, seperti kita. Tanpa pengalaman ini, kamu tidak akan bisa memahami mereka. Dan kita tahu, yang mereka butuhkan hanya dipahami, hanya tempat yang aman. Kita membantu dan pada saat yang sama kita juga dibantu.
SMP cuma tiga tahun kok. Setelah itu, masa SMA tidak akan seburuk yang kamu bayangkan. Kamu akan bertemu banyak teman-teman yang membantumu melihat dunia. Masa SMA-mu akan cukup berbeda, tidak seperti yang kau baca dan tonton. Lepas dari tiga tahun di SMA, kamu akan menemukan banyak teman dan sahabat –orang-orang yang tidak akan mempermasalahkan keunikan-keunikan dirimu.
Doel, kamu akan bisa melihat dunia lebih banyak daripada teman-temanmu itu. Kamu akan pergi jauh, memperoleh perspektif baru, dan berkelana. Surat ini pun tidak kutulis dari Indonesia, doel! Bukan kaya harta, tahta, atau wanita, kamu akan menemukan kebebasan yang lebih berharga dari semua itu. Dunia tidak hanya selebar SMP 5 atau Kotabaru, dunia tidak hanya seluas kota Yogya, atau bahkan Indonesia. Bermimpilah, karena mimpi-mimpimu itu yang akan menjadi sayapmu, mengepak jauh pergi. Saat kau melayang, akan kau sadari betapa orang-orang itu tidak lebih besar dari semut hitam…….
Published on October 15, 2014 21:47
October 7, 2014
Lamunan Pagi Hari
Pagi ini, playlist musik yang biasa menemani perjalananku ke kampus mengkhianatiku. Alih-alih mencerahkan awal hari, ia berturut-turut memainkan lagu-lagu yang sempat menjadi musik pengiring patah hati di masa lalu.
Lagu pertama, ‘Heart Vacancy’ dari The Wanted mengingatkanku pada masa-masa patah hatiku yang pertama, pada sebuah musim dingin jauh di Inggris sana. Dalam kesendirian musim dingin, ketika hampir semua teman asrama pulang ke rumah mereka masing-masing, lagu ini seolah menjadi sebuah lorong dan jalan keluar bagi semua emosi negatif. Seorang sahabat dari Indonesia, seorang penyiar radio pada masa itu, mengirimkan lagu ini setelah mendengar cerita pengalaman gagalnya hubungan pertamaku. Tak disangka tak dinyana, aku menjadi sangat terikat pada melodi dan lirik yang ada di dalamnya.
Kupikir cukup satu lagu ini saja yang akan muncul di playlist. Entah kenapa, telepon genggamku seolah ingin melemparku kembali ke dalam gelapnya masa lalu dan memutar ‘Payphone’ dari Maroon 5. Sial, pikirku. Lagu ini kembali membawaku ke dalam kemarahan besar pada kegagalan keduaku. Marah, murka, dan kecewa. Mungkin itu tiga kata yang cocok menggambarkan apa yang kualami pada saat itu.
Kurang ajar, pikirku! Kenapa aku diberondong luapan-luapan emosi yang ingin kulupakan di pagi hari? Lagu selanjutnya yang dimainkan memang sudah tidak lagi berhubungan dengan masa lalu, tapi benak dan pikirku sudah terlanjur terperangkap dalam lubang hitam kenangan. Sebuah pikiran lalu melayang dan muncul, lagu apa lagi yang mungkin muncul? Bodoh bukan? Bukannya mencoba untuk melangkah ke hari yang lebih cerah, aku justru memperangkap diri sendiri dengan berkubang di dalam lumpur memori.
Bus-ku saat itu sedang melintas di dekat Galaxy Macau. Di sana terlihat sebuah pagar sekolah, Guang Da Middle School. Otakku yang terlalu banyak berpikir langsung terpusat pada salah satu karakter cina yang ada di sana, 光 (Guang). Sebuah karakter biasa yang berarti cahaya. Tapi otak ini langsung teringat dengan nama seorang penyanyi, Guang Liang. Di waktu itulah, sebuah judul lagu dari Guang Liang muncul dalam benak, ‘Yue Ding’.
Beginilah nasib orang dengan benak yang tak pernah berhenti berpikir. Sedikit saja pemicu terlihat, sang benak akan terus berlari tak tentu arah mencari dan menyambar, menyulut api bagi rangkaian-rangkaian peristiwa dan pikiran. Lagu itu tidak pernah punya makna bagiku saat ia baru saja muncul. Baru di tahun 2009, lagu itu menempel dalam benak.
‘Kampret’, sebut saja begitu, adalah seseorang yang sempat menempati kursi khusus dalam hatiku di tahun itu. Kami pernah berangan-angan bersama akan masa depan yang mungkin terjadi, yang mungkin dapat kami jalani berdua. Tetapi, sebuah halangan yang menghadang di depan kami saat itu adalah mimpi kami berdua untuk dapat melanjutkan studi ke luar negeri, Salah satu kekhawatiran yang ia ungkapkan adalah bahwa jarak dan waktu akan memisahkan kami pada saat studi lanjut. Inilah bagian dimana lagu ‘Yue Ding’ menjadi sangat berkesan.
Lagu itu bercerita mengenai sepasang kekasih yang berpisah dan berjanji untuk bertemu lagi tiga tahun kemudian. Setidaknya, salah satu dari pasangan itu masih setia menunggu, masih mengingat janjinya, dan bergeming di tempat yang sama. Studi lanjut kami diprediksikan selama dua tahun, setidaknya. Apakah kami sanggup menjalani perpisahan selama dua tahun? Aku selalu meyakinkan diriku dan dirinya dengan lagu itu, bahwa ada orang yang sanggup menjalani semuanya.
Takdir ternyata berkata lain. Dalam hitungan bulan, banyak sekali yang terjadi. Puncak semuanya terjadi ketika si ‘kampret’ menghilang, pindah dari Yogya tanpa kata pamit. Beberapa kali upaya untuk menyambung komunikasi kembali selalu gagal. Aku akhirnya mendapatkan jalan untuk melanjutkan studi ke Inggris, sementara ia (setahun setelahku) mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya ke Belanda.
Tak dinyana, jalan kami bertemu lagi di tahun 2013. Secara tidak sengaja, kami berdua bertemu di sebuah warung tegal di Jakarta. Siapa yang pernah menyangka dan berpikir bahwa pertemuan itu akan terjadi di sebuah kota lain, di sebuah warung kecil yang tidak terkenal. Entah mengapa, lirik dari lagu ‘Yue Ding’ itu benar-benar terjadi. Setelah tiga tahun, kami kembali bertemu dan menyelesaikan semuanya.
Penyelesaian? Di masa lalu, perpisahan kami tidak ditandai dengan kata-kata apapun, tidak ada kata pamit atau selesai. Semua hanya berputar dalam benak saja. Tahu sama tahu, Tetapi tiga tahun berselang, semua akhirnya benar-benar jelas. Semua kemarahan, semua perasaan sayang, dan semua mimpi yang pernah kami pendam berdua akhirnya benar-benar disegel dengan sebuah kata ‘TAMAT’.
Lamunanku berakhir ketika speaker di dalam bus berteriak, menandakan pemberhentianku sudah dekat. Lamunan dan permenungan yang cukup panjang dari sebuah otak yang cukup ‘random’.
Ah, lagu ajaib itu… Lagu yang benar-benar terjadi dalam hidup…
Lagu pertama, ‘Heart Vacancy’ dari The Wanted mengingatkanku pada masa-masa patah hatiku yang pertama, pada sebuah musim dingin jauh di Inggris sana. Dalam kesendirian musim dingin, ketika hampir semua teman asrama pulang ke rumah mereka masing-masing, lagu ini seolah menjadi sebuah lorong dan jalan keluar bagi semua emosi negatif. Seorang sahabat dari Indonesia, seorang penyiar radio pada masa itu, mengirimkan lagu ini setelah mendengar cerita pengalaman gagalnya hubungan pertamaku. Tak disangka tak dinyana, aku menjadi sangat terikat pada melodi dan lirik yang ada di dalamnya.
Kupikir cukup satu lagu ini saja yang akan muncul di playlist. Entah kenapa, telepon genggamku seolah ingin melemparku kembali ke dalam gelapnya masa lalu dan memutar ‘Payphone’ dari Maroon 5. Sial, pikirku. Lagu ini kembali membawaku ke dalam kemarahan besar pada kegagalan keduaku. Marah, murka, dan kecewa. Mungkin itu tiga kata yang cocok menggambarkan apa yang kualami pada saat itu.
Kurang ajar, pikirku! Kenapa aku diberondong luapan-luapan emosi yang ingin kulupakan di pagi hari? Lagu selanjutnya yang dimainkan memang sudah tidak lagi berhubungan dengan masa lalu, tapi benak dan pikirku sudah terlanjur terperangkap dalam lubang hitam kenangan. Sebuah pikiran lalu melayang dan muncul, lagu apa lagi yang mungkin muncul? Bodoh bukan? Bukannya mencoba untuk melangkah ke hari yang lebih cerah, aku justru memperangkap diri sendiri dengan berkubang di dalam lumpur memori.
Bus-ku saat itu sedang melintas di dekat Galaxy Macau. Di sana terlihat sebuah pagar sekolah, Guang Da Middle School. Otakku yang terlalu banyak berpikir langsung terpusat pada salah satu karakter cina yang ada di sana, 光 (Guang). Sebuah karakter biasa yang berarti cahaya. Tapi otak ini langsung teringat dengan nama seorang penyanyi, Guang Liang. Di waktu itulah, sebuah judul lagu dari Guang Liang muncul dalam benak, ‘Yue Ding’.
Beginilah nasib orang dengan benak yang tak pernah berhenti berpikir. Sedikit saja pemicu terlihat, sang benak akan terus berlari tak tentu arah mencari dan menyambar, menyulut api bagi rangkaian-rangkaian peristiwa dan pikiran. Lagu itu tidak pernah punya makna bagiku saat ia baru saja muncul. Baru di tahun 2009, lagu itu menempel dalam benak.
‘Kampret’, sebut saja begitu, adalah seseorang yang sempat menempati kursi khusus dalam hatiku di tahun itu. Kami pernah berangan-angan bersama akan masa depan yang mungkin terjadi, yang mungkin dapat kami jalani berdua. Tetapi, sebuah halangan yang menghadang di depan kami saat itu adalah mimpi kami berdua untuk dapat melanjutkan studi ke luar negeri, Salah satu kekhawatiran yang ia ungkapkan adalah bahwa jarak dan waktu akan memisahkan kami pada saat studi lanjut. Inilah bagian dimana lagu ‘Yue Ding’ menjadi sangat berkesan.
Lagu itu bercerita mengenai sepasang kekasih yang berpisah dan berjanji untuk bertemu lagi tiga tahun kemudian. Setidaknya, salah satu dari pasangan itu masih setia menunggu, masih mengingat janjinya, dan bergeming di tempat yang sama. Studi lanjut kami diprediksikan selama dua tahun, setidaknya. Apakah kami sanggup menjalani perpisahan selama dua tahun? Aku selalu meyakinkan diriku dan dirinya dengan lagu itu, bahwa ada orang yang sanggup menjalani semuanya.
Takdir ternyata berkata lain. Dalam hitungan bulan, banyak sekali yang terjadi. Puncak semuanya terjadi ketika si ‘kampret’ menghilang, pindah dari Yogya tanpa kata pamit. Beberapa kali upaya untuk menyambung komunikasi kembali selalu gagal. Aku akhirnya mendapatkan jalan untuk melanjutkan studi ke Inggris, sementara ia (setahun setelahku) mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya ke Belanda.
Tak dinyana, jalan kami bertemu lagi di tahun 2013. Secara tidak sengaja, kami berdua bertemu di sebuah warung tegal di Jakarta. Siapa yang pernah menyangka dan berpikir bahwa pertemuan itu akan terjadi di sebuah kota lain, di sebuah warung kecil yang tidak terkenal. Entah mengapa, lirik dari lagu ‘Yue Ding’ itu benar-benar terjadi. Setelah tiga tahun, kami kembali bertemu dan menyelesaikan semuanya.
Penyelesaian? Di masa lalu, perpisahan kami tidak ditandai dengan kata-kata apapun, tidak ada kata pamit atau selesai. Semua hanya berputar dalam benak saja. Tahu sama tahu, Tetapi tiga tahun berselang, semua akhirnya benar-benar jelas. Semua kemarahan, semua perasaan sayang, dan semua mimpi yang pernah kami pendam berdua akhirnya benar-benar disegel dengan sebuah kata ‘TAMAT’.
Lamunanku berakhir ketika speaker di dalam bus berteriak, menandakan pemberhentianku sudah dekat. Lamunan dan permenungan yang cukup panjang dari sebuah otak yang cukup ‘random’.
Ah, lagu ajaib itu… Lagu yang benar-benar terjadi dalam hidup…
Published on October 07, 2014 20:42
October 31, 2013
Freirean Reading of Zombie
I am found guilty of watching tons of zombie movies, boththe crappy ones and the magnificent ones. It’s true, the repetition they portrayed is often cheesy and as uncreative as it can be. Furthermore, the zombieque culture becomes so huge and widespread that these undeads lost their charms. But why do I still watch (andhunt) those movies? Frankly speaking, these brain-eating brainless creatures brought about a sense of reminisce and nostalgic feeling for me.
It was started with the routine geek pajama parties I often held in my house with fellow geeks. Well, these chaps would certainly refuse the ‘geek’ label I used in this writing. Yet, what would you call four chaps having sleepovers for days only to play some video games? The year was 2001,back when the first Sony Play Station was still ruling and winning the third console war.
Some franchises stood out among the others, some titles flunked dramatically. One of the standing out franchises was Bio Hazard / Resident Evil. It became our challenge night by night, how to finish this thrilling silent game with sound effects amplified through gigantic room speaker in the darkness where the only light we had came from the TV screen and the green PSX LED. Ah, what a moment.
What is so special from the hordes of undead corpse flocking the world in search of fresh brains? They are less cool than their blood-sucking vampiric cousins, the perpetually seductive witches or the ever-furry werewolf neighbours. I don’t know. I honestly don’t know. The market was also saturated already with constant exposure to these rotting bodies.
Yet the key to understand zombies are the concept of bodies through body culture studies perspective. Body is defined by Maurice Merleau-Ponty (1968) as Flesh, the being, and the appearance of oneself. This conceptual flesh puts body as an integral part of the mind, consequently in unity with main drive of any action. The integration with a force of will thus placed body in the position of a subject, as meaning, and as embodied existence.
Butler (in Bodies ThatMatter, 1993) argued that body acts or performs its own subjectivity,devoid of any influence from constructed reality and expectation from surrounding society. The seclusion of subjectivity from any expectation thus signified ‘body’ as the core identity; initial identity. Furthermore, body is theorised as “matter”, so that the cultural norms that constitute its identity can be exposed, examined, and critique. This is the state of nakedness, a complete strip off where self identity is broken down into Democritus’ concept of atom,the state where further division is no longer possible.
Thus, the common concept of basic identity is the result of negotiation / dialogue between the materiality of body and the materiality of knowledge and language. Within this framework, each aspect is materialised;manifested into solid matter. The solidification of two parties creates real spatial context of dialogue between them. Taking the nature of knowledge and language as being able to be controlled by any person, the dialogal practice taking place here follows an ideal Bakhtinian dialogism. A horizontal power structure wherein no party dominates the other operates here, creating an ideal negotiation and neutral adjustment.
Different situation may happen when culture is included here, as the nature of culture sometimes forces any person to bestow before it,the conquering nature over any individual living within its authority. An inclusion of culture in the dialogal practice would turn the natural dialogue into cyborgization. Following Donna Haraway’s (1997) concept of post-humanism,culture and social norms posses the machinization ability; operates as a gigantic mother brain penetrating the skin of the fleshed out body and replacing the natural parts with mechanical prosthetic. However, in doing so,not all of the flesh parts are taken out, creating power struggle between the nature and the machine.
If we are taking an analogy of natural connection between flesh and knowledge and language into a man taking material and sew them into clothes, we can see that the skin still acts as a border between these two parties. Even though the unity between body and clothing can be seen, body will perform its own subjectivity to counter willful construction, in turn creates a clear distinction of constructional aspects. The difference here is the skin as a liminal field, the meeting point of body and construction. However, in the cyborgization, the skin is violated and instead being replaced by mechanical layers. The loss of liminal quality in the skin renders the construction aspects indistinguishable from the flesh.
The term power struggle consequently brings about the shift from horizontal dialogue into vertical dialogue; where one side reclaimed dominance over the others; Foucauldian scheme of war and oppression. Thestruggle between personal “body” and machinization
What about zombie? Using body cultural studies, we can scrutinise the implicit meaning behind dead ‘body’; dead ‘flesh’. What does it mean then? If (living) body can perform its own subjectivity, then zombie cannot perform their own subjectivity. Even though they are living, their freewill is taken from them. Without subjectivity, their main driving force, their main existence, and their very core are robbed. Interestingly, these zombies are still wearing their clothes; which leads into a reading that their knowledge and language are still there. Yet, without their subjectivities, knowledge and languages cannot be used (which is manifested in their lack of intelligence and lack of speech). In other words, this is the manifestation of closed society, a mutism in flesh (pun intended).
Another question sprung up, what are the main causes of this zombie plague? Some initial movies resorted to the explanation of Haitian black magic, yet the newest movies vaguely referred to viral infection. Whether we take side on the black magic (mythical) or biochemical weapon (mechanical cyborgization?), the zombies are all acting the same; following what the source‘programmed’/ ‘dictated’ them to do. Interestingly, this source successfully killed the body and reanimated them as some kind of slaves.
 Similarity in this ‘society’/’hordes’ indicates soulless society, brainwashed into throwing away their very essence of identity and uniqueness and rendering their ability to think (critically) useless. According to Freirean perspective, this is one of the characteristic of a closed society led by a dictator / tyrant. In Education for Critical Consciousness, Paulo Freire (1973) described massification as a characteristic of a closed society imposed by the leader to avoid any coup d’etat. Within this massification process, any citizen should not be given any opportunity to develop critical thinking –similar to zombies inability to thinkand speak – and is expected to behave uniformly. This massification will create‘obedient’ domesticated civilians, separated from total project and consequently being dehumanised.
Similarity in this ‘society’/’hordes’ indicates soulless society, brainwashed into throwing away their very essence of identity and uniqueness and rendering their ability to think (critically) useless. According to Freirean perspective, this is one of the characteristic of a closed society led by a dictator / tyrant. In Education for Critical Consciousness, Paulo Freire (1973) described massification as a characteristic of a closed society imposed by the leader to avoid any coup d’etat. Within this massification process, any citizen should not be given any opportunity to develop critical thinking –similar to zombies inability to thinkand speak – and is expected to behave uniformly. This massification will create‘obedient’ domesticated civilians, separated from total project and consequently being dehumanised.
Before the perspective of this closed society, social norms are changed. Freirean concept of sui generis democracy explains that popular silence (mutism) and inaction is synonymous with healthy society. Thus, people who try to bring about critical thinking will be seen as ‘subversive’ and ‘public enemy’. This branding as a public enemy is what caused them to be crushed under people power; manifested as the attack of zombie hordes towards the protagonists.
Further similarity between zombie apocalypse and mutism also lies in the trigger to the zombie attack. In most movies, the zombies are attracted by any sound and sudden movement. Any voice breaking the silence of the zombieland will be treated as a threat to be taken care of; triggering flock attack. What would happen then after the attack? The victim will either be dead or turned into zombie; both results in mutism and submersion.
It was started with the routine geek pajama parties I often held in my house with fellow geeks. Well, these chaps would certainly refuse the ‘geek’ label I used in this writing. Yet, what would you call four chaps having sleepovers for days only to play some video games? The year was 2001,back when the first Sony Play Station was still ruling and winning the third console war.
Some franchises stood out among the others, some titles flunked dramatically. One of the standing out franchises was Bio Hazard / Resident Evil. It became our challenge night by night, how to finish this thrilling silent game with sound effects amplified through gigantic room speaker in the darkness where the only light we had came from the TV screen and the green PSX LED. Ah, what a moment.
What is so special from the hordes of undead corpse flocking the world in search of fresh brains? They are less cool than their blood-sucking vampiric cousins, the perpetually seductive witches or the ever-furry werewolf neighbours. I don’t know. I honestly don’t know. The market was also saturated already with constant exposure to these rotting bodies.
Yet the key to understand zombies are the concept of bodies through body culture studies perspective. Body is defined by Maurice Merleau-Ponty (1968) as Flesh, the being, and the appearance of oneself. This conceptual flesh puts body as an integral part of the mind, consequently in unity with main drive of any action. The integration with a force of will thus placed body in the position of a subject, as meaning, and as embodied existence.
Butler (in Bodies ThatMatter, 1993) argued that body acts or performs its own subjectivity,devoid of any influence from constructed reality and expectation from surrounding society. The seclusion of subjectivity from any expectation thus signified ‘body’ as the core identity; initial identity. Furthermore, body is theorised as “matter”, so that the cultural norms that constitute its identity can be exposed, examined, and critique. This is the state of nakedness, a complete strip off where self identity is broken down into Democritus’ concept of atom,the state where further division is no longer possible.
Thus, the common concept of basic identity is the result of negotiation / dialogue between the materiality of body and the materiality of knowledge and language. Within this framework, each aspect is materialised;manifested into solid matter. The solidification of two parties creates real spatial context of dialogue between them. Taking the nature of knowledge and language as being able to be controlled by any person, the dialogal practice taking place here follows an ideal Bakhtinian dialogism. A horizontal power structure wherein no party dominates the other operates here, creating an ideal negotiation and neutral adjustment.
Different situation may happen when culture is included here, as the nature of culture sometimes forces any person to bestow before it,the conquering nature over any individual living within its authority. An inclusion of culture in the dialogal practice would turn the natural dialogue into cyborgization. Following Donna Haraway’s (1997) concept of post-humanism,culture and social norms posses the machinization ability; operates as a gigantic mother brain penetrating the skin of the fleshed out body and replacing the natural parts with mechanical prosthetic. However, in doing so,not all of the flesh parts are taken out, creating power struggle between the nature and the machine.
If we are taking an analogy of natural connection between flesh and knowledge and language into a man taking material and sew them into clothes, we can see that the skin still acts as a border between these two parties. Even though the unity between body and clothing can be seen, body will perform its own subjectivity to counter willful construction, in turn creates a clear distinction of constructional aspects. The difference here is the skin as a liminal field, the meeting point of body and construction. However, in the cyborgization, the skin is violated and instead being replaced by mechanical layers. The loss of liminal quality in the skin renders the construction aspects indistinguishable from the flesh.
The term power struggle consequently brings about the shift from horizontal dialogue into vertical dialogue; where one side reclaimed dominance over the others; Foucauldian scheme of war and oppression. Thestruggle between personal “body” and machinization
What about zombie? Using body cultural studies, we can scrutinise the implicit meaning behind dead ‘body’; dead ‘flesh’. What does it mean then? If (living) body can perform its own subjectivity, then zombie cannot perform their own subjectivity. Even though they are living, their freewill is taken from them. Without subjectivity, their main driving force, their main existence, and their very core are robbed. Interestingly, these zombies are still wearing their clothes; which leads into a reading that their knowledge and language are still there. Yet, without their subjectivities, knowledge and languages cannot be used (which is manifested in their lack of intelligence and lack of speech). In other words, this is the manifestation of closed society, a mutism in flesh (pun intended).
Another question sprung up, what are the main causes of this zombie plague? Some initial movies resorted to the explanation of Haitian black magic, yet the newest movies vaguely referred to viral infection. Whether we take side on the black magic (mythical) or biochemical weapon (mechanical cyborgization?), the zombies are all acting the same; following what the source‘programmed’/ ‘dictated’ them to do. Interestingly, this source successfully killed the body and reanimated them as some kind of slaves.
 Similarity in this ‘society’/’hordes’ indicates soulless society, brainwashed into throwing away their very essence of identity and uniqueness and rendering their ability to think (critically) useless. According to Freirean perspective, this is one of the characteristic of a closed society led by a dictator / tyrant. In Education for Critical Consciousness, Paulo Freire (1973) described massification as a characteristic of a closed society imposed by the leader to avoid any coup d’etat. Within this massification process, any citizen should not be given any opportunity to develop critical thinking –similar to zombies inability to thinkand speak – and is expected to behave uniformly. This massification will create‘obedient’ domesticated civilians, separated from total project and consequently being dehumanised.
Similarity in this ‘society’/’hordes’ indicates soulless society, brainwashed into throwing away their very essence of identity and uniqueness and rendering their ability to think (critically) useless. According to Freirean perspective, this is one of the characteristic of a closed society led by a dictator / tyrant. In Education for Critical Consciousness, Paulo Freire (1973) described massification as a characteristic of a closed society imposed by the leader to avoid any coup d’etat. Within this massification process, any citizen should not be given any opportunity to develop critical thinking –similar to zombies inability to thinkand speak – and is expected to behave uniformly. This massification will create‘obedient’ domesticated civilians, separated from total project and consequently being dehumanised. Before the perspective of this closed society, social norms are changed. Freirean concept of sui generis democracy explains that popular silence (mutism) and inaction is synonymous with healthy society. Thus, people who try to bring about critical thinking will be seen as ‘subversive’ and ‘public enemy’. This branding as a public enemy is what caused them to be crushed under people power; manifested as the attack of zombie hordes towards the protagonists.
Further similarity between zombie apocalypse and mutism also lies in the trigger to the zombie attack. In most movies, the zombies are attracted by any sound and sudden movement. Any voice breaking the silence of the zombieland will be treated as a threat to be taken care of; triggering flock attack. What would happen then after the attack? The victim will either be dead or turned into zombie; both results in mutism and submersion.
Published on October 31, 2013 21:18
October 23, 2013
Unheimlich
Unheimlich
adalah ikan yang dikeluarkan dari air
berkelebat-kelebit panik mencari napas
di penghujung hayatnya
mencoba mengulur waktu
walau bimbang
mengingat belaian sungai
atau mempersiapkan diri menuju ajal
serta ragu
antara maju penuh sakit
atau mundur yang tak mungkin
atau bertahan di antara
dan tak berdaya
sama seperti saat ia
ada di batas
hidup dan mati
saat dilahirkan
adalah ikan yang dikeluarkan dari air
berkelebat-kelebit panik mencari napas
di penghujung hayatnya
mencoba mengulur waktu
walau bimbang
mengingat belaian sungai
atau mempersiapkan diri menuju ajal
serta ragu
antara maju penuh sakit
atau mundur yang tak mungkin
atau bertahan di antara
dan tak berdaya
sama seperti saat ia
ada di batas
hidup dan mati
saat dilahirkan
Published on October 23, 2013 06:06



